main |
sidebar

supported by deditsabit
supported by deditsabit
Jumlah Posting & Komentar:
buah artikel telah ditulis
buah komentar masuk


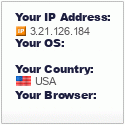



supported by deditsabit
supported by deditsabit
deditsabit bekerjasama dengan dan atas dukungan:
kidz music community, desakuArt production, crew forsil songolas, sahabat forsil songolas, sekolah rakyat merdeka, perguruan rakyat merdeka, sekretariat anak merdeka indonesia, sanggar alif kaligrafi, sanggar mata air, exsongolas management, ponpes daarul rahman jakarta, ponpes an-nuqayah sumenep, boom cell cellulare, tunas trans solusindo, semeru scooter club '06 klakah, komunitas indie lumajang, solidaritas buruh migran indonesia - jawa timur, peduli buruh migran, prakarsa rakyat, bulletin sadar, praxis, dll.
(mohon maaf jika ada yang belum disebutkan)
terima kasih atas kunjungan anda, kritik saran yang membangun adalah kunci keberhasilan kami.
deditsabit@smara

supported by deditsabit
play musik gue
blogroll gue
menurut label
- adsense (1)
- advokasi (2)
- anak (8)
- artikel (11)
- bakat (1)
- bisnis (2)
- budaya (3)
- bulletin sadar (198)
- buruh (1)
- buruh migran (10)
- cdma (1)
- cellulare (4)
- cerita gambar (2)
- deditsabit (4)
- elektronik (2)
- energi (1)
- event (5)
- facebook (4)
- gsm (1)
- ham (1)
- hukum (2)
- informatika (6)
- internet (4)
- jejaring (2)
- kartun (1)
- kdrt (1)
- kesehatan (4)
- kesenian (1)
- keyakinan (8)
- komputer (3)
- konservasi (1)
- korupsi (2)
- lingkungan (2)
- lomba (1)
- lumajang (1)
- maulid hijau (1)
- movie review (19)
- muhammad saw. (1)
- musik (14)
- nuklir (1)
- olah raga (4)
- pendidikan (7)
- perda (1)
- perempuan (9)
- Perguruan Rakyat Merdeka (56)
- peristiwa (7)
- politik (70)
- prestasi (1)
- produk (1)
- qur'an (1)
- radiasi (1)
- religi (9)
- remaja (9)
- resensi buku (27)
- rohani (3)
- sejarah (4)
- serial number (1)
- siswa (1)
- software (1)
- sosial (3)
- ssc '06 klakah (2)
- teknologi (3)
- tv kabel (2)
- undang-undang (1)
- undangan (3)
- video (2)
- website (1)
- wisata (1)
ngikut gak ni...?
statistik blog:
buah artikel telah ditulis
buah komentar masuk

supported by deditsabit
Oleh : Fitri Bintang Timur*
Violence can be justifiable, but it will never be legitimate
(Kekerasan bisa saja dilegalkan, tapi tidak pernah mendapatkan legitimasinya)
Hannah Arendt, Crises of the Republic, 1972
Tindak kekerasan di negara ini telah sampai pada tataran yang mengkhawatirkan. Bukan hanya karena kekerasan terjadi di banyak lini –mulai dari atas nama agama, hingga usaha cari uang yang berakhir dengan bentrok petugas keamanan diskotik– tapi juga karena adanya proses pelegalan dari tindakan tersebut.
Contoh nyata dari ini adalah adanya jaringan preman yang membuka usaha security alias satpam; Forum Pembela Islam (FPI) yang masih bebas melakukan aksi kekerasan melalui ancaman dan tindakan lainnya; serta Protap Anarki milik Polri. Kondisi bagaimana kekerasan bertransformasi dari tindakan kriminal menjadi sesuatu yang legal ini perlu dicermati.
Kekerasan Legal versi Masyarakat
Bentuk yang jelas terlihat, namun sering dihiraukan, dari upaya legalisasi kekerasan di masyarakat adalah bagaimana preman menemukan tempatnya dalam bisnis keamanan. Misalnya saja geng Ambon Basri Sangaji, dimana pemimpin geng telah terbunuh pada tahun 2007, kini menjadi Grup Haji Luhung yang melakukan usaha kolektor (debt collector). Juga grup preman Herkules yang dulu merupakan jawara di Tanah Abang, sekarang memiliki beberapa perusahaan pemasok satpam untuk kantor-kantor di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat.
Usaha jasa keamanan ini besar perputaran dananya, hal yang diakui oleh Ketua Perhimpunan Pengusaha Rekreasi dan Hiburan Umum (PPRHU) Andrian Maelite. Menurut Andrian, sekitar 20% dari pendapatan 400 club, bar, panti pijat dan diskotik di Jakarta digunakan untuk membayar jasa keamanan. Jumlahnya bisa mencapai Rp. 360 milyar per tahun (Jakarta Post, 1/11).
Selain uang, upaya preman dan pengusaha mencari dasar hukum resmi untuk bisnis kekerasan adalah karena ketatnya persaingan. Dahulu di antara penyedia jasa keamanan preman terjadi perang pada November 1998. Saat itu geng Ambon dan preman berbasis agama, yakni FPI, bentrok di Jl. Ketapang, Jakarta Pusat. Bentrokan ini menewaskan 16 orang serta membakar sejumlah gedung dan gereja. Sedikit yang tahu bahwa bentrok tersebut disebabkan oleh perebutan jatah preman untuk membayar jasa keamanan.
Melemahnya preman yang berasal dari Indonesia bagian timur karena kejaran polisi, membuat naiknya premanisme berbasis daerah dan agama terutama di kota-kota besar, seperti Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi), Forum Betawi Rempug (FBR) dan FPI. Hal ini membuat para preman membuka usaha bisnis satpam ke perusahaan, sementara ormas-ormas ini menargetkan figur publik dan event besar, misalnya pembuatan film Mengejar Miyabi. Namun tidak semuanya sukses mencari legalisasi untuk tindakannya, misalnya saja Komando Laskar Islam (KLI) yang harus menghadapi tuntutan karena tindak kekerasannya atas Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Umat Beragama di Monas, Juni 2008.
Pencarian legalitas kekerasan masyarakat sipil tidak selalu diawali dengan membuat badan hukum formal, tapi bisa juga dengan mencari pendukung melalui agama mayoritas negara. Kekerasan terhadap Ahmadiyah yang dilakukan oleh FPI dan KLI, misalnya, akhirnya mendapatkan legalisasinya dengan Surat Keputusan Bersama dari Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung. Sebegitu suksesnya mobilisasi kekerasan pada Ahmadiyah, bahkan pemerintah Lombok Barat menawarkan mereka untuk pindah ke pulau untuk usaha pengamanannya.
Kekerasan Legal versi Penegak Hukum
Tidak hanya di masyarakat umum, aparat penegak hukum negara lebih lagi membutuhkan legalitas dalam mempraktekkan kekerasan. Kapolri Timur Pradopo belum sebulan menjabat posisi barunya, namun ia sudah harus memberi tanggapan atas Protap Penanggulangan Anarki No. 1/X/2010 yang dikeluarkan pendahulunya Kapolri Bambang H. Danuri.
Jenderal Timur menyatakan bahwa Protap tersebut bukan ditujukan untuk demonstran namun untuk mengatasi kekerasan yang dihadapi oleh aparat kepolisian sendiri ataupun bentrok antar massa (Media Indonesia, 28/10). Sementara Kapolri terdahulu, Jenderal BHD menyatakan bahwa pengeluaran Protap ini merupakan reaksi dari kerusuhan di Tarakan, Kaltim; bentrok massa di depan PN Jakarta Selatan di Ampera; kerusuhan di Lebak, Banten; dan penyerangan Polsek Hamparan Perak, Medan. Konflik-konflik ini menimbulkan kebingungan bagaimana polisi merespon karena dianggap tidak adanya kewenangan untuk tembak di tempat, akhirnya keluarlah Protap tersebut.
Permasalahan terjadi ketika Protap ini tidak disertai prosedur pelaksanaan di lapangan sehingga timbul masalah ketika polisi menembak demonstran. Kondisi ini terjadi pada 20 Oktober lalu saat demo setahun pemerintahan SBY Periode II, dimana seorang mahasiswa Universitas Bung Karno tertembak kakinya ketika demo berubah ricuh. Karena insiden tesebut, enam polisi diperiksa dan harus melewati sidang disiplin. Sampai saat ini upaya legalisasi kekerasan aparat kepolisian sendiri belumlah seberhasil preman, yang mana menjadi masalah tersendiri bagi perlindungan masyarakat sipil. Namun idealnya, kekerasan bukanlah jalan keluar yang mampu membawa kedamaian yang langgeng (perpetual peace).
Keluar dari Siklus Kekerasan
Bila membawa teori ke dalam fenomena legalisasi kekerasan, Hannah Arendt memiliki pendapat yang cukup tajam. Menurutnya kekerasan adalah cara untuk mendapatkan kekuasaan (power). Kekerasan digunakan untuk membuat orang patuh pada suruhan penguasa. Arent membedakan antara legalisasi kekerasan dan legitimasi kekerasan. Kekerasan dapat dilegalisasi melalui seperangkat proses hukum, melalui alasan dan pembenaran; namun tidak pernah mendapat legitimasi atau pembenarannya.
Riset yang dilakukan Arent menyatakan bahwa kekuasaan yang didapat dengan cara kekerasan memiliki power lebih kecil dibandingkan dengan kekuasaan yang diraih dengan jalan tanpa kekerasan. Contohnya kekejaman Kaisar Nero dan Kaligula yang justru menghilangkan legitimasi kekuasaan mereka. Tentu saja sebagai penguasa, keduanya melakukan proses legalisasi kekerasan, namun akhirnya justru menjadi kontraproduktif karena ‘membisukan’ dialog.
Aksi main gebuk adalah bentuk ketidakmampuan masyarakat kita untuk berdialog, berbicara dan mendengar. Mungkin selama ini kita tuli terhadap orang miskin yang berkata 'lapar' sehingga harus merampok, memalak dan akhirnya menjadi preman. Kemudian polisi yang merasa terancam melakukan kekerasan lebih kuat lagi. Namun masalah tidak akan selesai dengan kekerasan, kita hanya memupuk siklusnya, melahirkan gerilya-gerilya kecil, kelompok separatis yang sakit hati yang terus ada dan menjadi duri dalam daging. Maka ada baiknya kita mulai bicara, mulai mendengar, dan mencari solusi yang lebih beradab untuk menyelesaikan masalah bersama.
* Penulis adalah Periset IDSPS dan Master bidang Manajemen Pertahanan Keamanan ITB-Cranfield UK, sekaligus Anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Jabodetabek.
** Siapa saja dipersilahkan mengutip, menggandakan, menyebarluaskan sebagian atau seluruh materi yang termuat dalam portal ini selama untuk kajian dan mendukung gerakan rakyat. Untuk keperluan komersial pengguna harus mendapatkan ijin tertulis dari pengelola portal Prakarsa Rakyat. Setiap pengutipan, penggandaan dan penyebarluasan sebagian atau seluruh materi harus mencantumkan sumber (portal Prakarsa Rakyat atau www.prakarsa-rakyat.org).
Melemahnya preman yang berasal dari Indonesia bagian timur karena kejaran polisi, membuat naiknya premanisme berbasis daerah dan agama terutama di kota-kota besar, seperti Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi), Forum Betawi Rempug (FBR) dan FPI. Hal ini membuat para preman membuka usaha bisnis satpam ke perusahaan, sementara ormas-ormas ini menargetkan figur publik dan event besar, misalnya pembuatan film Mengejar Miyabi. Namun tidak semuanya sukses mencari legalisasi untuk tindakannya, misalnya saja Komando Laskar Islam (KLI) yang harus menghadapi tuntutan karena tindak kekerasannya atas Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Umat Beragama di Monas, Juni 2008.
Pencarian legalitas kekerasan masyarakat sipil tidak selalu diawali dengan membuat badan hukum formal, tapi bisa juga dengan mencari pendukung melalui agama mayoritas negara. Kekerasan terhadap Ahmadiyah yang dilakukan oleh FPI dan KLI, misalnya, akhirnya mendapatkan legalisasinya dengan Surat Keputusan Bersama dari Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung. Sebegitu suksesnya mobilisasi kekerasan pada Ahmadiyah, bahkan pemerintah Lombok Barat menawarkan mereka untuk pindah ke pulau untuk usaha pengamanannya.
Kekerasan Legal versi Penegak Hukum
Tidak hanya di masyarakat umum, aparat penegak hukum negara lebih lagi membutuhkan legalitas dalam mempraktekkan kekerasan. Kapolri Timur Pradopo belum sebulan menjabat posisi barunya, namun ia sudah harus memberi tanggapan atas Protap Penanggulangan Anarki No. 1/X/2010 yang dikeluarkan pendahulunya Kapolri Bambang H. Danuri.
Jenderal Timur menyatakan bahwa Protap tersebut bukan ditujukan untuk demonstran namun untuk mengatasi kekerasan yang dihadapi oleh aparat kepolisian sendiri ataupun bentrok antar massa (Media Indonesia, 28/10). Sementara Kapolri terdahulu, Jenderal BHD menyatakan bahwa pengeluaran Protap ini merupakan reaksi dari kerusuhan di Tarakan, Kaltim; bentrok massa di depan PN Jakarta Selatan di Ampera; kerusuhan di Lebak, Banten; dan penyerangan Polsek Hamparan Perak, Medan. Konflik-konflik ini menimbulkan kebingungan bagaimana polisi merespon karena dianggap tidak adanya kewenangan untuk tembak di tempat, akhirnya keluarlah Protap tersebut.
Permasalahan terjadi ketika Protap ini tidak disertai prosedur pelaksanaan di lapangan sehingga timbul masalah ketika polisi menembak demonstran. Kondisi ini terjadi pada 20 Oktober lalu saat demo setahun pemerintahan SBY Periode II, dimana seorang mahasiswa Universitas Bung Karno tertembak kakinya ketika demo berubah ricuh. Karena insiden tesebut, enam polisi diperiksa dan harus melewati sidang disiplin. Sampai saat ini upaya legalisasi kekerasan aparat kepolisian sendiri belumlah seberhasil preman, yang mana menjadi masalah tersendiri bagi perlindungan masyarakat sipil. Namun idealnya, kekerasan bukanlah jalan keluar yang mampu membawa kedamaian yang langgeng (perpetual peace).
Keluar dari Siklus Kekerasan
Bila membawa teori ke dalam fenomena legalisasi kekerasan, Hannah Arendt memiliki pendapat yang cukup tajam. Menurutnya kekerasan adalah cara untuk mendapatkan kekuasaan (power). Kekerasan digunakan untuk membuat orang patuh pada suruhan penguasa. Arent membedakan antara legalisasi kekerasan dan legitimasi kekerasan. Kekerasan dapat dilegalisasi melalui seperangkat proses hukum, melalui alasan dan pembenaran; namun tidak pernah mendapat legitimasi atau pembenarannya.
Riset yang dilakukan Arent menyatakan bahwa kekuasaan yang didapat dengan cara kekerasan memiliki power lebih kecil dibandingkan dengan kekuasaan yang diraih dengan jalan tanpa kekerasan. Contohnya kekejaman Kaisar Nero dan Kaligula yang justru menghilangkan legitimasi kekuasaan mereka. Tentu saja sebagai penguasa, keduanya melakukan proses legalisasi kekerasan, namun akhirnya justru menjadi kontraproduktif karena ‘membisukan’ dialog.
Aksi main gebuk adalah bentuk ketidakmampuan masyarakat kita untuk berdialog, berbicara dan mendengar. Mungkin selama ini kita tuli terhadap orang miskin yang berkata 'lapar' sehingga harus merampok, memalak dan akhirnya menjadi preman. Kemudian polisi yang merasa terancam melakukan kekerasan lebih kuat lagi. Namun masalah tidak akan selesai dengan kekerasan, kita hanya memupuk siklusnya, melahirkan gerilya-gerilya kecil, kelompok separatis yang sakit hati yang terus ada dan menjadi duri dalam daging. Maka ada baiknya kita mulai bicara, mulai mendengar, dan mencari solusi yang lebih beradab untuk menyelesaikan masalah bersama.
* Penulis adalah Periset IDSPS dan Master bidang Manajemen Pertahanan Keamanan ITB-Cranfield UK, sekaligus Anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Jabodetabek.
** Siapa saja dipersilahkan mengutip, menggandakan, menyebarluaskan sebagian atau seluruh materi yang termuat dalam portal ini selama untuk kajian dan mendukung gerakan rakyat. Untuk keperluan komersial pengguna harus mendapatkan ijin tertulis dari pengelola portal Prakarsa Rakyat. Setiap pengutipan, penggandaan dan penyebarluasan sebagian atau seluruh materi harus mencantumkan sumber (portal Prakarsa Rakyat atau www.prakarsa-rakyat.org).
Labels: bulletin sadar
0 Comments:
d-i-s-c-l-a-i-m-e-r
games tools
- agent waste
- asstroidz
- billyard
- binatang kembar
- blok 2
- bounce
- bullet snale 3
- cavern klamrisk
- chicken invaders roty
- dynomite deluxe
- feeding frenzy 2
- freeciv 2.1.9
- hell chess
- insaniquarium
- luxor
- monopoly
- moto
- pandaland
- picross mania
- pizza frenzy
- sponge bob collapse
- standing point the final stronghold
- the power
- zuma deluxe
temen gue
- adsense for feeds
- anang's blog
- angkatan sembilan belas
- babu ngeblog
- blog oranje
- blogger templates bycaz
- btemplates
- catatan dunia ira
- daleclick templates
- densu-nod
- desakuArt production
- dua mata
- facebook sunnah
- foto tanpa genre
- free blogger template layout
- free musicz mp3
- free templates
- hujan musik indonesia
- imam marsus
- indo bloger
- indo lawas
- indo metal box
- islam substantif
- karim samman
- kidz music community
- klasik rock indonesia
- lumajang music community
- media putra
- mr. ozay's blog
- music 4 sharing
- nona cantiq
- peduli buruh migran
- pers bebas, pintu demokrasi
- rindu pulang
- sanggar alif kaligrafi
- sanggar mata air
- soft 4 u
- template unik
- tunas trans solusindo
- tutorial jitu
- uc1n blog's
- underground indonesia
- unduh musik
- upex rock
- wonogiri voucher
bookmarks gue
- angel fire
- anymaking
- blog lines
- blog template 4u
- blogspot template
- blogspot templetes
- cbm card
- club brillian (id: cgd935029)
- currency converter
- cyber fret
- dhanny dhuzell site's
- dynamic tools drive
- editing foto online
- ez wp themes
- free templates online
- free warebb
- gpro tab
- gudang lagu
- guitar about
- guitar chords/scales
- guitarists
- hot frets
- html-kit-favicon
- indo mp3
- indonesia mp3
- indrakila band
- inilah indie
- isnaini blogger templates
- lumajang music
- mozilla themes
- mozilla themes
- mp3 indonesia
- musician
- musisi
- nolkoma band
- pax
- pp. daarul rahman jakarta
- rubby band
- sekolah rakyat indonesia
- smart telecom
- speed test
- speed test smart
- stafa band
- tab crawler
- tagihan pln jatim
- translator online (babelfish)
- translator online (toggle text)
- universitas terbuka
- warung mp3
- warung musik
- web2 feel
- youtube
kidz music community, desakuArt production, crew forsil songolas, sahabat forsil songolas, sekolah rakyat merdeka, perguruan rakyat merdeka, sekretariat anak merdeka indonesia, sanggar alif kaligrafi, sanggar mata air, exsongolas management, ponpes daarul rahman jakarta, ponpes an-nuqayah sumenep, boom cell cellulare, tunas trans solusindo, semeru scooter club '06 klakah, komunitas indie lumajang, solidaritas buruh migran indonesia - jawa timur, peduli buruh migran, prakarsa rakyat, bulletin sadar, praxis, dll.
(mohon maaf jika ada yang belum disebutkan)
terima kasih atas kunjungan anda, kritik saran yang membangun adalah kunci keberhasilan kami.
deditsabit@smara
thanks for the template design to skinCorner | grunged girl image from dapinoGraphics



