main |
sidebar

supported by deditsabit
supported by deditsabit
Jumlah Posting & Komentar:
buah artikel telah ditulis
buah komentar masuk


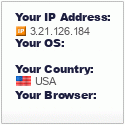



supported by deditsabit
supported by deditsabit
deditsabit bekerjasama dengan dan atas dukungan:
kidz music community, desakuArt production, crew forsil songolas, sahabat forsil songolas, sekolah rakyat merdeka, perguruan rakyat merdeka, sekretariat anak merdeka indonesia, sanggar alif kaligrafi, sanggar mata air, exsongolas management, ponpes daarul rahman jakarta, ponpes an-nuqayah sumenep, boom cell cellulare, tunas trans solusindo, semeru scooter club '06 klakah, komunitas indie lumajang, solidaritas buruh migran indonesia - jawa timur, peduli buruh migran, prakarsa rakyat, bulletin sadar, praxis, dll.
(mohon maaf jika ada yang belum disebutkan)
terima kasih atas kunjungan anda, kritik saran yang membangun adalah kunci keberhasilan kami.
deditsabit@smara

supported by deditsabit
play musik gue
blogroll gue
menurut label
- adsense (1)
- advokasi (2)
- anak (8)
- artikel (11)
- bakat (1)
- bisnis (2)
- budaya (3)
- bulletin sadar (198)
- buruh (1)
- buruh migran (10)
- cdma (1)
- cellulare (4)
- cerita gambar (2)
- deditsabit (4)
- elektronik (2)
- energi (1)
- event (5)
- facebook (4)
- gsm (1)
- ham (1)
- hukum (2)
- informatika (6)
- internet (4)
- jejaring (2)
- kartun (1)
- kdrt (1)
- kesehatan (4)
- kesenian (1)
- keyakinan (8)
- komputer (3)
- konservasi (1)
- korupsi (2)
- lingkungan (2)
- lomba (1)
- lumajang (1)
- maulid hijau (1)
- movie review (19)
- muhammad saw. (1)
- musik (14)
- nuklir (1)
- olah raga (4)
- pendidikan (7)
- perda (1)
- perempuan (9)
- Perguruan Rakyat Merdeka (56)
- peristiwa (7)
- politik (70)
- prestasi (1)
- produk (1)
- qur'an (1)
- radiasi (1)
- religi (9)
- remaja (9)
- resensi buku (27)
- rohani (3)
- sejarah (4)
- serial number (1)
- siswa (1)
- software (1)
- sosial (3)
- ssc '06 klakah (2)
- teknologi (3)
- tv kabel (2)
- undang-undang (1)
- undangan (3)
- video (2)
- website (1)
- wisata (1)
ngikut gak ni...?
statistik blog:
buah artikel telah ditulis
buah komentar masuk

supported by deditsabit
Buletin SADAR Edisi: 325 Tahun VI - 2010, ISSN: 2086-2024, PAHLAWAN DEVISA: SUMBANGSIH BESAR, MINIM PERLINDUNGAN
Oleh : Rinto Tri Hasworo*
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
(Pasal 27 Ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia)
Kasus Sumiati kembali menyadarkan kita bahwa persoalan buruh migran belum selesai. Masih banyak hal yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi warga negaranya yang bekerja di luar negeri, terutama untuk pekerjaan sektor domestik. Kasus penyiksaan Sumiati merupakan kasus kesekian yang menghentakkan nurani kemanusiaan kita dan melemparkan harga diri bangsa ke titik yang paling rendah.
Ketika Sumiati masih tergolek lemah di ruang perawatan, kita kembali dikejutkan dengan berita buruh migran bernama Kikim Komalasari, TKW asal Sukabumi. Nasibnya jauh lebih tragis. Ia tewas di tangan majikan kemudian mayatnya ditemukan di tempat sampah. Mengerikan, nyawa seorang manusia disetarakan dengan sampah. Alam pikiran kita (yang waras) tentu tidak bisa membayangkan bagaimana manusia bisa memperlakukan manusia lain dengan perlakuan sebiadab itu.
Pola Rekrutmen
Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri mengamanatkan bahwa pelaksana penempatan buruh migran terdiri dari pemerintah dan pelaksana penempatan swasta (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia – PJTKI). Dalam praktiknya, PJTKI mengambil peran lebih besar dalam pelaksanaan penempatan buruh migran. Lebih ironis lagi, PJTKI lebih banyak mengirim buruh migran untuk sektor yang sangat rentan, yaitu pembantu rumah tangga (PRT). Ini disebabkan karena PRT bekerja dalam lingkungan yang terbatas (terisolir).
Bermain dalam bisnis penempatan jelas memberikan keuntungan yang tidak sedikit, maka bisa dipahami para PJTKI berlomba merekrut calon buruh migran hingga pelosok desa. Padahal, perekrutan calon buruh migran harus disesuaikan dengan job order. Pada kenyataannya, ada atau tidak ada job order PJTKI tetap melakukan perekrutan. Mereka menerapkan sistem “ready stock.” Calon buruh migran direkrut dengan berbagai iming-iming. Mereka ditampung dalam barak penampungan (yang lebih mirip ruang isolasi), tanpa kepastian kapan akan diberangkatkan. Sistem ini (“ready stock”) jelas telah menempatkan buruh migran sebagai komoditi.
Tingginya permintaan buruh migran di luar negeri (terutama untuk sektor domestik) mendorong PJTKI menciptakan berbagai strategi jitu dalam merekrut calon buruh migran. Dengan memberikan imbalan yang lebih besar, PJTKI menempatkan calo sebagai ujung tombak perekrutan. Mereka masuk ke desa-desa, terutama desa miskin, untuk mencari calon buruh migran. Iming-iming mereka berikan untuk meyakinkan sang calon: gaji besar, kondisi kerja yang enak, diberi pelatihan atau pendidikan keterampilan, penampungan yang nyaman, memberikan uang saku kepada calon TKI dan keluarganya selama TKI belum memperoleh gaji. Semua tentu tidak gratis, karena mereka harus membayar dari gaji yang akan mereka terima.
Para calo juga rela merogoh kocek pribadi untuk memberangkatkan TKI, sebesar dua hingga lima juta rupiah per orang. Nantinya, seluruh biaya tersebut diganti oleh agen dan PJTKI. Imbalan bagi para calo ini bervariasi. Untuk pemula, upah biasanya berkisar Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta setiap merekrut orang. Peran para calo tidak hanya berhenti pada proses perekrutan, masalah dokumen pun bisa diurusnya. Calo menyediakan jasa mengurus surat identitas palsu. Mulai dari kartu keluarga hingga kartu tanda penduduk. Kartu identitas palsu mudah dikantongi, tentunya dengan memanipulasi usia calon TKI. Dan pastinya dengan uang pelicin. Tak banyak, hanya Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribu, aparat pun bisa diajak bermain mata (Gerilya Pemburu TKI ABG, Tim Sigi SCTV, 2010).
Minimnya pengawasan terhadap praktik PJTKI, menyebabkan berbagai kasus kriminal dilakukan atau melibatkan PJTKI. Mulai dari pemalsuan dokumen, pemerasan, perdagangan manusia (human trafficking), penipuan, dan tindak kriminal lainnya. Untuk itu, pola perekrutan harus dirubah, mekanisme pengawasanpun harus diperkuat. Tidak bisa lagi PJTKI, apalagi calo, dengan leluasa ‘menjemput bola’ hingga ke desa-desa. Peran pemerintah melalui Kemenakertrans dan Dinas-dinas Tenaga Kerja di daerah harus lebih dioptimalkan. PJTKI sebaiknya tidak diperkenankan menempatkan buruh migran pada sektor-sektor yang memiliki tingkat kerentanan tinggi. Tugas itu harus dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Ketenagakerjaan di daerah-daerah yang berperan sebagai pelaksana penempatan.
Dinamika di Tempat Kerja
Sulit membayangkan jika selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kita tidak dapat menghubungi atau mengetahui kabar anggota keluarga yang bekerja di luar negeri. Padahal, mereka bekerja di negara yang cukup maju dengan sarana komunikasi (telepon) yang canggih. Mereka seakan lenyap ‘tertelan’ bumi setelah tiba di negara tujuan bekerja. Tapi, inilah realitas yang dihadapi ribuan keluarga buruh migran. Tidak jarang sebagian dari buruh migran baru diketahui nasib dan keberadaannya setelah menjadi korban penganiayaan majikannya. Mencari anggota keluarga yang menjadi buruh migran seakan mencari jarum yang jatuh di padang pasir.
Kajan adalah salah seorang yang bertahun-tahun tidak dapat mengetahui nasib dan keberadaan anaknya, Sunesih. Sunesih seperti lenyap tertelan bumi Arab Saudi setelah ia diberangkatkan pada 27 Mei 2007. Berbagai upaya telah dilakukan Kajan dan anggota keluarga lain untuk memperoleh kepastian kondisi Sunesih. Mulai dari menghubungi perusahaan penyalur hingga menghubungi majikannya di Arab Saudi. Namun kabar tentang Sunesih tidak juga ia peroleh.
Setelah bolak-balik mendatangi dan mendesak perusahaan penyalur, barulah Kajan memperoleh kabar bahwa Sunesih sudah meninggal. Ironisnya, kabar kematian Sunesih baru diperoleh Kajan tanggal 12 Agustus 2010. Padahal menurut catatan yang ada Sunesih meninggal tanggal 18 Juli 2007. Artinya Kajan baru mengetahui kematian anaknya setelah tiga tahun Sunesih meninggal dunia (Kompas, 22/11/2010).
Setelah kasus Sumiati dan Kikim mengemuka, berbagai reaksi bermunculan menyikapi nasib kedua buruh migran ini dan kebijakan ketenagakerjaan migran. Akses komunikasi dan informasi kepada tiap buruh migran menjadi salah satu sorotan penting. Tidak adanya akses ke dan dari TKI menyebabkan tidak adanya pemantauan terhadap nasib TKI. Untuk meretas persoalan ini, Presiden SBY mengusulkan agar tiap TKI dibekali telepon seluler (HP). Alasannya, jika terjadi sesuatu, mereka (buruh migran) bisa segera berkomunikasi dengan pejabat perwakilan RI di negara tempat bekerja. Ide yang cemerlang namun naif jika kita melihat hubungan kerja antara buruh migran dengan majikannya.
Bisa memiliki dan menggunakan HP atau sarana komunikasi lainnya di tempat bekerja merupakan suatu ‘kemewahan’ bagi buruh migran. Sebab, jangankan alat komunikasi sekelas HP, buku saku yang berisi catatan alamat dan nomor telepon perwakilan RI atau lembaga-lembaga yang dapat dihubungi buruh migran jika mengalami masalah pun ditahan majikan. Termasuk dokumen keimigrasian buruh migran. Mungkin SBY (berlagak) lupa, bahwa ia pun menyetujui majikan menahan dokumen buruh migran lewat nota kesepahaman (MoU) ketenagakerjaan migran dengan Pemerintahan Malaysia.
Penahanan dokumen oleh majikan tidak hanya berimplikasi pada perendahan martabat bangsa, namun juga berimplikasi pada nasib dan status buruh migran. Dengan ditahannya dokumen maka memaksa buruh untuk tetap ‘setia’ pada majikan, sekalipun kondisi kerja lebih mirip perbudakan. Jika buruh migran nekat memlih kabur, maka ia harus siap dengan status sebagai buruh migran ‘ilegal.’ Artinya, penahanan dokumen oleh majikan menjadi salah satu penyebab lahirnya buruh migran ‘ilegal’ (Atase Tenaga Kerja & Perlindungan TKI , antara Indonesia–Singapura–Malaysia, The Institute for Ecosoc Rights, 2010).
Buruh Migran dan Sumbangsihnya
Dalam hal remitansi tentu tidak ada pembicaraan mengenai sumbernya: dari buruh migran legal atau ilegal. Sebagaimana yang kerap terjadi dalam penanganan buruh migran yang sedang menghadapi masalah, yang kerap mempersoalkan status (legal ilegal) buruh migran.
Desakan ekonomi dan kesederhanaan berpikir menyebabkan sebagian besar buruh migran tidak menyadari bahwa tiap lembar mata uang asing yang ia peroleh dan kirimkan ke tanah air memberikan sumbangan yang luar biasa terhadap cadangan devisa dan pembangunan negeri ini. Namun demikian kesederhanaan berpikir, ketidakmengertian tentang kalkulasi politik dan ekonomi buruh migran tidak serta-merta membuat negera menjadi abai terhadap tanggung jawabnya memberikan perhatian dan perlindungan kepada mereka.
Remitansi menjadi primadona bagi negara untuk ‘menebalkan’ pundi-pundi devisa. Menurut Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), penempatan TKI di luar negeri hingga awal Februari 2010 mencapai 2.679.536 orang. Pemasukan devisa dari remitansi TKI pada 2009 mencapai USD 8,2 miliar. Remitansi nasional pada 2006-2009 masing-masing mencapai USD 5,56 miliar, USD 6 miliar, USD 8,24 miliar, dan USD 8,2 miliar. Dengan 2.679.536 orang warga negaranya yang bekerja di luar negeri, negara melalui Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menargetkan angka remitansi dari TKI pada 2010 sebesar USD10 miliar atau naik 21,95 persen dibanding 2009 (okezone.com).
Tidak hanya negara, bisnis perbankan pun berebut dan bersaing untuk mereguk keuntungan dari remitansi. Persaingan menajam manakala bank nasional yang mayoritas sahamnya dikuasi oleh pihak asing pun terjun ke pasar remitansi. Untuk memenangi persaingan sengit itu, beberapa bank nasional menempatkan perwakilannya di bank koresponden di luar negeri. Tengok saja, BNI sebagai pemimpin pasar telah menempatkan remittance representative di Malaysia dan negara-negara Timur Tengah, seperti Arab Saudi, United Arab Emirates (UAE) untuk menjemput bola bisnis remitansi langsung dari sumbernya. Perwakilan yang semula tingkat analis kini ditingkatkan hingga level manajer bahkan assistant vice president(AVP) (okezone.com).
Mulai negara hingga bisnis perbankan mereguk keuntungan dari keringat buruh migran dalam bentuk remitansi. Kondisi ini ironis dengan nasib buruh migran. Tidak ada skema perlindungan yang memadai bagi mereka, seakan mereka dibiarkan hidup dan bekerja berdampingan dengan kerentanannya di luar negeri. Perhatian bagi mereka pun masih sangat minim. Kalaupun ada, sifatnya kasuistik, datang bergelombang manakala media massa melakukan ekspos berita terhadap buruh migran yang sedang menghadapi masalah. Mereda dan hilang tertelan waktu dan berita-berita lain yang lebih ‘seksi.’
Sumbangsih buruh migran kepada ekonomi negara tidak sebanding dengan perlindungan yang mereka terima dari pemerintah. Berbagai kasus yang mendera buruh migran masih terus saja terjadi, jumlahnya pun terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk kasus kematian buruh migran Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa jumlah buruh migran Indonesia yang meninggal di luar negeri sepanjang 2009 mencapai 1.107 jiwa atau naik 124 persen, dibandingkan angka kematian buruh migran tahun sebelumnya, 494 jiwa.
Sedangkan untuk kasus penganiayaan, pada tahun 2009 sebanyak 4.822 kasus. Jumlahnyapun meningkat tajam jika dibandingkan tahun sebelumnya, 3.470. Dan sakit akibat kerja 10.153. Masalah lainnya adalah PHK sepihak oleh Majikan. PHK sepihak merupakan kasus terbesar yang dialami buruh migran Indonesia, jumlahnya 13.155 kasus (Republika Online, 11/2/2010).
Sumiati dan Kikim: Babak Akhir Masalah Buruh Migran?
Sama dengan kasus-kasus yang menimpa buruh migran sebelumnya, kasus Sumiati dan Kikim juga dianggap sebagai momentum yang baik untuk menata kembali sistem ketenagakerjaan buruh migran. Mulai dari membuat MoU ketenagakerjaan migran yang berpihak pada buruh migran dengan negara-negara tujuan bekerja (khususnya Arab Saudi), moratorium pengiriman buruh migran ke negara-negara Arab hingga menghentikan samasekali pengiriman buruh migran ke Arab Saudi.
Sejatinya, dalam melihat persoalan buruh migran tidak hanya ‘mengutuk’ kebijakan ketenagakerjaan migran negara tujuan bekerja, namun juga mesti melihat dan membenahi sistem (perlindungan) ketenagakerjaan migran di dalam negeri. Baik peraturan perundang-undangan maupun kelembagaan yang berkaitan dengan kebijakan ketenagakerjaan migran.
Undang-Undang nomor 39 tahun 2004 jelas sudah tidak memadai lagi untuk mengatasi persoalan buruh migran. Selain karena lebih banyak mengatur soal bisnis penempatan ketimbang perlindungan buruh migran, sejumlah pasal krusial undang-undang ini juga melahirkan multi tafsir.
Lembaga yang memiliki mandat khusus untuk memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap ketenagakerjaan migran pun mendesak untuk dibentuk, apapun namanya. Karena Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) juga sudah tidak memadai lagi untuk memberikan perlindungan, karena lembaga ini juga berperan sebagai pelaksana penempatan.
Kita tentu berharap kasus Sumiati dan Kikim sungguh menjadi momentum untuk dilakukannnya perubahan mendasar dalam sistem ketenagakerjaan migran negara kita. Tidak seperti kasus-kasus Nirmala Bona, Ceriati, Siti Hajar. Menggema ketika lukanya masih menganga. Hilang tertelan waktu dan kasus-kasus lain. Jangankan menjadikannya sebagai pintu masuk membuat perubahan, (proses hukum) kasusnya pun tidak jelas rimbanya.
Lewat Sumiati dan Almarhumah Kikim Komalasari kita tetap berharap dan mendesak pemerintah untuk melakukan yang terbaik bagi buruh migran atau calon migran. Memenuhi hak buruh migran adalah memenuhi hak asasi manusia, karena hak buruh migran adalah hak asasi manusia.
* Penulis adalah Advokat, Peneliti pada Institute for Ecosoc Rights, sekaligus Anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Jabodetabek.
** Siapa saja dipersilahkan mengutip, menggandakan, menyebarluaskan sebagian atau seluruh materi yang termuat dalam portal ini selama untuk kajian dan mendukung gerakan rakyat. Untuk keperluan komersial pengguna harus mendapatkan ijin tertulis dari pengelola portal Prakarsa Rakyat. Setiap pengutipan, penggandaan dan penyebarluasan sebagian atau seluruh materi harus mencantumkan sumber (portal Prakarsa Rakyat atau www.prakarsa-rakyat.org).
Kajan adalah salah seorang yang bertahun-tahun tidak dapat mengetahui nasib dan keberadaan anaknya, Sunesih. Sunesih seperti lenyap tertelan bumi Arab Saudi setelah ia diberangkatkan pada 27 Mei 2007. Berbagai upaya telah dilakukan Kajan dan anggota keluarga lain untuk memperoleh kepastian kondisi Sunesih. Mulai dari menghubungi perusahaan penyalur hingga menghubungi majikannya di Arab Saudi. Namun kabar tentang Sunesih tidak juga ia peroleh.
Setelah bolak-balik mendatangi dan mendesak perusahaan penyalur, barulah Kajan memperoleh kabar bahwa Sunesih sudah meninggal. Ironisnya, kabar kematian Sunesih baru diperoleh Kajan tanggal 12 Agustus 2010. Padahal menurut catatan yang ada Sunesih meninggal tanggal 18 Juli 2007. Artinya Kajan baru mengetahui kematian anaknya setelah tiga tahun Sunesih meninggal dunia (Kompas, 22/11/2010).
Setelah kasus Sumiati dan Kikim mengemuka, berbagai reaksi bermunculan menyikapi nasib kedua buruh migran ini dan kebijakan ketenagakerjaan migran. Akses komunikasi dan informasi kepada tiap buruh migran menjadi salah satu sorotan penting. Tidak adanya akses ke dan dari TKI menyebabkan tidak adanya pemantauan terhadap nasib TKI. Untuk meretas persoalan ini, Presiden SBY mengusulkan agar tiap TKI dibekali telepon seluler (HP). Alasannya, jika terjadi sesuatu, mereka (buruh migran) bisa segera berkomunikasi dengan pejabat perwakilan RI di negara tempat bekerja. Ide yang cemerlang namun naif jika kita melihat hubungan kerja antara buruh migran dengan majikannya.
Bisa memiliki dan menggunakan HP atau sarana komunikasi lainnya di tempat bekerja merupakan suatu ‘kemewahan’ bagi buruh migran. Sebab, jangankan alat komunikasi sekelas HP, buku saku yang berisi catatan alamat dan nomor telepon perwakilan RI atau lembaga-lembaga yang dapat dihubungi buruh migran jika mengalami masalah pun ditahan majikan. Termasuk dokumen keimigrasian buruh migran. Mungkin SBY (berlagak) lupa, bahwa ia pun menyetujui majikan menahan dokumen buruh migran lewat nota kesepahaman (MoU) ketenagakerjaan migran dengan Pemerintahan Malaysia.
Penahanan dokumen oleh majikan tidak hanya berimplikasi pada perendahan martabat bangsa, namun juga berimplikasi pada nasib dan status buruh migran. Dengan ditahannya dokumen maka memaksa buruh untuk tetap ‘setia’ pada majikan, sekalipun kondisi kerja lebih mirip perbudakan. Jika buruh migran nekat memlih kabur, maka ia harus siap dengan status sebagai buruh migran ‘ilegal.’ Artinya, penahanan dokumen oleh majikan menjadi salah satu penyebab lahirnya buruh migran ‘ilegal’ (Atase Tenaga Kerja & Perlindungan TKI , antara Indonesia–Singapura–Malaysia, The Institute for Ecosoc Rights, 2010).
Buruh Migran dan Sumbangsihnya
Dalam hal remitansi tentu tidak ada pembicaraan mengenai sumbernya: dari buruh migran legal atau ilegal. Sebagaimana yang kerap terjadi dalam penanganan buruh migran yang sedang menghadapi masalah, yang kerap mempersoalkan status (legal ilegal) buruh migran.
Desakan ekonomi dan kesederhanaan berpikir menyebabkan sebagian besar buruh migran tidak menyadari bahwa tiap lembar mata uang asing yang ia peroleh dan kirimkan ke tanah air memberikan sumbangan yang luar biasa terhadap cadangan devisa dan pembangunan negeri ini. Namun demikian kesederhanaan berpikir, ketidakmengertian tentang kalkulasi politik dan ekonomi buruh migran tidak serta-merta membuat negera menjadi abai terhadap tanggung jawabnya memberikan perhatian dan perlindungan kepada mereka.
Remitansi menjadi primadona bagi negara untuk ‘menebalkan’ pundi-pundi devisa. Menurut Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), penempatan TKI di luar negeri hingga awal Februari 2010 mencapai 2.679.536 orang. Pemasukan devisa dari remitansi TKI pada 2009 mencapai USD 8,2 miliar. Remitansi nasional pada 2006-2009 masing-masing mencapai USD 5,56 miliar, USD 6 miliar, USD 8,24 miliar, dan USD 8,2 miliar. Dengan 2.679.536 orang warga negaranya yang bekerja di luar negeri, negara melalui Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menargetkan angka remitansi dari TKI pada 2010 sebesar USD10 miliar atau naik 21,95 persen dibanding 2009 (okezone.com).
Tidak hanya negara, bisnis perbankan pun berebut dan bersaing untuk mereguk keuntungan dari remitansi. Persaingan menajam manakala bank nasional yang mayoritas sahamnya dikuasi oleh pihak asing pun terjun ke pasar remitansi. Untuk memenangi persaingan sengit itu, beberapa bank nasional menempatkan perwakilannya di bank koresponden di luar negeri. Tengok saja, BNI sebagai pemimpin pasar telah menempatkan remittance representative di Malaysia dan negara-negara Timur Tengah, seperti Arab Saudi, United Arab Emirates (UAE) untuk menjemput bola bisnis remitansi langsung dari sumbernya. Perwakilan yang semula tingkat analis kini ditingkatkan hingga level manajer bahkan assistant vice president(AVP) (okezone.com).
Mulai negara hingga bisnis perbankan mereguk keuntungan dari keringat buruh migran dalam bentuk remitansi. Kondisi ini ironis dengan nasib buruh migran. Tidak ada skema perlindungan yang memadai bagi mereka, seakan mereka dibiarkan hidup dan bekerja berdampingan dengan kerentanannya di luar negeri. Perhatian bagi mereka pun masih sangat minim. Kalaupun ada, sifatnya kasuistik, datang bergelombang manakala media massa melakukan ekspos berita terhadap buruh migran yang sedang menghadapi masalah. Mereda dan hilang tertelan waktu dan berita-berita lain yang lebih ‘seksi.’
Sumbangsih buruh migran kepada ekonomi negara tidak sebanding dengan perlindungan yang mereka terima dari pemerintah. Berbagai kasus yang mendera buruh migran masih terus saja terjadi, jumlahnya pun terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk kasus kematian buruh migran Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa jumlah buruh migran Indonesia yang meninggal di luar negeri sepanjang 2009 mencapai 1.107 jiwa atau naik 124 persen, dibandingkan angka kematian buruh migran tahun sebelumnya, 494 jiwa.
Sedangkan untuk kasus penganiayaan, pada tahun 2009 sebanyak 4.822 kasus. Jumlahnyapun meningkat tajam jika dibandingkan tahun sebelumnya, 3.470. Dan sakit akibat kerja 10.153. Masalah lainnya adalah PHK sepihak oleh Majikan. PHK sepihak merupakan kasus terbesar yang dialami buruh migran Indonesia, jumlahnya 13.155 kasus (Republika Online, 11/2/2010).
Sumiati dan Kikim: Babak Akhir Masalah Buruh Migran?
Sama dengan kasus-kasus yang menimpa buruh migran sebelumnya, kasus Sumiati dan Kikim juga dianggap sebagai momentum yang baik untuk menata kembali sistem ketenagakerjaan buruh migran. Mulai dari membuat MoU ketenagakerjaan migran yang berpihak pada buruh migran dengan negara-negara tujuan bekerja (khususnya Arab Saudi), moratorium pengiriman buruh migran ke negara-negara Arab hingga menghentikan samasekali pengiriman buruh migran ke Arab Saudi.
Sejatinya, dalam melihat persoalan buruh migran tidak hanya ‘mengutuk’ kebijakan ketenagakerjaan migran negara tujuan bekerja, namun juga mesti melihat dan membenahi sistem (perlindungan) ketenagakerjaan migran di dalam negeri. Baik peraturan perundang-undangan maupun kelembagaan yang berkaitan dengan kebijakan ketenagakerjaan migran.
Undang-Undang nomor 39 tahun 2004 jelas sudah tidak memadai lagi untuk mengatasi persoalan buruh migran. Selain karena lebih banyak mengatur soal bisnis penempatan ketimbang perlindungan buruh migran, sejumlah pasal krusial undang-undang ini juga melahirkan multi tafsir.
Lembaga yang memiliki mandat khusus untuk memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap ketenagakerjaan migran pun mendesak untuk dibentuk, apapun namanya. Karena Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) juga sudah tidak memadai lagi untuk memberikan perlindungan, karena lembaga ini juga berperan sebagai pelaksana penempatan.
Kita tentu berharap kasus Sumiati dan Kikim sungguh menjadi momentum untuk dilakukannnya perubahan mendasar dalam sistem ketenagakerjaan migran negara kita. Tidak seperti kasus-kasus Nirmala Bona, Ceriati, Siti Hajar. Menggema ketika lukanya masih menganga. Hilang tertelan waktu dan kasus-kasus lain. Jangankan menjadikannya sebagai pintu masuk membuat perubahan, (proses hukum) kasusnya pun tidak jelas rimbanya.
Lewat Sumiati dan Almarhumah Kikim Komalasari kita tetap berharap dan mendesak pemerintah untuk melakukan yang terbaik bagi buruh migran atau calon migran. Memenuhi hak buruh migran adalah memenuhi hak asasi manusia, karena hak buruh migran adalah hak asasi manusia.
* Penulis adalah Advokat, Peneliti pada Institute for Ecosoc Rights, sekaligus Anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Jabodetabek.
** Siapa saja dipersilahkan mengutip, menggandakan, menyebarluaskan sebagian atau seluruh materi yang termuat dalam portal ini selama untuk kajian dan mendukung gerakan rakyat. Untuk keperluan komersial pengguna harus mendapatkan ijin tertulis dari pengelola portal Prakarsa Rakyat. Setiap pengutipan, penggandaan dan penyebarluasan sebagian atau seluruh materi harus mencantumkan sumber (portal Prakarsa Rakyat atau www.prakarsa-rakyat.org).
Sumber: Prakarsa Rakyat
Labels: bulletin sadar
0 Comments:
d-i-s-c-l-a-i-m-e-r
games tools
- agent waste
- asstroidz
- billyard
- binatang kembar
- blok 2
- bounce
- bullet snale 3
- cavern klamrisk
- chicken invaders roty
- dynomite deluxe
- feeding frenzy 2
- freeciv 2.1.9
- hell chess
- insaniquarium
- luxor
- monopoly
- moto
- pandaland
- picross mania
- pizza frenzy
- sponge bob collapse
- standing point the final stronghold
- the power
- zuma deluxe
temen gue
- adsense for feeds
- anang's blog
- angkatan sembilan belas
- babu ngeblog
- blog oranje
- blogger templates bycaz
- btemplates
- catatan dunia ira
- daleclick templates
- densu-nod
- desakuArt production
- dua mata
- facebook sunnah
- foto tanpa genre
- free blogger template layout
- free musicz mp3
- free templates
- hujan musik indonesia
- imam marsus
- indo bloger
- indo lawas
- indo metal box
- islam substantif
- karim samman
- kidz music community
- klasik rock indonesia
- lumajang music community
- media putra
- mr. ozay's blog
- music 4 sharing
- nona cantiq
- peduli buruh migran
- pers bebas, pintu demokrasi
- rindu pulang
- sanggar alif kaligrafi
- sanggar mata air
- soft 4 u
- template unik
- tunas trans solusindo
- tutorial jitu
- uc1n blog's
- underground indonesia
- unduh musik
- upex rock
- wonogiri voucher
bookmarks gue
- angel fire
- anymaking
- blog lines
- blog template 4u
- blogspot template
- blogspot templetes
- cbm card
- club brillian (id: cgd935029)
- currency converter
- cyber fret
- dhanny dhuzell site's
- dynamic tools drive
- editing foto online
- ez wp themes
- free templates online
- free warebb
- gpro tab
- gudang lagu
- guitar about
- guitar chords/scales
- guitarists
- hot frets
- html-kit-favicon
- indo mp3
- indonesia mp3
- indrakila band
- inilah indie
- isnaini blogger templates
- lumajang music
- mozilla themes
- mozilla themes
- mp3 indonesia
- musician
- musisi
- nolkoma band
- pax
- pp. daarul rahman jakarta
- rubby band
- sekolah rakyat indonesia
- smart telecom
- speed test
- speed test smart
- stafa band
- tab crawler
- tagihan pln jatim
- translator online (babelfish)
- translator online (toggle text)
- universitas terbuka
- warung mp3
- warung musik
- web2 feel
- youtube
kidz music community, desakuArt production, crew forsil songolas, sahabat forsil songolas, sekolah rakyat merdeka, perguruan rakyat merdeka, sekretariat anak merdeka indonesia, sanggar alif kaligrafi, sanggar mata air, exsongolas management, ponpes daarul rahman jakarta, ponpes an-nuqayah sumenep, boom cell cellulare, tunas trans solusindo, semeru scooter club '06 klakah, komunitas indie lumajang, solidaritas buruh migran indonesia - jawa timur, peduli buruh migran, prakarsa rakyat, bulletin sadar, praxis, dll.
(mohon maaf jika ada yang belum disebutkan)
terima kasih atas kunjungan anda, kritik saran yang membangun adalah kunci keberhasilan kami.
deditsabit@smara
thanks for the template design to skinCorner | grunged girl image from dapinoGraphics



