main |
sidebar

supported by deditsabit
supported by deditsabit
Jumlah Posting & Komentar:
buah artikel telah ditulis
buah komentar masuk


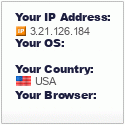



supported by deditsabit
Tujuan pendidikan sejatinya adalah untuk membebaskan manusia dari kebodohan dan kemiskinan. Sistem pendidikan nasional pun mempunyai tujuan mulia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia Indonesia yang berkarakter serta bermoral baik. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, negara berkewajiban melaksanakan pendidikan yang adil dan berkualitas seperti amanat Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya dalam pasal 31 Ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan." Artinya bahwa semua rakyat Indonesia harus memperoleh akses terhadap pendidikan tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama dan status sosial.
Namun, apa jadinya wajah pendidikan ketika dijadikan komoditas (barang dagangan) dan harganya sangat mahal? Fenomena anak bunuh diri karena tidak bisa membayar uang sekolah merupakan salah satu contoh realitas pendidikan. Subsidi pemerintah di sektor pendidikan ternyata belum mampu membantu anak-anak kurang mampu mengakses pendidikan. Buktinya, peserta didik masih dibebani biaya sekolah seperti seragam, buku, uang gedung dan biaya lainnya. Bahkan, untuk biaya seragam saja, orang tua harus “merogeh kocek” sebesar 1,8 juta rupiah. Orang tua siswa yang berasal dari golongan masyarakat miskin tentunya mengalami kesulitan membayar uang seragam sekolah. Supaya anaknya tetap bisa mengenyam pendidikan, orang tua murid terpaksa membeli seragam bekas di pasar “loakan”.
Mahalnya harga seragam di beberapa sekolah merupakan sebuah ironi di sistem pendidikan Indonesia. Institusi pendidikan tidak lagi dimaknai sebagai tempat mencari ilmu dan wadah pencerdasan masyarakat tetapi berubah menjadi tempat jualan pakaian. Momentum tahun ajaran baru ternyata dijadikan pihak sekolah untuk mencari keuntungan. Pihak sekolah menjual seragam dengan harga lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga pakaian sekolah di pasar tradisional. Maraknya praktek jual-beli seragam sekolah dengan harga yang mahal merupakan salah bentuk komersialisasi pendidikan. Sekolah pada akhirnya menjadi tempat “berdagang” untuk mencari profit.
Selain persoalan biaya seragam yang mahal, paradigma yang masih berlaku di institusi pendidikan adalah sistem penyeragaman (uniform). Hampir seluruh sekolah mewajibkan murid-muridnya berpakaian seragam. Misalnya di Sekolah Dasar, seragam yang harus digunakan berwarna Putih-Merah, sepatu hitam, kaos kaki putih. Paradigma penyeragaman pakaian merubah wajah lembaga pendidikan menjadi tempat “fashion show.”
Padahal, kualitas pendidikan tidak ditentukan oleh seragam yang dipakai seorang murid tetapi kecakapan dan kepintaran yang dimiliki. Seragam bukan kebutuhan yang substansial tetapi yang terpenting adalah semua anak bisa sekolah meskipun pakaian mereka berwarna hitam, hijau, biru dan sebagainya. Penyeragaman pakaian akan membebani orang tua murid karena harus mencari dan membeli pakaian yang diwajibkan oleh pihak sekolah. Jika seorang murid tidak mampu berseragam sesuai yang ditentukan oleh pihak sekolah maka kesempatan untuk duduk dibangku sekolah akan hilang.
Pergeseran paradigma pendidikan sangat memprihatinkan. Pendidikan tidak ubahnya sebuah pakaian yang terpajang di mall-mall, hanya yang berduit yang bisa membeli. Seleksi masuk sekolah formal tidak lagi didasarkan pada kemampuan dan kualitas seseorang tetapi berdasarkan “rupiah.” Keadaan seperti ini membuat institusi pendidikan hanya bisa diakses dan dinikmati oleh orang yang berduit banyak sedangkan anak dari tukang becak, anak buruh, anak petani, dan anak dari golongan keluarga miskin hanya bisa menonton dan tentunya semakin bodoh. Keadaan seperti ini tidak ada bedanya dengan kondisi pendidikan pada zaman penjajahan dimana sekolah formal hanya bisa diakses oleh golongan bangsawan yang notabenenya mempunyai uang yang banyak. Padahal, jika mengacu lagi pada Pasal 31 Ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya".
Sangat jelas bahwa negara mempunyai kewajiban untuk mengembangkan pendidikan dari segi pendanaan. Akan tetapi, pendidikan gratis hanya menjadi angan-angan dan harapan yang tidak akan tercapai. Jangankan gratis, alokasi anggaran pendidikan yang diamanatkan oleh UUD, pasal 31 ayat 4 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.” belum tercapai dan terwujud sampai sekarang. Subsidi pendidikan sebesar 20% terealisasi di beberapa daerah. Anggaran 20% pun tidak murni untuk fasilitas pendidikan tetapi juga sudah termasuk gaji guru dan pembiayaan lainnya sehingga dana yang bisa dinikmati oleh anak-anak peserta didik hanya sedikit. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga tidak bisa memberi solusi bagi persoalan pembiayaan di sektor pendidikan.
Apabila pemerintah serius menjalankan amanat Undang-Undang Dasar maka anak-anak bangsa bisa mengakses pendidikan. Pendidikan tanpa biaya (gratis) memberikan kesempatan setiap warga negara untuk bisa sekolah dan pada akhirnya bisa pintar sehingga dapat mengangkat derajat keluarga dan bangsa. Jika paragdigma pendidikan tidak dirubah menjadi lebih adil maka wajah pendidikan di Indonesia akan semakin suram.
* Penulis adalah anggota Keluarga Alumni Mahasiswa Gadjah Mada Yogyakarta, sekaligus Anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Jawa Tengah.
** Siapa saja dipersilahkan mengutip, menggandakan, menyebarluaskan sebagian atau seluruh materi yang termuat dalam portal ini selama untuk kajian dan mendukung gerakan rakyat. Untuk keperluan komersial pengguna harus mendapatkan ijin tertulis dari pengelola portal Prakarsa Rakyat. Setiap pengutipan, penggandaan dan penyebarluasan sebagian atau seluruh materi harus mencantumkan sumber (portal Prakarsa Rakyat atau www.prakarsa-rakyat.org).
supported by deditsabit
deditsabit bekerjasama dengan dan atas dukungan:
kidz music community, desakuArt production, crew forsil songolas, sahabat forsil songolas, sekolah rakyat merdeka, perguruan rakyat merdeka, sekretariat anak merdeka indonesia, sanggar alif kaligrafi, sanggar mata air, exsongolas management, ponpes daarul rahman jakarta, ponpes an-nuqayah sumenep, boom cell cellulare, tunas trans solusindo, semeru scooter club '06 klakah, komunitas indie lumajang, solidaritas buruh migran indonesia - jawa timur, peduli buruh migran, prakarsa rakyat, bulletin sadar, praxis, dll.
(mohon maaf jika ada yang belum disebutkan)
terima kasih atas kunjungan anda, kritik saran yang membangun adalah kunci keberhasilan kami.
deditsabit@smara

supported by deditsabit
play musik gue
blogroll gue
menurut label
- adsense (1)
- advokasi (2)
- anak (8)
- artikel (11)
- bakat (1)
- bisnis (2)
- budaya (3)
- bulletin sadar (198)
- buruh (1)
- buruh migran (10)
- cdma (1)
- cellulare (4)
- cerita gambar (2)
- deditsabit (4)
- elektronik (2)
- energi (1)
- event (5)
- facebook (4)
- gsm (1)
- ham (1)
- hukum (2)
- informatika (6)
- internet (4)
- jejaring (2)
- kartun (1)
- kdrt (1)
- kesehatan (4)
- kesenian (1)
- keyakinan (8)
- komputer (3)
- konservasi (1)
- korupsi (2)
- lingkungan (2)
- lomba (1)
- lumajang (1)
- maulid hijau (1)
- movie review (19)
- muhammad saw. (1)
- musik (14)
- nuklir (1)
- olah raga (4)
- pendidikan (7)
- perda (1)
- perempuan (9)
- Perguruan Rakyat Merdeka (56)
- peristiwa (7)
- politik (70)
- prestasi (1)
- produk (1)
- qur'an (1)
- radiasi (1)
- religi (9)
- remaja (9)
- resensi buku (27)
- rohani (3)
- sejarah (4)
- serial number (1)
- siswa (1)
- software (1)
- sosial (3)
- ssc '06 klakah (2)
- teknologi (3)
- tv kabel (2)
- undang-undang (1)
- undangan (3)
- video (2)
- website (1)
- wisata (1)
ngikut gak ni...?
statistik blog:
buah artikel telah ditulis
buah komentar masuk

supported by deditsabit
Oleh : Akbar Rewako*
Tujuan pendidikan sejatinya adalah untuk membebaskan manusia dari kebodohan dan kemiskinan. Sistem pendidikan nasional pun mempunyai tujuan mulia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia Indonesia yang berkarakter serta bermoral baik. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, negara berkewajiban melaksanakan pendidikan yang adil dan berkualitas seperti amanat Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya dalam pasal 31 Ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan." Artinya bahwa semua rakyat Indonesia harus memperoleh akses terhadap pendidikan tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama dan status sosial.
Namun, apa jadinya wajah pendidikan ketika dijadikan komoditas (barang dagangan) dan harganya sangat mahal? Fenomena anak bunuh diri karena tidak bisa membayar uang sekolah merupakan salah satu contoh realitas pendidikan. Subsidi pemerintah di sektor pendidikan ternyata belum mampu membantu anak-anak kurang mampu mengakses pendidikan. Buktinya, peserta didik masih dibebani biaya sekolah seperti seragam, buku, uang gedung dan biaya lainnya. Bahkan, untuk biaya seragam saja, orang tua harus “merogeh kocek” sebesar 1,8 juta rupiah. Orang tua siswa yang berasal dari golongan masyarakat miskin tentunya mengalami kesulitan membayar uang seragam sekolah. Supaya anaknya tetap bisa mengenyam pendidikan, orang tua murid terpaksa membeli seragam bekas di pasar “loakan”.
Mahalnya harga seragam di beberapa sekolah merupakan sebuah ironi di sistem pendidikan Indonesia. Institusi pendidikan tidak lagi dimaknai sebagai tempat mencari ilmu dan wadah pencerdasan masyarakat tetapi berubah menjadi tempat jualan pakaian. Momentum tahun ajaran baru ternyata dijadikan pihak sekolah untuk mencari keuntungan. Pihak sekolah menjual seragam dengan harga lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga pakaian sekolah di pasar tradisional. Maraknya praktek jual-beli seragam sekolah dengan harga yang mahal merupakan salah bentuk komersialisasi pendidikan. Sekolah pada akhirnya menjadi tempat “berdagang” untuk mencari profit.
Selain persoalan biaya seragam yang mahal, paradigma yang masih berlaku di institusi pendidikan adalah sistem penyeragaman (uniform). Hampir seluruh sekolah mewajibkan murid-muridnya berpakaian seragam. Misalnya di Sekolah Dasar, seragam yang harus digunakan berwarna Putih-Merah, sepatu hitam, kaos kaki putih. Paradigma penyeragaman pakaian merubah wajah lembaga pendidikan menjadi tempat “fashion show.”
Padahal, kualitas pendidikan tidak ditentukan oleh seragam yang dipakai seorang murid tetapi kecakapan dan kepintaran yang dimiliki. Seragam bukan kebutuhan yang substansial tetapi yang terpenting adalah semua anak bisa sekolah meskipun pakaian mereka berwarna hitam, hijau, biru dan sebagainya. Penyeragaman pakaian akan membebani orang tua murid karena harus mencari dan membeli pakaian yang diwajibkan oleh pihak sekolah. Jika seorang murid tidak mampu berseragam sesuai yang ditentukan oleh pihak sekolah maka kesempatan untuk duduk dibangku sekolah akan hilang.
Pergeseran paradigma pendidikan sangat memprihatinkan. Pendidikan tidak ubahnya sebuah pakaian yang terpajang di mall-mall, hanya yang berduit yang bisa membeli. Seleksi masuk sekolah formal tidak lagi didasarkan pada kemampuan dan kualitas seseorang tetapi berdasarkan “rupiah.” Keadaan seperti ini membuat institusi pendidikan hanya bisa diakses dan dinikmati oleh orang yang berduit banyak sedangkan anak dari tukang becak, anak buruh, anak petani, dan anak dari golongan keluarga miskin hanya bisa menonton dan tentunya semakin bodoh. Keadaan seperti ini tidak ada bedanya dengan kondisi pendidikan pada zaman penjajahan dimana sekolah formal hanya bisa diakses oleh golongan bangsawan yang notabenenya mempunyai uang yang banyak. Padahal, jika mengacu lagi pada Pasal 31 Ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya".
Sangat jelas bahwa negara mempunyai kewajiban untuk mengembangkan pendidikan dari segi pendanaan. Akan tetapi, pendidikan gratis hanya menjadi angan-angan dan harapan yang tidak akan tercapai. Jangankan gratis, alokasi anggaran pendidikan yang diamanatkan oleh UUD, pasal 31 ayat 4 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.” belum tercapai dan terwujud sampai sekarang. Subsidi pendidikan sebesar 20% terealisasi di beberapa daerah. Anggaran 20% pun tidak murni untuk fasilitas pendidikan tetapi juga sudah termasuk gaji guru dan pembiayaan lainnya sehingga dana yang bisa dinikmati oleh anak-anak peserta didik hanya sedikit. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga tidak bisa memberi solusi bagi persoalan pembiayaan di sektor pendidikan.
Apabila pemerintah serius menjalankan amanat Undang-Undang Dasar maka anak-anak bangsa bisa mengakses pendidikan. Pendidikan tanpa biaya (gratis) memberikan kesempatan setiap warga negara untuk bisa sekolah dan pada akhirnya bisa pintar sehingga dapat mengangkat derajat keluarga dan bangsa. Jika paragdigma pendidikan tidak dirubah menjadi lebih adil maka wajah pendidikan di Indonesia akan semakin suram.
* Penulis adalah anggota Keluarga Alumni Mahasiswa Gadjah Mada Yogyakarta, sekaligus Anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Jawa Tengah.
** Siapa saja dipersilahkan mengutip, menggandakan, menyebarluaskan sebagian atau seluruh materi yang termuat dalam portal ini selama untuk kajian dan mendukung gerakan rakyat. Untuk keperluan komersial pengguna harus mendapatkan ijin tertulis dari pengelola portal Prakarsa Rakyat. Setiap pengutipan, penggandaan dan penyebarluasan sebagian atau seluruh materi harus mencantumkan sumber (portal Prakarsa Rakyat atau www.prakarsa-rakyat.org).
Sumber: PRAKARSA RAKYAT
Labels: bulletin sadar, pendidikan
0 Comments:
d-i-s-c-l-a-i-m-e-r
games tools
- agent waste
- asstroidz
- billyard
- binatang kembar
- blok 2
- bounce
- bullet snale 3
- cavern klamrisk
- chicken invaders roty
- dynomite deluxe
- feeding frenzy 2
- freeciv 2.1.9
- hell chess
- insaniquarium
- luxor
- monopoly
- moto
- pandaland
- picross mania
- pizza frenzy
- sponge bob collapse
- standing point the final stronghold
- the power
- zuma deluxe
temen gue
- adsense for feeds
- anang's blog
- angkatan sembilan belas
- babu ngeblog
- blog oranje
- blogger templates bycaz
- btemplates
- catatan dunia ira
- daleclick templates
- densu-nod
- desakuArt production
- dua mata
- facebook sunnah
- foto tanpa genre
- free blogger template layout
- free musicz mp3
- free templates
- hujan musik indonesia
- imam marsus
- indo bloger
- indo lawas
- indo metal box
- islam substantif
- karim samman
- kidz music community
- klasik rock indonesia
- lumajang music community
- media putra
- mr. ozay's blog
- music 4 sharing
- nona cantiq
- peduli buruh migran
- pers bebas, pintu demokrasi
- rindu pulang
- sanggar alif kaligrafi
- sanggar mata air
- soft 4 u
- template unik
- tunas trans solusindo
- tutorial jitu
- uc1n blog's
- underground indonesia
- unduh musik
- upex rock
- wonogiri voucher
bookmarks gue
- angel fire
- anymaking
- blog lines
- blog template 4u
- blogspot template
- blogspot templetes
- cbm card
- club brillian (id: cgd935029)
- currency converter
- cyber fret
- dhanny dhuzell site's
- dynamic tools drive
- editing foto online
- ez wp themes
- free templates online
- free warebb
- gpro tab
- gudang lagu
- guitar about
- guitar chords/scales
- guitarists
- hot frets
- html-kit-favicon
- indo mp3
- indonesia mp3
- indrakila band
- inilah indie
- isnaini blogger templates
- lumajang music
- mozilla themes
- mozilla themes
- mp3 indonesia
- musician
- musisi
- nolkoma band
- pax
- pp. daarul rahman jakarta
- rubby band
- sekolah rakyat indonesia
- smart telecom
- speed test
- speed test smart
- stafa band
- tab crawler
- tagihan pln jatim
- translator online (babelfish)
- translator online (toggle text)
- universitas terbuka
- warung mp3
- warung musik
- web2 feel
- youtube
kidz music community, desakuArt production, crew forsil songolas, sahabat forsil songolas, sekolah rakyat merdeka, perguruan rakyat merdeka, sekretariat anak merdeka indonesia, sanggar alif kaligrafi, sanggar mata air, exsongolas management, ponpes daarul rahman jakarta, ponpes an-nuqayah sumenep, boom cell cellulare, tunas trans solusindo, semeru scooter club '06 klakah, komunitas indie lumajang, solidaritas buruh migran indonesia - jawa timur, peduli buruh migran, prakarsa rakyat, bulletin sadar, praxis, dll.
(mohon maaf jika ada yang belum disebutkan)
terima kasih atas kunjungan anda, kritik saran yang membangun adalah kunci keberhasilan kami.
deditsabit@smara
thanks for the template design to skinCorner | grunged girl image from dapinoGraphics



