main |
sidebar

supported by deditsabit
supported by deditsabit
Jumlah Posting & Komentar:
buah artikel telah ditulis
buah komentar masuk


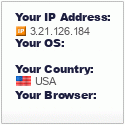



supported by deditsabit
"Saya mengusulkan karena SBY kan doktor, lalu punya tim sukses lagi.
Saya juga doktor. Kalau buku dilawanlah dengan buku." (George Junus Aditjondro)
George Aditjondro menyampaikan tantangan intelektual, mengembalikan tradisi berpikir ilmiah, terhadap pihak-pihak yang menyoal buku barunya, “Membongkar Gurita Cikeas,” bahwa buku harus dibalas buku. Tantangan ini memang berlaku tidak cuma bagi SBY, tapi siapapun yang menganggap sebuah buku melenceng, tidak benar atau tidak patut.
Tulisan ini tidak hendak membincang ribut-ribut yang ditimbulkan buku George, tetapi memang berimpitan, baik waktu maupun obyeknya. Tak berapa lama berselang, Kejaksaan Agung mengambil kebijakan aneh, yakni melarang peredaran 5 buku yang dianggap mengganggu ketertiban umum. Sontak ingatan publik kembali mengarah ke masa-masa orde baru dimana pelarangan buku dan pembredelan media massa jamak terjadi.
Kelima buku itu adalah: Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto karangan John Rosa, Suara Gereja bagi Umat Tertindas Penderitaan Tetesan Darah dan Cucuran Air Mata Umat Tuhan di Papua Barat Harus Diakhiri karangan Cocratez Sofyan Yoman, Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakjat 1950-1965 karya duet Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M Dahlan, Enam Jalan Menuju Tuhan karangan Darmawan dan Mengungkap Misteri Keberagaman Agama karangan Syahrudin Ahmad.
Larangan
Penulis tidak bermaksud mengupas apa dan bagaimana isi buku-buku itu, yang perlu bagi hemat penulis ialah menjejerkan masalah lebih besar tentang arti sebuah pelarangan.
Belum hilang di ingatan kita, di masa Hitler, kekejaman fasisme, benar-benar menjelma tanpa akal sehat, anti intelektualitas. Sedikitnya 20 ribu buku ludes ditelan api, dalam aksi pembakaran buku oleh Hitler sendiri.
Lalu di negeri sendiri, 32 tahun pemerintahan otoriter rezim militeristik, berkali-kali membredel sebuah penerbitan media, mengkampanyekan pelarangan terhadap banyak buku yang dianggap subversif, atau mau mengganggu versi tunggal penguasa dalam mencekoki bacaan masyarakatnya.
Jaman Soeharto, buku-buku yang pernah dilarang misalkan, judul buku “Saya Musuh Politik Soeharto” penulis Sri Bintang Pamungkas, “Seputar Kedung Ombo” penulis Stanley, lalu yang tidak bisa dilupa hampir seluruh karya Pramoedya Ananta Toer, novelis besar yang melahirkan tetralogi pulau Buru, dengan karya roman sejarahnya.
Begitu juga beberapa penerbitan media, Tempo, Detik, Editor di tahun 1994. Beberapa contoh ini sebagai pengingat kembali bagi kita bahwa belum tuntas perubahan nasib rakyat di Indonesia paska Soeharto, belum selesai pula pemahaman kita membangun kesadaran kritis melalui banyak wacana dan aneka bacaan untuk masyarakat..
Dalam dua kali pemilihan presiden yang disebarluaskan hasil pemilihan langsung, demokratis, atau apapun namanya. Tapi pemerintahan terpilih SBY nampaknya memberi kesan suatu sikap yang mewarisi Soeharto, berkarakter otoriter, memberi keleluasaan penuh pada Kejaksaan Agung. Hingga bisa mengeluarkan pelarangan, tanpa menyebutkan kebenaran dan kesalahan apa yang muncul dari penulisan sebuah buku.
Sebuah pelarangan berarti pengebirian kembali terhadap nilai-nilai demokrasi, kebebasan berpendapat untuk menuangkan pemikiran ke dalam sebuah buku. Padahal lewat bukulah, kita akan mendapati informasi yang lebih lengkap, sistematis, terdokumentasikan peristiwa, serta berbagai macam ingatan kita akan sebuah permasalahan yang berkembang.
Pantas saja kampanye membaca dan memiliki buku bagi masyarakat di era pemerintahan ini amat jarang sekali terlihat. Kalau tokh ada, semuanya akan menjadi kontradiktif, dimana pemerintahan sekarang sebaliknya, melarang sejumlah buku beredar.
Otoritarian Orde Baru
Baru-baru ini kita ketahui kalau kegusaran pemerintah yang membalas buku-buku yang dianggap menyudutkan pemerintah, dengan berbagai pernyataan kalau sikap kritis memandang pemerintah disebut sebagai fitnah, kebohongan, dan tak pernah berterimakasih kepada pemerintah.
Pemerintahan yang bersandar pada kaum modal tentu inginnya selalu mendapatkan pujian, dan pujian itupun pastinya datang dari kaum pemodal sendiri. Tapi sebaliknya pemerintahan yang seharusnya melayani masyarakat, dan menjadi abdi rakyat ialah pemerintahan yang tak henti-hentinya memperbaiki sistem dan keadaan yang saat ini justru menjauhkan keadilan sejati, dan kesejahteraan bagi masyarakat.
Dari tulisan ini sekali lagi bermaksud ingin bersama-sama menunjukkan keprihatianan mendalam, dan memberi peringatan dini bagi siapapun yang berseberangan dengan sikap pemerintah, kalau aktivitas ilmiah membaca dan menulis, telah dibungkam secara paksa.
Kondisi ini seharusnya segera dihentikan, dan disudahi, setidaknya ke dalam dua cara yang ditempuh pemerintah sekarang, pertama, pemerintah perlu membangun iklim keterbukaan dan demokrasi yang ekspresinya bisa berkembang menjadi aneka bentuk, baik di dalam diskusi-diskusi, unjuk rasa, serta karya tulis lainnya.
Jika dalam konteks beredarnya buku-buku kritis untuk masyarakat justru amat membantu memperkuat fondasi demokrasi paska rezim status quo Soeharto. Dan apabila presiden SBY terus-menerus membalas setiap penulisan di banyak media, dan buku dengan pernyataan di sana-sini dengan mengumbar kata-kata fitnah, lama-kelamaan malah semakin memperkeruh nuansa kebebasan berpendapat. Atau memang inilah bentuk kebebasan berpendapat dari sosok presiden SBY.
Akan tetapi alangkah lebih elegannya pemerintahan SBY, jikalau setiap karya-karya tulis dan buku juga dibalas dengan sanggahan, pendapat dan argumentasi yang sama-sama bisa dipertanggungjawabkan dan diperdebatkan di tengah-tengah rakyat. Agar rakyat tahu, dan menarik kesimpulan untuk menentukan buku-buku mana yang patut dibaca.
Kedua, menghentikan pelarangan buku mencabut seluruh aturan pelarangan yang dikeluarkan Kejaksaan Agung, karena telah melanggar hak azasi menulis, dan berkarya. Kita ketahui sudah ada UU HAM yang mengatur tentang hak ini. Dan justru dalil Kejaksaan Agung yang menyebutkan bahwa pelarangan buku-buku seperti di atas dianggap menggangu ketertiban umum, UUD 1945, dan Pancasila.
Malahan ketiga alasan yang disebut bertabrakan dalam aturannya sendiri. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (bunyi sila ke 5) Pancasila, bisa dianggap bentuk ekspresi secara adil kepada seluruh rakyat untuk menulis dan menerbtikan tulisan-tulisannya ke dalam bentuk buku-buku.
Dalam UUD 1945, kita ketahui juga kalau konstitusi ini ialah yang tertinggi dari seluruh aturan dan UU yang ada.. Maka dalam pasal 28 (UUD 1945 asli) bukan hasil amandemen, jelas melindungi hak kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapatnya.
Kejaksaan Agung dalam hal ini kembali membodoh-bodohi rakyat atas nama UUD 1945 dan Pancasila, padahal Kejaksaan Agung-lah yang tidak menjalankan apa itu semangat dan nilai, serta isi yang terkandung di dalam Pancasila dan UUD 1945.
Lalu apa lagi yang akan dilakukan oleh pemerintahan SBY jika buku sudah dilarang, seringkali memakai alasan aturan-aturan mengada-ada, tanpa memerhatikan bahwa di bawah rezim neoliberalis kesejahteraan rakyat hanya retorika, suara kritis mulai dibungkam?
* Penulis adalah penikmat buku yang dibredel negara, sekaligus Anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Jabodetabek.
** Siapa saja dipersilahkan mengutip, menggandakan, menyebarluaskan sebagian atau seluruh materi yang termuat dalam portal ini selama untuk kajian dan mendukung gerakan rakyat. Untuk keperluan komersial pengguna harus mendapatkan ijin tertulis dari pengelola portal Prakarsa Rakyat. Setiap pengutipan, penggandaan dan penyebarluasan sebagian atau seluruh materi harus mencantumkan sumber (portal Prakarsa Rakyat atau www.prakarsa-rakyat.org).
supported by deditsabit
deditsabit bekerjasama dengan dan atas dukungan:
kidz music community, desakuArt production, crew forsil songolas, sahabat forsil songolas, sekolah rakyat merdeka, perguruan rakyat merdeka, sekretariat anak merdeka indonesia, sanggar alif kaligrafi, sanggar mata air, exsongolas management, ponpes daarul rahman jakarta, ponpes an-nuqayah sumenep, boom cell cellulare, tunas trans solusindo, semeru scooter club '06 klakah, komunitas indie lumajang, solidaritas buruh migran indonesia - jawa timur, peduli buruh migran, prakarsa rakyat, bulletin sadar, praxis, dll.
(mohon maaf jika ada yang belum disebutkan)
terima kasih atas kunjungan anda, kritik saran yang membangun adalah kunci keberhasilan kami.
deditsabit@smara

supported by deditsabit
play musik gue
blogroll gue
menurut label
- adsense (1)
- advokasi (2)
- anak (8)
- artikel (11)
- bakat (1)
- bisnis (2)
- budaya (3)
- bulletin sadar (198)
- buruh (1)
- buruh migran (10)
- cdma (1)
- cellulare (4)
- cerita gambar (2)
- deditsabit (4)
- elektronik (2)
- energi (1)
- event (5)
- facebook (4)
- gsm (1)
- ham (1)
- hukum (2)
- informatika (6)
- internet (4)
- jejaring (2)
- kartun (1)
- kdrt (1)
- kesehatan (4)
- kesenian (1)
- keyakinan (8)
- komputer (3)
- konservasi (1)
- korupsi (2)
- lingkungan (2)
- lomba (1)
- lumajang (1)
- maulid hijau (1)
- movie review (19)
- muhammad saw. (1)
- musik (14)
- nuklir (1)
- olah raga (4)
- pendidikan (7)
- perda (1)
- perempuan (9)
- Perguruan Rakyat Merdeka (56)
- peristiwa (7)
- politik (70)
- prestasi (1)
- produk (1)
- qur'an (1)
- radiasi (1)
- religi (9)
- remaja (9)
- resensi buku (27)
- rohani (3)
- sejarah (4)
- serial number (1)
- siswa (1)
- software (1)
- sosial (3)
- ssc '06 klakah (2)
- teknologi (3)
- tv kabel (2)
- undang-undang (1)
- undangan (3)
- video (2)
- website (1)
- wisata (1)
ngikut gak ni...?
statistik blog:
buah artikel telah ditulis
buah komentar masuk

supported by deditsabit
Bulletin SADAR Edisi: 262 Tahun V - 2009, PELARANGAN BUKU, MELEJITNYA KEGANASAN OTORITARIAN NEOLIBERALIS
Oleh Eka Pangulimara Hutajulu *
"Saya mengusulkan karena SBY kan doktor, lalu punya tim sukses lagi.
Saya juga doktor. Kalau buku dilawanlah dengan buku." (George Junus Aditjondro)
George Aditjondro menyampaikan tantangan intelektual, mengembalikan tradisi berpikir ilmiah, terhadap pihak-pihak yang menyoal buku barunya, “Membongkar Gurita Cikeas,” bahwa buku harus dibalas buku. Tantangan ini memang berlaku tidak cuma bagi SBY, tapi siapapun yang menganggap sebuah buku melenceng, tidak benar atau tidak patut.
Tulisan ini tidak hendak membincang ribut-ribut yang ditimbulkan buku George, tetapi memang berimpitan, baik waktu maupun obyeknya. Tak berapa lama berselang, Kejaksaan Agung mengambil kebijakan aneh, yakni melarang peredaran 5 buku yang dianggap mengganggu ketertiban umum. Sontak ingatan publik kembali mengarah ke masa-masa orde baru dimana pelarangan buku dan pembredelan media massa jamak terjadi.
Kelima buku itu adalah: Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto karangan John Rosa, Suara Gereja bagi Umat Tertindas Penderitaan Tetesan Darah dan Cucuran Air Mata Umat Tuhan di Papua Barat Harus Diakhiri karangan Cocratez Sofyan Yoman, Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakjat 1950-1965 karya duet Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M Dahlan, Enam Jalan Menuju Tuhan karangan Darmawan dan Mengungkap Misteri Keberagaman Agama karangan Syahrudin Ahmad.
Larangan
Penulis tidak bermaksud mengupas apa dan bagaimana isi buku-buku itu, yang perlu bagi hemat penulis ialah menjejerkan masalah lebih besar tentang arti sebuah pelarangan.
Belum hilang di ingatan kita, di masa Hitler, kekejaman fasisme, benar-benar menjelma tanpa akal sehat, anti intelektualitas. Sedikitnya 20 ribu buku ludes ditelan api, dalam aksi pembakaran buku oleh Hitler sendiri.
Lalu di negeri sendiri, 32 tahun pemerintahan otoriter rezim militeristik, berkali-kali membredel sebuah penerbitan media, mengkampanyekan pelarangan terhadap banyak buku yang dianggap subversif, atau mau mengganggu versi tunggal penguasa dalam mencekoki bacaan masyarakatnya.
Jaman Soeharto, buku-buku yang pernah dilarang misalkan, judul buku “Saya Musuh Politik Soeharto” penulis Sri Bintang Pamungkas, “Seputar Kedung Ombo” penulis Stanley, lalu yang tidak bisa dilupa hampir seluruh karya Pramoedya Ananta Toer, novelis besar yang melahirkan tetralogi pulau Buru, dengan karya roman sejarahnya.
Begitu juga beberapa penerbitan media, Tempo, Detik, Editor di tahun 1994. Beberapa contoh ini sebagai pengingat kembali bagi kita bahwa belum tuntas perubahan nasib rakyat di Indonesia paska Soeharto, belum selesai pula pemahaman kita membangun kesadaran kritis melalui banyak wacana dan aneka bacaan untuk masyarakat..
Dalam dua kali pemilihan presiden yang disebarluaskan hasil pemilihan langsung, demokratis, atau apapun namanya. Tapi pemerintahan terpilih SBY nampaknya memberi kesan suatu sikap yang mewarisi Soeharto, berkarakter otoriter, memberi keleluasaan penuh pada Kejaksaan Agung. Hingga bisa mengeluarkan pelarangan, tanpa menyebutkan kebenaran dan kesalahan apa yang muncul dari penulisan sebuah buku.
Sebuah pelarangan berarti pengebirian kembali terhadap nilai-nilai demokrasi, kebebasan berpendapat untuk menuangkan pemikiran ke dalam sebuah buku. Padahal lewat bukulah, kita akan mendapati informasi yang lebih lengkap, sistematis, terdokumentasikan peristiwa, serta berbagai macam ingatan kita akan sebuah permasalahan yang berkembang.
Pantas saja kampanye membaca dan memiliki buku bagi masyarakat di era pemerintahan ini amat jarang sekali terlihat. Kalau tokh ada, semuanya akan menjadi kontradiktif, dimana pemerintahan sekarang sebaliknya, melarang sejumlah buku beredar.
Otoritarian Orde Baru
Baru-baru ini kita ketahui kalau kegusaran pemerintah yang membalas buku-buku yang dianggap menyudutkan pemerintah, dengan berbagai pernyataan kalau sikap kritis memandang pemerintah disebut sebagai fitnah, kebohongan, dan tak pernah berterimakasih kepada pemerintah.
Pemerintahan yang bersandar pada kaum modal tentu inginnya selalu mendapatkan pujian, dan pujian itupun pastinya datang dari kaum pemodal sendiri. Tapi sebaliknya pemerintahan yang seharusnya melayani masyarakat, dan menjadi abdi rakyat ialah pemerintahan yang tak henti-hentinya memperbaiki sistem dan keadaan yang saat ini justru menjauhkan keadilan sejati, dan kesejahteraan bagi masyarakat.
Dari tulisan ini sekali lagi bermaksud ingin bersama-sama menunjukkan keprihatianan mendalam, dan memberi peringatan dini bagi siapapun yang berseberangan dengan sikap pemerintah, kalau aktivitas ilmiah membaca dan menulis, telah dibungkam secara paksa.
Kondisi ini seharusnya segera dihentikan, dan disudahi, setidaknya ke dalam dua cara yang ditempuh pemerintah sekarang, pertama, pemerintah perlu membangun iklim keterbukaan dan demokrasi yang ekspresinya bisa berkembang menjadi aneka bentuk, baik di dalam diskusi-diskusi, unjuk rasa, serta karya tulis lainnya.
Jika dalam konteks beredarnya buku-buku kritis untuk masyarakat justru amat membantu memperkuat fondasi demokrasi paska rezim status quo Soeharto. Dan apabila presiden SBY terus-menerus membalas setiap penulisan di banyak media, dan buku dengan pernyataan di sana-sini dengan mengumbar kata-kata fitnah, lama-kelamaan malah semakin memperkeruh nuansa kebebasan berpendapat. Atau memang inilah bentuk kebebasan berpendapat dari sosok presiden SBY.
Akan tetapi alangkah lebih elegannya pemerintahan SBY, jikalau setiap karya-karya tulis dan buku juga dibalas dengan sanggahan, pendapat dan argumentasi yang sama-sama bisa dipertanggungjawabkan dan diperdebatkan di tengah-tengah rakyat. Agar rakyat tahu, dan menarik kesimpulan untuk menentukan buku-buku mana yang patut dibaca.
Kedua, menghentikan pelarangan buku mencabut seluruh aturan pelarangan yang dikeluarkan Kejaksaan Agung, karena telah melanggar hak azasi menulis, dan berkarya. Kita ketahui sudah ada UU HAM yang mengatur tentang hak ini. Dan justru dalil Kejaksaan Agung yang menyebutkan bahwa pelarangan buku-buku seperti di atas dianggap menggangu ketertiban umum, UUD 1945, dan Pancasila.
Malahan ketiga alasan yang disebut bertabrakan dalam aturannya sendiri. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (bunyi sila ke 5) Pancasila, bisa dianggap bentuk ekspresi secara adil kepada seluruh rakyat untuk menulis dan menerbtikan tulisan-tulisannya ke dalam bentuk buku-buku.
Dalam UUD 1945, kita ketahui juga kalau konstitusi ini ialah yang tertinggi dari seluruh aturan dan UU yang ada.. Maka dalam pasal 28 (UUD 1945 asli) bukan hasil amandemen, jelas melindungi hak kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapatnya.
Kejaksaan Agung dalam hal ini kembali membodoh-bodohi rakyat atas nama UUD 1945 dan Pancasila, padahal Kejaksaan Agung-lah yang tidak menjalankan apa itu semangat dan nilai, serta isi yang terkandung di dalam Pancasila dan UUD 1945.
Lalu apa lagi yang akan dilakukan oleh pemerintahan SBY jika buku sudah dilarang, seringkali memakai alasan aturan-aturan mengada-ada, tanpa memerhatikan bahwa di bawah rezim neoliberalis kesejahteraan rakyat hanya retorika, suara kritis mulai dibungkam?
* Penulis adalah penikmat buku yang dibredel negara, sekaligus Anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Jabodetabek.
** Siapa saja dipersilahkan mengutip, menggandakan, menyebarluaskan sebagian atau seluruh materi yang termuat dalam portal ini selama untuk kajian dan mendukung gerakan rakyat. Untuk keperluan komersial pengguna harus mendapatkan ijin tertulis dari pengelola portal Prakarsa Rakyat. Setiap pengutipan, penggandaan dan penyebarluasan sebagian atau seluruh materi harus mencantumkan sumber (portal Prakarsa Rakyat atau www.prakarsa-rakyat.org).
Labels: bulletin sadar
0 Comments:
d-i-s-c-l-a-i-m-e-r
games tools
- agent waste
- asstroidz
- billyard
- binatang kembar
- blok 2
- bounce
- bullet snale 3
- cavern klamrisk
- chicken invaders roty
- dynomite deluxe
- feeding frenzy 2
- freeciv 2.1.9
- hell chess
- insaniquarium
- luxor
- monopoly
- moto
- pandaland
- picross mania
- pizza frenzy
- sponge bob collapse
- standing point the final stronghold
- the power
- zuma deluxe
temen gue
- adsense for feeds
- anang's blog
- angkatan sembilan belas
- babu ngeblog
- blog oranje
- blogger templates bycaz
- btemplates
- catatan dunia ira
- daleclick templates
- densu-nod
- desakuArt production
- dua mata
- facebook sunnah
- foto tanpa genre
- free blogger template layout
- free musicz mp3
- free templates
- hujan musik indonesia
- imam marsus
- indo bloger
- indo lawas
- indo metal box
- islam substantif
- karim samman
- kidz music community
- klasik rock indonesia
- lumajang music community
- media putra
- mr. ozay's blog
- music 4 sharing
- nona cantiq
- peduli buruh migran
- pers bebas, pintu demokrasi
- rindu pulang
- sanggar alif kaligrafi
- sanggar mata air
- soft 4 u
- template unik
- tunas trans solusindo
- tutorial jitu
- uc1n blog's
- underground indonesia
- unduh musik
- upex rock
- wonogiri voucher
bookmarks gue
- angel fire
- anymaking
- blog lines
- blog template 4u
- blogspot template
- blogspot templetes
- cbm card
- club brillian (id: cgd935029)
- currency converter
- cyber fret
- dhanny dhuzell site's
- dynamic tools drive
- editing foto online
- ez wp themes
- free templates online
- free warebb
- gpro tab
- gudang lagu
- guitar about
- guitar chords/scales
- guitarists
- hot frets
- html-kit-favicon
- indo mp3
- indonesia mp3
- indrakila band
- inilah indie
- isnaini blogger templates
- lumajang music
- mozilla themes
- mozilla themes
- mp3 indonesia
- musician
- musisi
- nolkoma band
- pax
- pp. daarul rahman jakarta
- rubby band
- sekolah rakyat indonesia
- smart telecom
- speed test
- speed test smart
- stafa band
- tab crawler
- tagihan pln jatim
- translator online (babelfish)
- translator online (toggle text)
- universitas terbuka
- warung mp3
- warung musik
- web2 feel
- youtube
kidz music community, desakuArt production, crew forsil songolas, sahabat forsil songolas, sekolah rakyat merdeka, perguruan rakyat merdeka, sekretariat anak merdeka indonesia, sanggar alif kaligrafi, sanggar mata air, exsongolas management, ponpes daarul rahman jakarta, ponpes an-nuqayah sumenep, boom cell cellulare, tunas trans solusindo, semeru scooter club '06 klakah, komunitas indie lumajang, solidaritas buruh migran indonesia - jawa timur, peduli buruh migran, prakarsa rakyat, bulletin sadar, praxis, dll.
(mohon maaf jika ada yang belum disebutkan)
terima kasih atas kunjungan anda, kritik saran yang membangun adalah kunci keberhasilan kami.
deditsabit@smara
thanks for the template design to skinCorner | grunged girl image from dapinoGraphics



