main |
sidebar

supported by deditsabit
supported by deditsabit
Jumlah Posting & Komentar:
buah artikel telah ditulis
buah komentar masuk


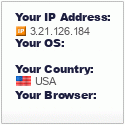



supported by deditsabit
Tidak dapat dipungkiri bahwa gelombang reformasi 11 tahun lalu telah membawa perubahan bagi korban pelanggaran HAM. Mereka dapat leluasa menyatakan diri sebagai korban, menceritakan pengalaman kekerasan yang pernah mereka alami. Secara terbuka mereka juga dapat menyatakan bahwa ada yang keliru dalam penyelenggaraan negara di masa lalu. Bahkan dengan bebas bisa menyatakan diri sebagai mantan anggota organisasi yang selama 32 tahun kekuasaan Orba sangat diharamkan. Jelas semua ini tidaklah mungkin dilakukan sebelum era reformasi 1998.
Perubahan kecil, sedang atau besar, (mungkin) memang sudah terjadi pascareformasi, namun perubahan yang paling mendasar bagi korban sama sekali belumlah terjadi. Negara masih enggan memberikan pengakuan kepada para korban. Pengadilan HAM Ad Hoc yang dirancang sebagai pengadilan luar biasa tak berdaya ketika berhadapan dengan para pelaku. Tengok saja Pengadilan HAM Ad Hoc untuk kasus Timor Timur dan Tanjung Priok. Semua terdakwa dinyatakan tidak bersalah. Baik pada tingkat pertama (Pengadilan Negeri), maupun tingkat Banding dan Kasasi atau Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Institusi peradilan seolah menjadi alat legitimasi atas kejahatan yang mereka (para pelaku) lakukan. Sehingga tidak ada yang salah dengan tindakan atau kebijakan mereka, sekalipun menelan korban.
Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc, sebagai salah satu perwujudan dari amanat reformasi dalam proses penegakan HAM, seakan tidak memiliki makna lagi. Pengadilan HAM Ad Hoc Timtim dan Tanjung Priok sebagai cermin dari prospek penegakan hak asasi manusia di masa yang akan datang, justru tidak menciptakan tonggak baru sejarah hak asasi manusia. Padahal kasus Timtim dan Tanjung Priok adalah dua dari sekian banyak kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di negeri ini. Masih banyak kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu yang belum terselesaikan. Yang berarti masih banyak pula korban yang belum memperoleh hak-haknya.
Seiring dengan penyelesaian kasus masa lalu melalui mekanisme peradilan HAM, muncul wacana pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Sebuah badan yang lazim didirikan pada sebuah negara yang baru keluar dari cengkraman rezim oteriter menuju rezim yang lebih demokratis. Berbagai reaksi muncul terhadap wacana pembentukan KKR, dari yang setuju hingga yang menolak. Tentu dengan alasan dan argumentasi masing-masing. Setelah melalui perdebatan yang cukup panjang, September 2004 RUU KKR akhirnya disahkan menjadi undang-undang.
Namun sayang, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), sebagai ‘jalan tengah’ atau cara damai untuk menyelesaikan kasus-kasus masa lalu, justru ‘mati’ sebelum dilahirkan. Desember 2006, Mahkakamah Konstitusi lewat putusannya menyatakan UU No. 27 Tahun 2004 Tentang KKR sebagai landasan hukum pembentukan KKR tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Fajar harapan korban kembali terbenam. Keadilan seolah semakin menjauh seiring bertambahnya usia reformasi dan usia para korban. Penegakan hak asasi manusia telah kehilangan momentum.
Beberapa waktu lalu, ide untuk mendirikan KKR muncul kembali. Ide ini muncul dari pemerintah melalui Departemen Hukum dan HAM dengan menyusun Rancangan Undang-Undang KKR versi pemerintah. Proses perumusan RUU ini masih dalam tahap diskusi dan konsultasi dengan berbagai pihak. Ini merupakan babak awal dalam proses pembentukan undang-undang. Masih banyak lubang atau kelemahan dalam RUU ini yang perlu mendapat komentar atau masukan, terutama dari korban selaku pemangku kepentingan utama dalam proses pengungkapan kebenaran.
Kita tentu berharap adanya pelibatan publik (terutama korban) secara luas dalam proses perumusan RUU KKR dan pembentukan UU KKR. Lahirnya RUU dari berbagai versi juga diharapkan dalam proses ini, agar tidak ada lubang atau kelemahan yang dapat dijadikan celah untuk (kembali) membatalkan UU KKR. Di tengah pupusnya harapan banyak korban, RUU KKR kembali menerbitkan secercah harapan bagi korban akan lahirnya keadilan dan terciptanya proses pengungkapan kebenaran.
Sebagai negara yang pernah berada dalam cengkraman rezim otoriter, KKR atau apapun namanya, adalah lembaga yang sangat penting dan mendesak bagi Indonesia. Banyaknya kejahatan HAM pada rezim otoriter Orde Baru adalah beban tersendiri bagi pemerintahan selanjutnya. Bangsa Indonesia pun tidak mungkin “menggendong” beban masa lalu yang begitu berat. Lembaga peradilan konvensional yang ada tidaklah mungkin menyelenggarakan peradilan untuk kasus-kasus masa lalu yang memiliki skala kekerasan yang begitu luas, kompleksitas persoalan yang sangat tinggi, melibatkan banyak orang (pelaku dan korban), melibatkan berbagai institusi (sipil dan militer).
Kemendesakkan yang lain adalah (mumpung) masih banyak pelaku, korban dan saksi kejahatan masa lalu yang masih hidup. Pelaku, korban dan saksi adalah pilar utama dalam proses pengungkapan kebenaran. Bayangkan jika KKR dibentuk ketika sebagian besar (atau semua) pelaku, korban dan saksi telah meninggal dunia. Siapa yang akan mengungkap kebenaran masa lalu?
Semoga RUU KKR ini sungguh menjadi fajar harapan baru, bukan fatamorgana keadilan bagi korban. Sehingga peringatan 61 tahun penandatanganan Deklarasi Univrsal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) Perserikatan Bangsa-Bangsa sungguh memiliki arti penting bagi bangsa ini. Sebab hakekat peringatan adalah untuk mengingatkan kembali komitmen awal kita untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia, tidak semata-mata ‘upacara’ HAM.
* Penulis adalah Advokat, bekerja pada Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI), sekaligus anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Jabodetabek.
** Siapa saja dipersilahkan mengutip, menggandakan, menyebarluaskan sebagian atau seluruh materi yang termuat dalam portal ini selama untuk kajian dan mendukung gerakan rakyat. Untuk keperluan komersial pengguna harus mendapatkan ijin tertulis dari pengelola portal Prakarsa Rakyat. Setiap pengutipan, penggandaan dan penyebarluasan sebagian atau seluruh materi harus mencantumkan sumber (portal Prakarsa Rakyat atau www.prakarsa-rakyat.org).
supported by deditsabit
deditsabit bekerjasama dengan dan atas dukungan:
kidz music community, desakuArt production, crew forsil songolas, sahabat forsil songolas, sekolah rakyat merdeka, perguruan rakyat merdeka, sekretariat anak merdeka indonesia, sanggar alif kaligrafi, sanggar mata air, exsongolas management, ponpes daarul rahman jakarta, ponpes an-nuqayah sumenep, boom cell cellulare, tunas trans solusindo, semeru scooter club '06 klakah, komunitas indie lumajang, solidaritas buruh migran indonesia - jawa timur, peduli buruh migran, prakarsa rakyat, bulletin sadar, praxis, dll.
(mohon maaf jika ada yang belum disebutkan)
terima kasih atas kunjungan anda, kritik saran yang membangun adalah kunci keberhasilan kami.
deditsabit@smara

supported by deditsabit
play musik gue
blogroll gue
menurut label
- adsense (1)
- advokasi (2)
- anak (8)
- artikel (11)
- bakat (1)
- bisnis (2)
- budaya (3)
- bulletin sadar (198)
- buruh (1)
- buruh migran (10)
- cdma (1)
- cellulare (4)
- cerita gambar (2)
- deditsabit (4)
- elektronik (2)
- energi (1)
- event (5)
- facebook (4)
- gsm (1)
- ham (1)
- hukum (2)
- informatika (6)
- internet (4)
- jejaring (2)
- kartun (1)
- kdrt (1)
- kesehatan (4)
- kesenian (1)
- keyakinan (8)
- komputer (3)
- konservasi (1)
- korupsi (2)
- lingkungan (2)
- lomba (1)
- lumajang (1)
- maulid hijau (1)
- movie review (19)
- muhammad saw. (1)
- musik (14)
- nuklir (1)
- olah raga (4)
- pendidikan (7)
- perda (1)
- perempuan (9)
- Perguruan Rakyat Merdeka (56)
- peristiwa (7)
- politik (70)
- prestasi (1)
- produk (1)
- qur'an (1)
- radiasi (1)
- religi (9)
- remaja (9)
- resensi buku (27)
- rohani (3)
- sejarah (4)
- serial number (1)
- siswa (1)
- software (1)
- sosial (3)
- ssc '06 klakah (2)
- teknologi (3)
- tv kabel (2)
- undang-undang (1)
- undangan (3)
- video (2)
- website (1)
- wisata (1)
ngikut gak ni...?
statistik blog:
buah artikel telah ditulis
buah komentar masuk

supported by deditsabit
Oleh Rinto Tri Hasworo*
Tidak dapat dipungkiri bahwa gelombang reformasi 11 tahun lalu telah membawa perubahan bagi korban pelanggaran HAM. Mereka dapat leluasa menyatakan diri sebagai korban, menceritakan pengalaman kekerasan yang pernah mereka alami. Secara terbuka mereka juga dapat menyatakan bahwa ada yang keliru dalam penyelenggaraan negara di masa lalu. Bahkan dengan bebas bisa menyatakan diri sebagai mantan anggota organisasi yang selama 32 tahun kekuasaan Orba sangat diharamkan. Jelas semua ini tidaklah mungkin dilakukan sebelum era reformasi 1998.
Perubahan kecil, sedang atau besar, (mungkin) memang sudah terjadi pascareformasi, namun perubahan yang paling mendasar bagi korban sama sekali belumlah terjadi. Negara masih enggan memberikan pengakuan kepada para korban. Pengadilan HAM Ad Hoc yang dirancang sebagai pengadilan luar biasa tak berdaya ketika berhadapan dengan para pelaku. Tengok saja Pengadilan HAM Ad Hoc untuk kasus Timor Timur dan Tanjung Priok. Semua terdakwa dinyatakan tidak bersalah. Baik pada tingkat pertama (Pengadilan Negeri), maupun tingkat Banding dan Kasasi atau Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Institusi peradilan seolah menjadi alat legitimasi atas kejahatan yang mereka (para pelaku) lakukan. Sehingga tidak ada yang salah dengan tindakan atau kebijakan mereka, sekalipun menelan korban.
Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc, sebagai salah satu perwujudan dari amanat reformasi dalam proses penegakan HAM, seakan tidak memiliki makna lagi. Pengadilan HAM Ad Hoc Timtim dan Tanjung Priok sebagai cermin dari prospek penegakan hak asasi manusia di masa yang akan datang, justru tidak menciptakan tonggak baru sejarah hak asasi manusia. Padahal kasus Timtim dan Tanjung Priok adalah dua dari sekian banyak kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di negeri ini. Masih banyak kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu yang belum terselesaikan. Yang berarti masih banyak pula korban yang belum memperoleh hak-haknya.
Seiring dengan penyelesaian kasus masa lalu melalui mekanisme peradilan HAM, muncul wacana pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Sebuah badan yang lazim didirikan pada sebuah negara yang baru keluar dari cengkraman rezim oteriter menuju rezim yang lebih demokratis. Berbagai reaksi muncul terhadap wacana pembentukan KKR, dari yang setuju hingga yang menolak. Tentu dengan alasan dan argumentasi masing-masing. Setelah melalui perdebatan yang cukup panjang, September 2004 RUU KKR akhirnya disahkan menjadi undang-undang.
Namun sayang, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), sebagai ‘jalan tengah’ atau cara damai untuk menyelesaikan kasus-kasus masa lalu, justru ‘mati’ sebelum dilahirkan. Desember 2006, Mahkakamah Konstitusi lewat putusannya menyatakan UU No. 27 Tahun 2004 Tentang KKR sebagai landasan hukum pembentukan KKR tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Fajar harapan korban kembali terbenam. Keadilan seolah semakin menjauh seiring bertambahnya usia reformasi dan usia para korban. Penegakan hak asasi manusia telah kehilangan momentum.
Beberapa waktu lalu, ide untuk mendirikan KKR muncul kembali. Ide ini muncul dari pemerintah melalui Departemen Hukum dan HAM dengan menyusun Rancangan Undang-Undang KKR versi pemerintah. Proses perumusan RUU ini masih dalam tahap diskusi dan konsultasi dengan berbagai pihak. Ini merupakan babak awal dalam proses pembentukan undang-undang. Masih banyak lubang atau kelemahan dalam RUU ini yang perlu mendapat komentar atau masukan, terutama dari korban selaku pemangku kepentingan utama dalam proses pengungkapan kebenaran.
Kita tentu berharap adanya pelibatan publik (terutama korban) secara luas dalam proses perumusan RUU KKR dan pembentukan UU KKR. Lahirnya RUU dari berbagai versi juga diharapkan dalam proses ini, agar tidak ada lubang atau kelemahan yang dapat dijadikan celah untuk (kembali) membatalkan UU KKR. Di tengah pupusnya harapan banyak korban, RUU KKR kembali menerbitkan secercah harapan bagi korban akan lahirnya keadilan dan terciptanya proses pengungkapan kebenaran.
Sebagai negara yang pernah berada dalam cengkraman rezim otoriter, KKR atau apapun namanya, adalah lembaga yang sangat penting dan mendesak bagi Indonesia. Banyaknya kejahatan HAM pada rezim otoriter Orde Baru adalah beban tersendiri bagi pemerintahan selanjutnya. Bangsa Indonesia pun tidak mungkin “menggendong” beban masa lalu yang begitu berat. Lembaga peradilan konvensional yang ada tidaklah mungkin menyelenggarakan peradilan untuk kasus-kasus masa lalu yang memiliki skala kekerasan yang begitu luas, kompleksitas persoalan yang sangat tinggi, melibatkan banyak orang (pelaku dan korban), melibatkan berbagai institusi (sipil dan militer).
Kemendesakkan yang lain adalah (mumpung) masih banyak pelaku, korban dan saksi kejahatan masa lalu yang masih hidup. Pelaku, korban dan saksi adalah pilar utama dalam proses pengungkapan kebenaran. Bayangkan jika KKR dibentuk ketika sebagian besar (atau semua) pelaku, korban dan saksi telah meninggal dunia. Siapa yang akan mengungkap kebenaran masa lalu?
Semoga RUU KKR ini sungguh menjadi fajar harapan baru, bukan fatamorgana keadilan bagi korban. Sehingga peringatan 61 tahun penandatanganan Deklarasi Univrsal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) Perserikatan Bangsa-Bangsa sungguh memiliki arti penting bagi bangsa ini. Sebab hakekat peringatan adalah untuk mengingatkan kembali komitmen awal kita untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia, tidak semata-mata ‘upacara’ HAM.
* Penulis adalah Advokat, bekerja pada Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI), sekaligus anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Jabodetabek.
** Siapa saja dipersilahkan mengutip, menggandakan, menyebarluaskan sebagian atau seluruh materi yang termuat dalam portal ini selama untuk kajian dan mendukung gerakan rakyat. Untuk keperluan komersial pengguna harus mendapatkan ijin tertulis dari pengelola portal Prakarsa Rakyat. Setiap pengutipan, penggandaan dan penyebarluasan sebagian atau seluruh materi harus mencantumkan sumber (portal Prakarsa Rakyat atau www.prakarsa-rakyat.org).
Labels: bulletin sadar
0 Comments:
d-i-s-c-l-a-i-m-e-r
games tools
- agent waste
- asstroidz
- billyard
- binatang kembar
- blok 2
- bounce
- bullet snale 3
- cavern klamrisk
- chicken invaders roty
- dynomite deluxe
- feeding frenzy 2
- freeciv 2.1.9
- hell chess
- insaniquarium
- luxor
- monopoly
- moto
- pandaland
- picross mania
- pizza frenzy
- sponge bob collapse
- standing point the final stronghold
- the power
- zuma deluxe
temen gue
- adsense for feeds
- anang's blog
- angkatan sembilan belas
- babu ngeblog
- blog oranje
- blogger templates bycaz
- btemplates
- catatan dunia ira
- daleclick templates
- densu-nod
- desakuArt production
- dua mata
- facebook sunnah
- foto tanpa genre
- free blogger template layout
- free musicz mp3
- free templates
- hujan musik indonesia
- imam marsus
- indo bloger
- indo lawas
- indo metal box
- islam substantif
- karim samman
- kidz music community
- klasik rock indonesia
- lumajang music community
- media putra
- mr. ozay's blog
- music 4 sharing
- nona cantiq
- peduli buruh migran
- pers bebas, pintu demokrasi
- rindu pulang
- sanggar alif kaligrafi
- sanggar mata air
- soft 4 u
- template unik
- tunas trans solusindo
- tutorial jitu
- uc1n blog's
- underground indonesia
- unduh musik
- upex rock
- wonogiri voucher
bookmarks gue
- angel fire
- anymaking
- blog lines
- blog template 4u
- blogspot template
- blogspot templetes
- cbm card
- club brillian (id: cgd935029)
- currency converter
- cyber fret
- dhanny dhuzell site's
- dynamic tools drive
- editing foto online
- ez wp themes
- free templates online
- free warebb
- gpro tab
- gudang lagu
- guitar about
- guitar chords/scales
- guitarists
- hot frets
- html-kit-favicon
- indo mp3
- indonesia mp3
- indrakila band
- inilah indie
- isnaini blogger templates
- lumajang music
- mozilla themes
- mozilla themes
- mp3 indonesia
- musician
- musisi
- nolkoma band
- pax
- pp. daarul rahman jakarta
- rubby band
- sekolah rakyat indonesia
- smart telecom
- speed test
- speed test smart
- stafa band
- tab crawler
- tagihan pln jatim
- translator online (babelfish)
- translator online (toggle text)
- universitas terbuka
- warung mp3
- warung musik
- web2 feel
- youtube
kidz music community, desakuArt production, crew forsil songolas, sahabat forsil songolas, sekolah rakyat merdeka, perguruan rakyat merdeka, sekretariat anak merdeka indonesia, sanggar alif kaligrafi, sanggar mata air, exsongolas management, ponpes daarul rahman jakarta, ponpes an-nuqayah sumenep, boom cell cellulare, tunas trans solusindo, semeru scooter club '06 klakah, komunitas indie lumajang, solidaritas buruh migran indonesia - jawa timur, peduli buruh migran, prakarsa rakyat, bulletin sadar, praxis, dll.
(mohon maaf jika ada yang belum disebutkan)
terima kasih atas kunjungan anda, kritik saran yang membangun adalah kunci keberhasilan kami.
deditsabit@smara
thanks for the template design to skinCorner | grunged girl image from dapinoGraphics



