main |
sidebar

supported by deditsabit
supported by deditsabit
Jumlah Posting & Komentar:
buah artikel telah ditulis
buah komentar masuk


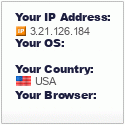



supported by deditsabit
supported by deditsabit
deditsabit bekerjasama dengan dan atas dukungan:
kidz music community, desakuArt production, crew forsil songolas, sahabat forsil songolas, sekolah rakyat merdeka, perguruan rakyat merdeka, sekretariat anak merdeka indonesia, sanggar alif kaligrafi, sanggar mata air, exsongolas management, ponpes daarul rahman jakarta, ponpes an-nuqayah sumenep, boom cell cellulare, tunas trans solusindo, semeru scooter club '06 klakah, komunitas indie lumajang, solidaritas buruh migran indonesia - jawa timur, peduli buruh migran, prakarsa rakyat, bulletin sadar, praxis, dll.
(mohon maaf jika ada yang belum disebutkan)
terima kasih atas kunjungan anda, kritik saran yang membangun adalah kunci keberhasilan kami.
deditsabit@smara

supported by deditsabit
play musik gue
blogroll gue
menurut label
- adsense (1)
- advokasi (2)
- anak (8)
- artikel (11)
- bakat (1)
- bisnis (2)
- budaya (3)
- bulletin sadar (198)
- buruh (1)
- buruh migran (10)
- cdma (1)
- cellulare (4)
- cerita gambar (2)
- deditsabit (4)
- elektronik (2)
- energi (1)
- event (5)
- facebook (4)
- gsm (1)
- ham (1)
- hukum (2)
- informatika (6)
- internet (4)
- jejaring (2)
- kartun (1)
- kdrt (1)
- kesehatan (4)
- kesenian (1)
- keyakinan (8)
- komputer (3)
- konservasi (1)
- korupsi (2)
- lingkungan (2)
- lomba (1)
- lumajang (1)
- maulid hijau (1)
- movie review (19)
- muhammad saw. (1)
- musik (14)
- nuklir (1)
- olah raga (4)
- pendidikan (7)
- perda (1)
- perempuan (9)
- Perguruan Rakyat Merdeka (56)
- peristiwa (7)
- politik (70)
- prestasi (1)
- produk (1)
- qur'an (1)
- radiasi (1)
- religi (9)
- remaja (9)
- resensi buku (27)
- rohani (3)
- sejarah (4)
- serial number (1)
- siswa (1)
- software (1)
- sosial (3)
- ssc '06 klakah (2)
- teknologi (3)
- tv kabel (2)
- undang-undang (1)
- undangan (3)
- video (2)
- website (1)
- wisata (1)
ngikut gak ni...?
statistik blog:
buah artikel telah ditulis
buah komentar masuk

supported by deditsabit
Oleh : Syahrul Sidin *
Konflik agraria dibanyak tempat berimplikasi pada persoalan sosio-yuridis yang berujung pada pelanggaran HAM. Bentrok di Mesuji beberapa waktu lalu yang melahirkan korban lagi-lagi memberikan gambaran terang dampak dari konflik agraria berkepanjangan. Perlahan tapi pasti konflik-konflik agraria menjadi "bom waktu" yang siap meledak setiap saat. Kasus tewasnya Jailani , warga Mesuji menambah panjang potret pelanggaran HAM dalam konflik-konflik agraria.
Mengapa konflik agraria akan menjadi bom waktu? Hal yang harus kita pahami adalah salah satu hal terpenting dalam kehidupan petani adalah akses terhadap tanah sebagai sumber penghidupan. Rakyat khususnya petani membutuhkan tanah-tanah untuk sumber kehidupan dan kelanjutan hidup mereka, sedangkan pihak lain pada umumnya memerlukan tanah-tanah tersebut untuk kegiatan usaha ekonomi dalam skala besar. Monopoli atas tanah inilah yang menjadi bibit lahirnya konflik-konflik agraria.
Di banyak tempat, ekspansi perkebunan- perkebunan besar terutama sawit memerlukan lahan dalam jumlah yang sangat besar dan pengadaannya seringkali “merampas” tanah-tanah rakyat. Data Sawit Watch menunjukan eskalasi konflik agraria di wilayah perkebunan sawit yang terus meningkat setiap tahunnya. Tahun 2010 terjadi sekitar 660 kasus konflik agraria di kawasan perkebunan kelapa sawit, meningkat tajam dari tahun sebelumnya yang hanya berkisar 240 kasus. Pada proses selanjutnya hal yang membuat situasi bertambah rumit dalam konflik agraria yang melibatkan perusahaan ataupun perkebunan swasta dan masyarakat adalah perilaku perusahaan yang seringkali “menyuapi moncong senjata.” Dalam kasus di Mesuji diberitakan polisi terkesan menjadi “centeng perusahaan” meskipun anggapan ini segera disanggah oleh pihak kepolisian.
Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar beberapa waktu lalu dengan lugas menyatakan bahwa “Polisi jangan jadi centeng, Polisi adalah polisi negara, bukan polisi liberal atau kolonial karenanya negaralah yang harus membiayai.” Sebagai abdi negara, aparat keamanan sebenarnya dilarang menerima atau meminta dana tambahan dari siapapun selain dari negara. Penerimaan dana dari pihak ketiga terlebih dalam situasi konflik tentunya akan mengganggu independensi para penegak hukum. Kondisi inilah mendorong dugaan “kolaborasi” aparat keamanan pada pihak tertentu dalam konflik agraria.
Kerja sama yang rapi antara pemburu rente, perumus kebijakan, ditambah penyalahgunaan wewenang oleh aparat keamanan semakin menyulitkan proses penyelesaian konflik agraria. Akibatnya acap kali masyarakat dikejutkan oleh tindakan-tindakan dan kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, dan setiap kali terjadi skandal selalu berupaya keras ditutupi dengan mengunakan istilah “oknum” atau berdalih “it is illegal but not criminal.” Kasus penerimaan dana Freeport dari Polri menunjukkan dengan terang -benderang hal tersebut. Meski Polri berkelit bahwa hal tersebut diatur dalam peraturan tapi secara etik dan hati nuraninya sebagai abdi negara tentunya mereka memahami hal tersebut tentunya tidak layak.
Budaya Hukum Kapitalistik
Fenomena kolaborasi aparat keamanan dan perusahaan-perusahaan besar sesungguhnya adalah implikasi dari penerapan budaya hukum kapitalistik. Budaya hukum kapitalistik yang awalnya muncul di Amerika Serikat telah mendorong cara berhukum yang dicampuradukkan dengan kepentingan bisnis. Marc Galanter menyatakan bahwa pencampuradukan antara bisnis dan hukum tersebut cenderung mementingkan kepentingan orang ”berduit.” Atas nama investasi, itulah nabi-nabinya. Akibatnya muncul slogan “the haves always come out a head.” Akibatnya wajar jika rakyat berpandangan bahwa hukum memang seperti permainan yang sarat dengan kepentingan dan menyusahkan. Semakin kompleksnya persoalan bisnis mengakibatkan beban pemerintah sebagai regulator sekaligus fasilitator semakin meningkat. Terlebih dewasa ini semakin banyak produk perundang-undangan di bidang ekonomi diproduksi atas pesanan para pemilik modal.
Konsekuensi dari intervensi ekonomi dalam pembuatan hukum adalah lahirnya budaya hukum kapitalistik yang berimplikasi pada melemahnya peran negara sebagai pelindung dan pengayom rakyat. Penerapan budaya hukum semacam ini juga membuka peluang berbagai pelanggaran HAM. Konteks ini -budaya hukum kapitalistik- yang sesungguhnya bisa menjelaskan karakter hukum yang tampak congkak dan kejam di mata orang miskin.
Kondisi ini jika dibiarkan terus-menerus tentunya akan melanjutkan berbagai pelanggaran HAM dapat bermuara pada ketidakpercayaan terhadap hukum dan frustrasi sosial. Adagium “Hodie mihi, cras tibi” menjelaskan bahwa ketimpangan atau ketidakadilan yang menyentuh perasaan tetap tersimpan dalam hati nurani rakyat.
Saatnya kita merefleksikan kembali cara berhukum kita, merefleksikan cita-cita negara kita dibentuk dan cita hukum yang sesungguhnya. Institusi-institusi penegak hukum juga perlu berkaca diri dan memiliki keikhlasan untuk mengakui bahwa habitus mereka juga dapat membuat kekeliruan. Ke depan perlu kirannya untuk terus mewujudkan perlindungan yang sama bagi seluruh warga negara dengan mengormati dan melindungi HAM.
* Penulis adalah Sekretaris Jenderal Persatuan Petani Moro-Moro Way Serdang (PPMWS), sekaligus Anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Jabodetabek.
** Siapa saja dipersilahkan mengutip, menggandakan, menyebarluaskan sebagian atau seluruh materi yang termuat dalam portal ini selama untuk kajian dan mendukung gerakan rakyat. Untuk keperluan komersial pengguna harus mendapatkan ijin tertulis dari pengelola portal Prakarsa Rakyat. Setiap pengutipan, penggandaan dan penyebarluasan sebagian atau seluruh materi harus mencantumkan sumber (portal Prakarsa Rakyat atau www.prakarsa-rakyat.org).
Budaya Hukum Kapitalistik
Fenomena kolaborasi aparat keamanan dan perusahaan-perusahaan besar sesungguhnya adalah implikasi dari penerapan budaya hukum kapitalistik. Budaya hukum kapitalistik yang awalnya muncul di Amerika Serikat telah mendorong cara berhukum yang dicampuradukkan dengan kepentingan bisnis. Marc Galanter menyatakan bahwa pencampuradukan antara bisnis dan hukum tersebut cenderung mementingkan kepentingan orang ”berduit.” Atas nama investasi, itulah nabi-nabinya. Akibatnya muncul slogan “the haves always come out a head.” Akibatnya wajar jika rakyat berpandangan bahwa hukum memang seperti permainan yang sarat dengan kepentingan dan menyusahkan. Semakin kompleksnya persoalan bisnis mengakibatkan beban pemerintah sebagai regulator sekaligus fasilitator semakin meningkat. Terlebih dewasa ini semakin banyak produk perundang-undangan di bidang ekonomi diproduksi atas pesanan para pemilik modal.
Konsekuensi dari intervensi ekonomi dalam pembuatan hukum adalah lahirnya budaya hukum kapitalistik yang berimplikasi pada melemahnya peran negara sebagai pelindung dan pengayom rakyat. Penerapan budaya hukum semacam ini juga membuka peluang berbagai pelanggaran HAM. Konteks ini -budaya hukum kapitalistik- yang sesungguhnya bisa menjelaskan karakter hukum yang tampak congkak dan kejam di mata orang miskin.
Kondisi ini jika dibiarkan terus-menerus tentunya akan melanjutkan berbagai pelanggaran HAM dapat bermuara pada ketidakpercayaan terhadap hukum dan frustrasi sosial. Adagium “Hodie mihi, cras tibi” menjelaskan bahwa ketimpangan atau ketidakadilan yang menyentuh perasaan tetap tersimpan dalam hati nurani rakyat.
Saatnya kita merefleksikan kembali cara berhukum kita, merefleksikan cita-cita negara kita dibentuk dan cita hukum yang sesungguhnya. Institusi-institusi penegak hukum juga perlu berkaca diri dan memiliki keikhlasan untuk mengakui bahwa habitus mereka juga dapat membuat kekeliruan. Ke depan perlu kirannya untuk terus mewujudkan perlindungan yang sama bagi seluruh warga negara dengan mengormati dan melindungi HAM.
* Penulis adalah Sekretaris Jenderal Persatuan Petani Moro-Moro Way Serdang (PPMWS), sekaligus Anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Jabodetabek.
** Siapa saja dipersilahkan mengutip, menggandakan, menyebarluaskan sebagian atau seluruh materi yang termuat dalam portal ini selama untuk kajian dan mendukung gerakan rakyat. Untuk keperluan komersial pengguna harus mendapatkan ijin tertulis dari pengelola portal Prakarsa Rakyat. Setiap pengutipan, penggandaan dan penyebarluasan sebagian atau seluruh materi harus mencantumkan sumber (portal Prakarsa Rakyat atau www.prakarsa-rakyat.org).
Sumber: PrakarsaRakyat
Labels: bulletin sadar
0 Comments:
d-i-s-c-l-a-i-m-e-r
games tools
- agent waste
- asstroidz
- billyard
- binatang kembar
- blok 2
- bounce
- bullet snale 3
- cavern klamrisk
- chicken invaders roty
- dynomite deluxe
- feeding frenzy 2
- freeciv 2.1.9
- hell chess
- insaniquarium
- luxor
- monopoly
- moto
- pandaland
- picross mania
- pizza frenzy
- sponge bob collapse
- standing point the final stronghold
- the power
- zuma deluxe
temen gue
- adsense for feeds
- anang's blog
- angkatan sembilan belas
- babu ngeblog
- blog oranje
- blogger templates bycaz
- btemplates
- catatan dunia ira
- daleclick templates
- densu-nod
- desakuArt production
- dua mata
- facebook sunnah
- foto tanpa genre
- free blogger template layout
- free musicz mp3
- free templates
- hujan musik indonesia
- imam marsus
- indo bloger
- indo lawas
- indo metal box
- islam substantif
- karim samman
- kidz music community
- klasik rock indonesia
- lumajang music community
- media putra
- mr. ozay's blog
- music 4 sharing
- nona cantiq
- peduli buruh migran
- pers bebas, pintu demokrasi
- rindu pulang
- sanggar alif kaligrafi
- sanggar mata air
- soft 4 u
- template unik
- tunas trans solusindo
- tutorial jitu
- uc1n blog's
- underground indonesia
- unduh musik
- upex rock
- wonogiri voucher
bookmarks gue
- angel fire
- anymaking
- blog lines
- blog template 4u
- blogspot template
- blogspot templetes
- cbm card
- club brillian (id: cgd935029)
- currency converter
- cyber fret
- dhanny dhuzell site's
- dynamic tools drive
- editing foto online
- ez wp themes
- free templates online
- free warebb
- gpro tab
- gudang lagu
- guitar about
- guitar chords/scales
- guitarists
- hot frets
- html-kit-favicon
- indo mp3
- indonesia mp3
- indrakila band
- inilah indie
- isnaini blogger templates
- lumajang music
- mozilla themes
- mozilla themes
- mp3 indonesia
- musician
- musisi
- nolkoma band
- pax
- pp. daarul rahman jakarta
- rubby band
- sekolah rakyat indonesia
- smart telecom
- speed test
- speed test smart
- stafa band
- tab crawler
- tagihan pln jatim
- translator online (babelfish)
- translator online (toggle text)
- universitas terbuka
- warung mp3
- warung musik
- web2 feel
- youtube
kidz music community, desakuArt production, crew forsil songolas, sahabat forsil songolas, sekolah rakyat merdeka, perguruan rakyat merdeka, sekretariat anak merdeka indonesia, sanggar alif kaligrafi, sanggar mata air, exsongolas management, ponpes daarul rahman jakarta, ponpes an-nuqayah sumenep, boom cell cellulare, tunas trans solusindo, semeru scooter club '06 klakah, komunitas indie lumajang, solidaritas buruh migran indonesia - jawa timur, peduli buruh migran, prakarsa rakyat, bulletin sadar, praxis, dll.
(mohon maaf jika ada yang belum disebutkan)
terima kasih atas kunjungan anda, kritik saran yang membangun adalah kunci keberhasilan kami.
deditsabit@smara
thanks for the template design to skinCorner | grunged girl image from dapinoGraphics



