main |
sidebar

supported by deditsabit
supported by deditsabit
Jumlah Posting & Komentar:
buah artikel telah ditulis
buah komentar masuk


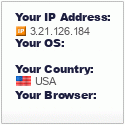



supported by deditsabit
supported by deditsabit
deditsabit bekerjasama dengan dan atas dukungan:
kidz music community, desakuArt production, crew forsil songolas, sahabat forsil songolas, sekolah rakyat merdeka, perguruan rakyat merdeka, sekretariat anak merdeka indonesia, sanggar alif kaligrafi, sanggar mata air, exsongolas management, ponpes daarul rahman jakarta, ponpes an-nuqayah sumenep, boom cell cellulare, tunas trans solusindo, semeru scooter club '06 klakah, komunitas indie lumajang, solidaritas buruh migran indonesia - jawa timur, peduli buruh migran, prakarsa rakyat, bulletin sadar, praxis, dll.
(mohon maaf jika ada yang belum disebutkan)
terima kasih atas kunjungan anda, kritik saran yang membangun adalah kunci keberhasilan kami.
deditsabit@smara

supported by deditsabit
play musik gue
blogroll gue
menurut label
- adsense (1)
- advokasi (2)
- anak (8)
- artikel (11)
- bakat (1)
- bisnis (2)
- budaya (3)
- bulletin sadar (198)
- buruh (1)
- buruh migran (10)
- cdma (1)
- cellulare (4)
- cerita gambar (2)
- deditsabit (4)
- elektronik (2)
- energi (1)
- event (5)
- facebook (4)
- gsm (1)
- ham (1)
- hukum (2)
- informatika (6)
- internet (4)
- jejaring (2)
- kartun (1)
- kdrt (1)
- kesehatan (4)
- kesenian (1)
- keyakinan (8)
- komputer (3)
- konservasi (1)
- korupsi (2)
- lingkungan (2)
- lomba (1)
- lumajang (1)
- maulid hijau (1)
- movie review (19)
- muhammad saw. (1)
- musik (14)
- nuklir (1)
- olah raga (4)
- pendidikan (7)
- perda (1)
- perempuan (9)
- Perguruan Rakyat Merdeka (56)
- peristiwa (7)
- politik (70)
- prestasi (1)
- produk (1)
- qur'an (1)
- radiasi (1)
- religi (9)
- remaja (9)
- resensi buku (27)
- rohani (3)
- sejarah (4)
- serial number (1)
- siswa (1)
- software (1)
- sosial (3)
- ssc '06 klakah (2)
- teknologi (3)
- tv kabel (2)
- undang-undang (1)
- undangan (3)
- video (2)
- website (1)
- wisata (1)
ngikut gak ni...?
statistik blog:
buah artikel telah ditulis
buah komentar masuk

supported by deditsabit
Buletin SADAR Edisi: 396 Tahun VII - 2011, ISSN: 2086-2024, TANTANGAN KAMPANYE GLOBAL ANTI-TEMBAKAU BAGI INDONESIA
Oleh : Okta Pinanjaya*
Mencoba memotret fenomena tembakau dalam rentang kisahnya bersama kebudayaan manusia, kembali dihadapkan kepada retorika konflik yang tak berujung. Paling tidak sejarah mencatat empat abad retorika konflik tembakau sejak zaman Paus Urban VII hingga Bloomberg yang masih terus berlangsung. Saat ini, pertentangan tersebut tidak lagi terjadi pada wilayah domestik, namun telah menggejala pada penetrasi di tingkat global seiring dengan perkembangan tatanan kuasa moralitas dan kepentingan yang tidak lagi memiliki batas-batas identitas teritorial dan kebudayaan. Sebelumnya, siapa yang peduli ketika King James I membuat manifesto anti-tembakau (Counterblast to Tobacco), sementara koloni-koloni Inggris di benua Amerika menikmati perdagangan komoditas tembakau atau ketika Hitler di era kekuasaan Nazi Jerman mengkampanyekan gerakan anti-tembakau yang berujung pada kebijakan pembatasan tembakau, sementara negara-negara besar lainnya, justru mengawali kebangkitan industri tembakau dunia. Di Indonesia sendiri, hampir tidak ditemukan catatan gerakan anti-tembakau sampai kemudian euforia globalisasi menjadi trend yang harus diikuti.
Gerakan anti-tembakau global mencapai puncak momentumnya ketika, World Health Organization (WHO), yang telah bermetamorfosa menjadi ‘rezim kesehatan’ dunia, yang di belakangnya membawa gerbong-gerbong industri farmasi sebagai alat kapitalisasi kesehatan, menginisiasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) sebagai traktat hukum internasional anti-tembakau pada tahun 2003. Dengan mengedepankan rasionalitas isu kesehatan bahwa tembakau adalah suatu gejala epidemik, penyebab utama kematian ataupun meningkatnya penyakit-penyakit berbahaya lainnya (non-communicable disease). Namun dalam perkembangan selanjutnya, tampak secara kasat mata, muncul anomali-anomali yang tidak sejalan dengan ‘ruh’ anti-tembakau itu sendiri. Sehingga perlu kiranya diamati lebih jauh ke belakang pada peristiwa-peristiwa yang terjadi seiring proses berjalannya gerakan anti-tembakau menuju episode globalisasi, untuk memahami dan mendapatkan suatu potret utuh panorama konflik antara 'rezim kesehatan' dan 'rezim tembakau.'
Pada era 1900-an adalah momentum kebangkitan industrialisasi tembakau, khususnya di Amerika dan Eropa yang juga menciptakan hubungan mesra antara industri kesehatan dan industri tembakau. Pada era 30-an, terlihat iklan-iklan produk rokok juga meramaikan jurnal-jurnal ilmiah medis dan kesehatan. Bahkan, slogan-slogan iklan rokok pun tak lepas dari ilustrasi kesehatan, seperti yang dilakukan Lollilard Tobacco di America: "Ask your dentist why Old Golds are better for the teeth." Menuju era Perang Dunia II (PD II) pun, ketika sebaliknya, Jerman oleh kekuasaan Nazi yang pada masa itu juga menjadi pemimpin di pengembangan iptek dan industri kesehatan memberlakukan kebijakan anti-tembakau yang dilandasi oleh rasionalitas ‘ilmiah’ isu kesehatan, tidak juga mempengaruhi atau bahkan menyurutkan gerak laju pertumbuhan industri tembakau di Eropa dan Amerika. Apalagi di Indonesia, yang juga mencapai pada momentum kebangkitan industri kreteknya pada era 30-an. Sedangkan Cina pada tahun 1947, mulai melakukan nasionalisasi industri tembakau ke bawah monopoli negara, sehingga British American Tobacco (BAT) yang saat itu ikut menikmati pasar Cina harus kehilangan potensi bisnisnya.
Sementara pasca-PD II, ketika industri tembakau sedang berada di atas angin, industri farmasi dan kesehatan dunia mencapai tahap konsolidasi besar-besaran yang sebelumnya dominasi iptek dan industri kesehatan serta farmasi dipegang oleh Jerman. Pasca kejatuhan rezim Nazi Jerman, raksasa-raksasa farmasi jerman seperti IG Farben (Bayer), harus ditutup dengan tuduhan kejahatan perang kepada aktor-aktor di dalamnya, yang berujung pada potensi asetnya yang berpindah tangan dalam kekuasaan industri kapitalis Amerika Serikat dan Inggris yang membentuk sebuah sindikasi farmasi internasional yang dikenal dengan ‘The Drug Trusts.’ Apabila ditelusuri lebih jauh, aktor-aktor kekuatan modal yang berada di belakangnya, juga yang menjadi kekuatan modal industri tembakau pasca-Sherman Anti-Trust Act pada tahun 1911 di Amerika Serikat.
Pada era 1960-an, industri tembakau menjadi primadona investasi di pasar modal. Bahkan universitas, rumah sakit, lembaga riset sebagai pondasi dari 'rezim kesehatan' ikut menanamkan uangnya di industri tembakau. Tidak cukup sampai di situ, industri tembakau juga ikut mendukung perkembangan industri kesehatan lewat dana-dana hibah yang digelontorkan kepada lembaga-lembaga riset dan universitas, baik terkait riset tembakau maupun riset-riset lainnya. Pada 7 Februari 1964, American Medical Association (AMA) juga ikut menikmati gelontoran dana dari industri tembakau senilai US$ 10 juta.
Pada era yang sama, Industri farmasi dan kesehatan juga mulai memantapkan pondasi hegemoni ‘rezim kesehatan’ modern sebagai ruh kekuasaan dan pertumbuhan industrinya. Pada 2 November 1963, AMA menginisiasi sebuah kampanye bertajuk ‘The War Against Quackery’ (perang melawan praktek perdukunan/pengobatan alternatif) lewat pembentukan komite perdukunan dalam wadah Coordinating Conference on Health Information (CCHI), yang terdiri dari: American Cancer Society, American Pharmaceutical Association, Arthritis Foundation, Council of Better Business Bureaus, National Health Council, Food and Drug Administration (FDA), Federal Trade Comission (FTC), U.S. Postal Service, Office of Consumer Affairs, U.S., State Attorney Generals’ Office dan Internal Revenue Service.’ Kampanye yang kemudian merubah wajah ‘otoritas kesehatan’ menjadi ‘rezim kesehatan’ yang menempatkan ‘metode pengobatan dan kesehatan modern’ sebagai satu-satunya kebenaran sedangkan ‘metode pengobatan dan kesehatan alami’ adalah bentuk praktek perdukunan yang menyesatkan. Kampanye ini kemudian menyebar ke seluruh dunia dan membentuk sistem pasar yang absolut terhadap ketergantungan masyarakat terhadap sistem layanan medis dan kesehatan modern lewat otoritas profesi dokter sebagai agen pemasaran bagi produk-produk industri farmasi dan kesehatan.
Pada era 80-an, industri tembakau Amerika Serikat mencapai puncaknya dengan pergeseran penguasaan pangsa pasar yang signifikan. Philip Morris yang sebelumnya berada pada urutan di bawah, melaju dengan pesat menyusul para kompetitornya menjadi pemimpin pasar. Lewat kombinasi strategi pemasaran yang progresif dan strategi konsolidasi lewat merger dan akuisisi, Philip Morris bergerak menguasai pangsa pasar Amerika Serikat sebesar 34% pada tahun 1987 meninggalkan RJ Reynolds yang sebelumnya menduduki urutan pertama. Kemudian Philip Morris bergerak mendominasi pasar rokok Amerika Serikat dengan penguasaan pangsa pasar mencapai 43%, berada pada puncak pimpinan diikuti oleh RJ Reynolds sebesar 28% pada tahun 1995. Pada tahap ini, industri tembakau Amerika Serikat pun mengalami stagnasi. Kemudian gerak ekspansi pun beralih pada konsolidasi skala global, untuk tetap mendorong pertumbuhan.
Pada era yang sama, industri farmasi dan kesehatan juga bisa dikatakan mulai mengalami stagnasi. Pertumbuhan industri Farmasi tidak saja diindikasikan pada peningkatan produksi dan penjualan ataupun penguasaan pangsa pasar. Indikator pertumbuhan lain yang bisa digunakan adalah perkembangan teknologi dari riset-riset pengembangan yang menjadi dasar dari strategi diversifikasi produk yang mendorong peningkatan nilai aset ataupun kredibilitas suatu perusahaan farmasi. Sementara momok utama yang dihadapi dunia kesehatan modern dengan munculnya kasus HIV dan kanker yang terus meningkat tidak diikuti dengan perkembangan teknologi farmasi yang signifikan untuk menjawab tantangan tersebut. Sejak lebih dari 100 tahun lalu, ketika Dr. James Ewing mengembangkan teknik radiasi (kemoterapi) di Memorial Hospital, hingga saat ini, perkembangan teknik pengobatan kanker pun tidak mengalami perubahan yang signifikan, tidak pernah jauh dari metode cut, slash and burn. Perkembangan yang terjadi hanya pada prosedur pengobatan yang menyesuaikan kasus-kasus kanker dan komplikasinya yang muncul. Apalagi HIV, yang hingga saat ini, industri farmasi masih terjebak dalam perlombaan untuk menemukan obatnya.
Persamaan momentum tersebut, menjadi suatu faktor kebetulan yang menguntungkan apabila coba dilihat dari kacamata kapitalistik. Frustasi akibat stagnasi pertumbuhan yang dihadapi oleh industri tembakau dan farmasi, memunculkan gejala ‘emerging interest.’ Industri tembakau membutuhkan momentum untuk memperkuat gerakan ekspansi global, sedangkan, Industri farmasi membutuhkan momentum untuk berlindung dari kegagalannya sebagai rezim kesehatan yang ibarat kuasa seorang dewa, mampu menjawab doa manusia yang sedang diselimuti teror kematian. Perang terhadap kanker, yang pernah diinisiasi oleh Amerika di bawah pemerintahan Nixon pada tahun 1970, yang awalnya bergerak ofensif lewat misi penciptaan senjata pamungkas (obat kanker), kemudian berubah dalam gerak defensif. Kebijakan preventif kemudian dikedepankan dengan mencari kambing hitam untuk dijadikan musuh bersama untuk menggerakkan peran publik sebagai militan-militan ‘rezim kesehatan.’
Pada era 90-an, gerakan anti-tembakau mencapai momentumnya untuk memperluas ruang gerak pada tingkat global. Bersama dengan sponsorship yang diberikan oleh industri farmasi pada WHO, skema hukum internasional yang menempatkan tembakau sebagai ‘musuh utama’ bagi kesehatan di dunia yang akhirnya menghasilkan FCTC. Seiring dengan era perdagangan bebas yang menjadi komitmen Washington Consensus pada tahun 1989. World Trade Organization (WTO) dan WHO pun saling mengakomodasi kepentingan masing-masing industri. Sehingga agenda anti-tembakau global tidak boleh mengganggu kepentingan kapitalisme global lewat perdagangan bebas yang menjadi kendaraan industri tembakau global.
Industri tembakau memasang ancang-ancang ekspansi global untuk menghidupkan kembali pertumbuhan industrinya. Konsolidasi besar-besaran pun terjadi, agenda merger dan akuisisi pun marak terjadi di antara kekuatan-kekuatan modal di industri tembakau untuk memperkuat eksistensi pasar tradisionalnya di Amerika dan Eropa sekaligus membangun kapasitas yang lebih besar untuk memperkuat ekspansi globalnya. Di antara Industri kesehatan dan industri tembakau, diawali dengan proyek divestasi tembakau yang dimotori oleh universitas-universitas dan rumah sakit, yang sebelumnya menginvestasikan dananya di industri tembakau, yang melegitimasi nilai-nilai etika kapitalisme atas pertentangan nilai antara kedua industri ini.
Agenda berlanjut dengan proses litigasi yang menggugat industri tembakau sebagai penyebab meningkatnya biaya kesehatan publik yang menjadi beban negara. Lewat ‘pengakuan’ salah satu pemain di industri tembakau Amerika Serikat, Liggett Group Inc. yang menyatakan secara tertulis di pengadilan bahwa produk rokok bersifat adiktif dan penyebab kanker, memperkuat gugatan yang akhirnya menghasilkan Master Settlement Agreement (MSA) 1998. Kesepakatan antara industri tembakau dan pemerintahan federal Amerika Serikat tersebut layaknya bentuk delegitimasi industri tembakau untuk ikut berperan dalam dinamika ‘ilmiah’ tembakau atas dasar konflik kepentingan dan ikut berpartisipasi dalam agenda anti-tembakau mencegah konsumsi tembakau bagi remaja. Kemudian ‘mengamankan’ penerimaan anggaran nasional pemerintah federal Amerika Serikat dari industri tembakau, lewat kewajiban bagi industri untuk menyetorkan kompensasi senilai US$ 206 miliar selama 25 tahun. Selain itu juga menciptakan sebuah bentuk sistem proteksi bagi industri tembakau lewat pembentukan sistem subsidi bagi pertanian tembakau di Amerika Serikat lewat National Tobacco Growers' Settlement Trust Fund senilai US$ 5,15 miliar.
Setelah melewati berbagai bentuk konsolidasi (merger dan akuisisi) yang menghasilkan tiga besar Transnational Tobacco Company (TTC) dalam industri tembakau global (Philip Morris, British American Tobacco, Japan Tobacco) pada 1 Desember 1999, melakukan pertemuan di Jenewa, Swiss untuk menginisiasi Project Cerberus, yang kemudian menghasilkan International Tobacco Product Marketing Standard (ITPMS), yang di dalamnya memuat ketentuan-ketentuan yang sejalan dengan kepentingan gerakan anti-tembakau, yang pada masa itu, hampir mendekati puncak kelahiran FCTC. Manuver ketiga TTC tersebut yang sejalan dengan gerakan anti-tembakau tentu menjadi sesuatu yang tidak biasa. Namun apabila dicermati lebih dalam lagi justru merupakan langkah yang sangat strategis untuk ikut mendorong euforia gerakan anti-tembakau global. Pada akhirnya, euforia tersebut akan membentuk paradigma inferioritas bagi industri-industri tembakau domestik lewat tekanan isu dan kebijakan nasional di negara-negara anggota WHO yang mau tidak mau harus tunduk terhadap 'rezim kesehatan' dunia tersebut. Paradigma tersebut yang kemudian membukakan pintu peluang masuknya ekspansi TTC tersebut ke pasar domestik suatu negara. Manuver cerdas bagi strategi ‘hostile take over’ yang terselubung halus.
Kemudian, di tengah gencarnya kampanye global anti-tembakau oleh ‘rezim kesehatan’ yang juga diikuti oleh ‘rezim tembakau’, industri farmasi mulai masuk ke dalam era baru perlombaan riset dan pengembangan teknologi. Selain itu, besarnya angka konsumen tembakau (rokok) dunia di tengah-tengah euforia anti-tembakau, menciptakan ‘emerging market’ bagi strategi diversifikasi produknya dengan menghadirkan Nicotine Replacement Therapy (NRT) untuk memenuhi permintaan ‘berhenti’ merokok. Kemudian tembakau juga menjadi salah satu sumber daya industri farmasi untuk pengembangan riset dan teknologinya. Dewasa ini, kita kenal dengan istilah Tobacco Pharming, sebuah konsep budi-daya tembakau lewat pendekatan Genetic Modification, untuk kepentingan bahan baku produksi farmasi. Seiring dengan itu, tembakau lewat pendekatan teknologi bio-molekular mulai dikembangkan sebagai agen produksi senyawa-senyawa hasil modifikasi genetik yang berpotensi untuk penyembuhan berbagai macam penyakit yang menjadi momok kesahatan modern, sebut saja: HIV, tubercolosis, alzheimer dan kanker. Tidak berhenti sampai di situ, korporasi-korporasi tembakau juga ikut dalam perlombaan ini, lewat pendirian divisi-divisi riset khusus tembakau dan juga konsolidasi merger serta akuisisi terhadap perusahaan-perusahaan farmasi yang bukan saja memanfaatkan tembakau sebagai produk farmasi, namun dengan pendekatan teknologi yang sama, mempertahankan tradisi rokok yang bebas isu kesehatan.
Fakta-fakta di atas akhirnya perlu dilihat sebagai ancaman sekaligus potensi, dengan kesadaran bahwa tembakau tidak semata-mata ditempatkan sebagai musuh kesehatan manusia, tetapi juga ditempatkan sebagai dewa penyelamat yang menunggu saatnya tiba membawa ‘titah utopia’ peradaban manusia. Indonesia sebagai bagian dari 10 besar produsen tembakau dunia dan 3 besar konsumen tembakau dunia, perlu meletakkan persoalan industri tembakaunya, khususnya industri kretek nasional kedalam kerangka yang utuh. Tidak hanya terbawa arus tren anti-tembakau global, dan kemudian menyerahkan industri tembakaunya untuk dikuasai kapitalis-kapitalis asing. Posisi industri tembakau Indonesia di peta global, memiliki potensi yang besar untuk ikut menjadi pemain utama dunia, bukan sekedar potensi pasar dan aset produksi dari kekuatan modal asing. Sehingga apakah perlu Indonesia meniru langkah-langkah yang telah dilakukan Cina untuk membawa tembakau ke dalam kontrol dan proteksi negara, mungkin dalam bentuknya yang lain, untuk menjawab tren ancaman dan potensi tembakau di masa yang akan datang demi kepentingan rakyat Indonesia?
* Penulis adalah anggota Komunitas Kretek Jakarta, sekaligus Anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Jabodetabek.
** Siapa saja dipersilahkan mengutip, menggandakan, menyebarluaskan sebagian atau seluruh materi yang termuat dalam portal ini selama untuk kajian dan mendukung gerakan rakyat. Untuk keperluan komersial pengguna harus mendapatkan ijin tertulis dari pengelola portal Prakarsa Rakyat. Setiap pengutipan, penggandaan dan penyebarluasan sebagian atau seluruh materi harus mencantumkan sumber (portal Prakarsa Rakyat atau www.prakarsa-rakyat.org).
Pada era 1960-an, industri tembakau menjadi primadona investasi di pasar modal. Bahkan universitas, rumah sakit, lembaga riset sebagai pondasi dari 'rezim kesehatan' ikut menanamkan uangnya di industri tembakau. Tidak cukup sampai di situ, industri tembakau juga ikut mendukung perkembangan industri kesehatan lewat dana-dana hibah yang digelontorkan kepada lembaga-lembaga riset dan universitas, baik terkait riset tembakau maupun riset-riset lainnya. Pada 7 Februari 1964, American Medical Association (AMA) juga ikut menikmati gelontoran dana dari industri tembakau senilai US$ 10 juta.
Pada era yang sama, Industri farmasi dan kesehatan juga mulai memantapkan pondasi hegemoni ‘rezim kesehatan’ modern sebagai ruh kekuasaan dan pertumbuhan industrinya. Pada 2 November 1963, AMA menginisiasi sebuah kampanye bertajuk ‘The War Against Quackery’ (perang melawan praktek perdukunan/pengobatan alternatif) lewat pembentukan komite perdukunan dalam wadah Coordinating Conference on Health Information (CCHI), yang terdiri dari: American Cancer Society, American Pharmaceutical Association, Arthritis Foundation, Council of Better Business Bureaus, National Health Council, Food and Drug Administration (FDA), Federal Trade Comission (FTC), U.S. Postal Service, Office of Consumer Affairs, U.S., State Attorney Generals’ Office dan Internal Revenue Service.’ Kampanye yang kemudian merubah wajah ‘otoritas kesehatan’ menjadi ‘rezim kesehatan’ yang menempatkan ‘metode pengobatan dan kesehatan modern’ sebagai satu-satunya kebenaran sedangkan ‘metode pengobatan dan kesehatan alami’ adalah bentuk praktek perdukunan yang menyesatkan. Kampanye ini kemudian menyebar ke seluruh dunia dan membentuk sistem pasar yang absolut terhadap ketergantungan masyarakat terhadap sistem layanan medis dan kesehatan modern lewat otoritas profesi dokter sebagai agen pemasaran bagi produk-produk industri farmasi dan kesehatan.
Pada era 80-an, industri tembakau Amerika Serikat mencapai puncaknya dengan pergeseran penguasaan pangsa pasar yang signifikan. Philip Morris yang sebelumnya berada pada urutan di bawah, melaju dengan pesat menyusul para kompetitornya menjadi pemimpin pasar. Lewat kombinasi strategi pemasaran yang progresif dan strategi konsolidasi lewat merger dan akuisisi, Philip Morris bergerak menguasai pangsa pasar Amerika Serikat sebesar 34% pada tahun 1987 meninggalkan RJ Reynolds yang sebelumnya menduduki urutan pertama. Kemudian Philip Morris bergerak mendominasi pasar rokok Amerika Serikat dengan penguasaan pangsa pasar mencapai 43%, berada pada puncak pimpinan diikuti oleh RJ Reynolds sebesar 28% pada tahun 1995. Pada tahap ini, industri tembakau Amerika Serikat pun mengalami stagnasi. Kemudian gerak ekspansi pun beralih pada konsolidasi skala global, untuk tetap mendorong pertumbuhan.
Pada era yang sama, industri farmasi dan kesehatan juga bisa dikatakan mulai mengalami stagnasi. Pertumbuhan industri Farmasi tidak saja diindikasikan pada peningkatan produksi dan penjualan ataupun penguasaan pangsa pasar. Indikator pertumbuhan lain yang bisa digunakan adalah perkembangan teknologi dari riset-riset pengembangan yang menjadi dasar dari strategi diversifikasi produk yang mendorong peningkatan nilai aset ataupun kredibilitas suatu perusahaan farmasi. Sementara momok utama yang dihadapi dunia kesehatan modern dengan munculnya kasus HIV dan kanker yang terus meningkat tidak diikuti dengan perkembangan teknologi farmasi yang signifikan untuk menjawab tantangan tersebut. Sejak lebih dari 100 tahun lalu, ketika Dr. James Ewing mengembangkan teknik radiasi (kemoterapi) di Memorial Hospital, hingga saat ini, perkembangan teknik pengobatan kanker pun tidak mengalami perubahan yang signifikan, tidak pernah jauh dari metode cut, slash and burn. Perkembangan yang terjadi hanya pada prosedur pengobatan yang menyesuaikan kasus-kasus kanker dan komplikasinya yang muncul. Apalagi HIV, yang hingga saat ini, industri farmasi masih terjebak dalam perlombaan untuk menemukan obatnya.
Persamaan momentum tersebut, menjadi suatu faktor kebetulan yang menguntungkan apabila coba dilihat dari kacamata kapitalistik. Frustasi akibat stagnasi pertumbuhan yang dihadapi oleh industri tembakau dan farmasi, memunculkan gejala ‘emerging interest.’ Industri tembakau membutuhkan momentum untuk memperkuat gerakan ekspansi global, sedangkan, Industri farmasi membutuhkan momentum untuk berlindung dari kegagalannya sebagai rezim kesehatan yang ibarat kuasa seorang dewa, mampu menjawab doa manusia yang sedang diselimuti teror kematian. Perang terhadap kanker, yang pernah diinisiasi oleh Amerika di bawah pemerintahan Nixon pada tahun 1970, yang awalnya bergerak ofensif lewat misi penciptaan senjata pamungkas (obat kanker), kemudian berubah dalam gerak defensif. Kebijakan preventif kemudian dikedepankan dengan mencari kambing hitam untuk dijadikan musuh bersama untuk menggerakkan peran publik sebagai militan-militan ‘rezim kesehatan.’
Pada era 90-an, gerakan anti-tembakau mencapai momentumnya untuk memperluas ruang gerak pada tingkat global. Bersama dengan sponsorship yang diberikan oleh industri farmasi pada WHO, skema hukum internasional yang menempatkan tembakau sebagai ‘musuh utama’ bagi kesehatan di dunia yang akhirnya menghasilkan FCTC. Seiring dengan era perdagangan bebas yang menjadi komitmen Washington Consensus pada tahun 1989. World Trade Organization (WTO) dan WHO pun saling mengakomodasi kepentingan masing-masing industri. Sehingga agenda anti-tembakau global tidak boleh mengganggu kepentingan kapitalisme global lewat perdagangan bebas yang menjadi kendaraan industri tembakau global.
Industri tembakau memasang ancang-ancang ekspansi global untuk menghidupkan kembali pertumbuhan industrinya. Konsolidasi besar-besaran pun terjadi, agenda merger dan akuisisi pun marak terjadi di antara kekuatan-kekuatan modal di industri tembakau untuk memperkuat eksistensi pasar tradisionalnya di Amerika dan Eropa sekaligus membangun kapasitas yang lebih besar untuk memperkuat ekspansi globalnya. Di antara Industri kesehatan dan industri tembakau, diawali dengan proyek divestasi tembakau yang dimotori oleh universitas-universitas dan rumah sakit, yang sebelumnya menginvestasikan dananya di industri tembakau, yang melegitimasi nilai-nilai etika kapitalisme atas pertentangan nilai antara kedua industri ini.
Agenda berlanjut dengan proses litigasi yang menggugat industri tembakau sebagai penyebab meningkatnya biaya kesehatan publik yang menjadi beban negara. Lewat ‘pengakuan’ salah satu pemain di industri tembakau Amerika Serikat, Liggett Group Inc. yang menyatakan secara tertulis di pengadilan bahwa produk rokok bersifat adiktif dan penyebab kanker, memperkuat gugatan yang akhirnya menghasilkan Master Settlement Agreement (MSA) 1998. Kesepakatan antara industri tembakau dan pemerintahan federal Amerika Serikat tersebut layaknya bentuk delegitimasi industri tembakau untuk ikut berperan dalam dinamika ‘ilmiah’ tembakau atas dasar konflik kepentingan dan ikut berpartisipasi dalam agenda anti-tembakau mencegah konsumsi tembakau bagi remaja. Kemudian ‘mengamankan’ penerimaan anggaran nasional pemerintah federal Amerika Serikat dari industri tembakau, lewat kewajiban bagi industri untuk menyetorkan kompensasi senilai US$ 206 miliar selama 25 tahun. Selain itu juga menciptakan sebuah bentuk sistem proteksi bagi industri tembakau lewat pembentukan sistem subsidi bagi pertanian tembakau di Amerika Serikat lewat National Tobacco Growers' Settlement Trust Fund senilai US$ 5,15 miliar.
Setelah melewati berbagai bentuk konsolidasi (merger dan akuisisi) yang menghasilkan tiga besar Transnational Tobacco Company (TTC) dalam industri tembakau global (Philip Morris, British American Tobacco, Japan Tobacco) pada 1 Desember 1999, melakukan pertemuan di Jenewa, Swiss untuk menginisiasi Project Cerberus, yang kemudian menghasilkan International Tobacco Product Marketing Standard (ITPMS), yang di dalamnya memuat ketentuan-ketentuan yang sejalan dengan kepentingan gerakan anti-tembakau, yang pada masa itu, hampir mendekati puncak kelahiran FCTC. Manuver ketiga TTC tersebut yang sejalan dengan gerakan anti-tembakau tentu menjadi sesuatu yang tidak biasa. Namun apabila dicermati lebih dalam lagi justru merupakan langkah yang sangat strategis untuk ikut mendorong euforia gerakan anti-tembakau global. Pada akhirnya, euforia tersebut akan membentuk paradigma inferioritas bagi industri-industri tembakau domestik lewat tekanan isu dan kebijakan nasional di negara-negara anggota WHO yang mau tidak mau harus tunduk terhadap 'rezim kesehatan' dunia tersebut. Paradigma tersebut yang kemudian membukakan pintu peluang masuknya ekspansi TTC tersebut ke pasar domestik suatu negara. Manuver cerdas bagi strategi ‘hostile take over’ yang terselubung halus.
Kemudian, di tengah gencarnya kampanye global anti-tembakau oleh ‘rezim kesehatan’ yang juga diikuti oleh ‘rezim tembakau’, industri farmasi mulai masuk ke dalam era baru perlombaan riset dan pengembangan teknologi. Selain itu, besarnya angka konsumen tembakau (rokok) dunia di tengah-tengah euforia anti-tembakau, menciptakan ‘emerging market’ bagi strategi diversifikasi produknya dengan menghadirkan Nicotine Replacement Therapy (NRT) untuk memenuhi permintaan ‘berhenti’ merokok. Kemudian tembakau juga menjadi salah satu sumber daya industri farmasi untuk pengembangan riset dan teknologinya. Dewasa ini, kita kenal dengan istilah Tobacco Pharming, sebuah konsep budi-daya tembakau lewat pendekatan Genetic Modification, untuk kepentingan bahan baku produksi farmasi. Seiring dengan itu, tembakau lewat pendekatan teknologi bio-molekular mulai dikembangkan sebagai agen produksi senyawa-senyawa hasil modifikasi genetik yang berpotensi untuk penyembuhan berbagai macam penyakit yang menjadi momok kesahatan modern, sebut saja: HIV, tubercolosis, alzheimer dan kanker. Tidak berhenti sampai di situ, korporasi-korporasi tembakau juga ikut dalam perlombaan ini, lewat pendirian divisi-divisi riset khusus tembakau dan juga konsolidasi merger serta akuisisi terhadap perusahaan-perusahaan farmasi yang bukan saja memanfaatkan tembakau sebagai produk farmasi, namun dengan pendekatan teknologi yang sama, mempertahankan tradisi rokok yang bebas isu kesehatan.
Fakta-fakta di atas akhirnya perlu dilihat sebagai ancaman sekaligus potensi, dengan kesadaran bahwa tembakau tidak semata-mata ditempatkan sebagai musuh kesehatan manusia, tetapi juga ditempatkan sebagai dewa penyelamat yang menunggu saatnya tiba membawa ‘titah utopia’ peradaban manusia. Indonesia sebagai bagian dari 10 besar produsen tembakau dunia dan 3 besar konsumen tembakau dunia, perlu meletakkan persoalan industri tembakaunya, khususnya industri kretek nasional kedalam kerangka yang utuh. Tidak hanya terbawa arus tren anti-tembakau global, dan kemudian menyerahkan industri tembakaunya untuk dikuasai kapitalis-kapitalis asing. Posisi industri tembakau Indonesia di peta global, memiliki potensi yang besar untuk ikut menjadi pemain utama dunia, bukan sekedar potensi pasar dan aset produksi dari kekuatan modal asing. Sehingga apakah perlu Indonesia meniru langkah-langkah yang telah dilakukan Cina untuk membawa tembakau ke dalam kontrol dan proteksi negara, mungkin dalam bentuknya yang lain, untuk menjawab tren ancaman dan potensi tembakau di masa yang akan datang demi kepentingan rakyat Indonesia?
* Penulis adalah anggota Komunitas Kretek Jakarta, sekaligus Anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Jabodetabek.
** Siapa saja dipersilahkan mengutip, menggandakan, menyebarluaskan sebagian atau seluruh materi yang termuat dalam portal ini selama untuk kajian dan mendukung gerakan rakyat. Untuk keperluan komersial pengguna harus mendapatkan ijin tertulis dari pengelola portal Prakarsa Rakyat. Setiap pengutipan, penggandaan dan penyebarluasan sebagian atau seluruh materi harus mencantumkan sumber (portal Prakarsa Rakyat atau www.prakarsa-rakyat.org).
Sumber: PrakarsaRakyat
Labels: bulletin sadar
0 Comments:
d-i-s-c-l-a-i-m-e-r
games tools
- agent waste
- asstroidz
- billyard
- binatang kembar
- blok 2
- bounce
- bullet snale 3
- cavern klamrisk
- chicken invaders roty
- dynomite deluxe
- feeding frenzy 2
- freeciv 2.1.9
- hell chess
- insaniquarium
- luxor
- monopoly
- moto
- pandaland
- picross mania
- pizza frenzy
- sponge bob collapse
- standing point the final stronghold
- the power
- zuma deluxe
temen gue
- adsense for feeds
- anang's blog
- angkatan sembilan belas
- babu ngeblog
- blog oranje
- blogger templates bycaz
- btemplates
- catatan dunia ira
- daleclick templates
- densu-nod
- desakuArt production
- dua mata
- facebook sunnah
- foto tanpa genre
- free blogger template layout
- free musicz mp3
- free templates
- hujan musik indonesia
- imam marsus
- indo bloger
- indo lawas
- indo metal box
- islam substantif
- karim samman
- kidz music community
- klasik rock indonesia
- lumajang music community
- media putra
- mr. ozay's blog
- music 4 sharing
- nona cantiq
- peduli buruh migran
- pers bebas, pintu demokrasi
- rindu pulang
- sanggar alif kaligrafi
- sanggar mata air
- soft 4 u
- template unik
- tunas trans solusindo
- tutorial jitu
- uc1n blog's
- underground indonesia
- unduh musik
- upex rock
- wonogiri voucher
bookmarks gue
- angel fire
- anymaking
- blog lines
- blog template 4u
- blogspot template
- blogspot templetes
- cbm card
- club brillian (id: cgd935029)
- currency converter
- cyber fret
- dhanny dhuzell site's
- dynamic tools drive
- editing foto online
- ez wp themes
- free templates online
- free warebb
- gpro tab
- gudang lagu
- guitar about
- guitar chords/scales
- guitarists
- hot frets
- html-kit-favicon
- indo mp3
- indonesia mp3
- indrakila band
- inilah indie
- isnaini blogger templates
- lumajang music
- mozilla themes
- mozilla themes
- mp3 indonesia
- musician
- musisi
- nolkoma band
- pax
- pp. daarul rahman jakarta
- rubby band
- sekolah rakyat indonesia
- smart telecom
- speed test
- speed test smart
- stafa band
- tab crawler
- tagihan pln jatim
- translator online (babelfish)
- translator online (toggle text)
- universitas terbuka
- warung mp3
- warung musik
- web2 feel
- youtube
kidz music community, desakuArt production, crew forsil songolas, sahabat forsil songolas, sekolah rakyat merdeka, perguruan rakyat merdeka, sekretariat anak merdeka indonesia, sanggar alif kaligrafi, sanggar mata air, exsongolas management, ponpes daarul rahman jakarta, ponpes an-nuqayah sumenep, boom cell cellulare, tunas trans solusindo, semeru scooter club '06 klakah, komunitas indie lumajang, solidaritas buruh migran indonesia - jawa timur, peduli buruh migran, prakarsa rakyat, bulletin sadar, praxis, dll.
(mohon maaf jika ada yang belum disebutkan)
terima kasih atas kunjungan anda, kritik saran yang membangun adalah kunci keberhasilan kami.
deditsabit@smara
thanks for the template design to skinCorner | grunged girl image from dapinoGraphics



