main |
sidebar

supported by deditsabit
supported by deditsabit
Jumlah Posting & Komentar:
buah artikel telah ditulis
buah komentar masuk


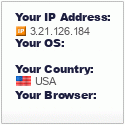



supported by deditsabit
supported by deditsabit
deditsabit bekerjasama dengan dan atas dukungan:
kidz music community, desakuArt production, crew forsil songolas, sahabat forsil songolas, sekolah rakyat merdeka, perguruan rakyat merdeka, sekretariat anak merdeka indonesia, sanggar alif kaligrafi, sanggar mata air, exsongolas management, ponpes daarul rahman jakarta, ponpes an-nuqayah sumenep, boom cell cellulare, tunas trans solusindo, semeru scooter club '06 klakah, komunitas indie lumajang, solidaritas buruh migran indonesia - jawa timur, peduli buruh migran, prakarsa rakyat, bulletin sadar, praxis, dll.
(mohon maaf jika ada yang belum disebutkan)
terima kasih atas kunjungan anda, kritik saran yang membangun adalah kunci keberhasilan kami.
deditsabit@smara

supported by deditsabit
play musik gue
blogroll gue
menurut label
- adsense (1)
- advokasi (2)
- anak (8)
- artikel (11)
- bakat (1)
- bisnis (2)
- budaya (3)
- bulletin sadar (198)
- buruh (1)
- buruh migran (10)
- cdma (1)
- cellulare (4)
- cerita gambar (2)
- deditsabit (4)
- elektronik (2)
- energi (1)
- event (5)
- facebook (4)
- gsm (1)
- ham (1)
- hukum (2)
- informatika (6)
- internet (4)
- jejaring (2)
- kartun (1)
- kdrt (1)
- kesehatan (4)
- kesenian (1)
- keyakinan (8)
- komputer (3)
- konservasi (1)
- korupsi (2)
- lingkungan (2)
- lomba (1)
- lumajang (1)
- maulid hijau (1)
- movie review (19)
- muhammad saw. (1)
- musik (14)
- nuklir (1)
- olah raga (4)
- pendidikan (7)
- perda (1)
- perempuan (9)
- Perguruan Rakyat Merdeka (56)
- peristiwa (7)
- politik (70)
- prestasi (1)
- produk (1)
- qur'an (1)
- radiasi (1)
- religi (9)
- remaja (9)
- resensi buku (27)
- rohani (3)
- sejarah (4)
- serial number (1)
- siswa (1)
- software (1)
- sosial (3)
- ssc '06 klakah (2)
- teknologi (3)
- tv kabel (2)
- undang-undang (1)
- undangan (3)
- video (2)
- website (1)
- wisata (1)
ngikut gak ni...?
statistik blog:
buah artikel telah ditulis
buah komentar masuk

supported by deditsabit
Buletin SADAR Edisi: 394 Tahun VII - 2011, ISSN: 2086-2024, PLURALISME SETENGAH HATI DALAM BERNEGARA
Oleh : Yenie Oktri*
Sejak Negara Indonesia tegak berdiri, pluralisme selalu menempati ruang abu-abu. Pluralisme tidak pernah menjadi sebuah konsensus politik bersama tapi hanya sekedar kosmetik politik saja. Perbedaan suku, agama dan ras yang merupakan keniscayaan sebagai sebuah negara terpaksa harus meringkuk dalam ruang kompromi dan tidak pernah membuka diri dalam ruang toleransi.
Sejarah menunjukkan bagaimana kosmetik politik justru mewarnai tindakan para pendiri bangsa ketika harus mengkompromikan antara Pancasila dalam naskah UUD 1945 dengan Piagam Jakarta terutama menyangkut penghilangan kata dalam sila pertama. Selama ini banyak pihak beranggapan bahwa penghilangan kata itu merupakan bagian dari toleransi. Padahal penghilangan kata tersebut adalah kompromi politik yang mempunyai konsekuensi logis hanya bersifat sementara.
Dari sinilah, disadari atau tidak, bibit pluralisme setengah hati mulai tertanam di setiap golongan dan lapisan masyarakat. Pluralisme setengah hati yang merupakan sikap hanya mau mengakui adanya perbedaan/kemajemukan tapi tidak bisa menerimanya terutama menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara. Semakin lama pluralisme setengah hati mendapatkan wadahnya berupa anarkisme dan kekerasan.
Konflik berbau suku, agama dan ras hampir mewarnai disetiap rejim pemerintahan di negeri ini tanpa kecuali. Mulai dari Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati sampai Susilo Bambang Yudhyono terlihat bahwa anak negeri ini telah menguras habis energinya hanya untuk melampiaskan bibit pluralisme setengah hati yang diwariskan turun-temurun.
Bila pada era Soekarno konflik berbau ras, agama dan sara sedikit bisa diminimalisir dalam beragam ideologi partai-partai politik yang tumbuh bak cendawan di musim hujan. Menyikapi perbedaan/kemajukan diselesaikan dengan gerakan politik yang mengedepankan dialog. Tapi kondisi itu berbeda total pada era Soeharto di mana setiap konflik berbau suku, agama dan ras akan berhadapan dengan militer. Habibie yang menjadi penerus Soeharto pun ternyata menganut paham pluralisme setengah hati.
Di era Habibie inilah pluralisme setengah hati mulai merasuki lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif. Hal itu dimungkinkan karena adanya pergantian ataupun rotasi besar-besaran di berbagai lembaga maupun organisasi sebagai efek domino dari eforia reformasi. Akibatnya bisa ditebak berbagai peraturan perundang-undangan tidak lagi mengedepankan kepentingan rakyat yang memang plural tapi lebih mewakili kepentingan satu golongan saja. Dari sinilah konflik berbau suku, agama dan ras di berbagai daerah mulai mengarah kepada konflik bersenjata.
Di era Gus Dur dan Megawati, konflik bersenjata berlatar belakang suku, agama dan ras meledak di berbagai daerah. Penyelesaian yang berlarut-larut menyebabkan banyak anak bangsa yang mati terbunuh secara sia-sia. Tidak hanya itu saja, kekerasan bersenjata yang dilakukan berbagai kelompok masyarakat mulai menemukan bentuk lain untuk mengekspresikan pluralisme setengah hati melalu teror. Teror yang mengatasnamakan agama menjadi sebuah fenomena tragis dalam sejarah peradaban masyarakat.
Pada saat Susilo Bambang Yudhyono naik menjadi presiden dan berkuasa sampai sekarang, konflik berbau suku, agama dan ras bahkan mulai merasuki kota-kota besar yang notabene sebenarnya banyak golongan terpelajar. Bentuknya pun semakin variatif. Bisa pemberlakuan peraturan daerah yang berbasiskan satu agama tertentu dan aksi massa yang terus-menerus melakukan tindakan anarkis terstruktur tapi tidak mampu dihentikan oleh aparatus negara.
Undang-Undang Pendidikan Nasional yang seharusnya menjadi acuan peningkatan kualitas kecerdasan dalam dunia pendidikan ternyata lebih mengutamakan persoalan akhlak dan moral. Sebelum disahkan menjadi undang-undang, mulai dari pembahasannya sudah diwarnai dengan beragam kontroversi. Ujung-ujungnya mengerahkan massa sebanyak-banyaknya untuk menekan satu sama lain. Lahirnya UU Pendidikan Nasional hanya merupakan bentuk lain dari pluralisme setengah hati itu.
Negara dalam kondisi seperti ini ternyata dibuat tak berdaya. Himbauan normatif yang dilontarkan aparat lembaga negara lenyap dalam lengkingan amarah para penganut pluralisme setengah hati. Apalagi himbauan normatif itu tidak didukung oleh penegakan dan sanksi hukum yang tegas sehingga para pelaku kekerasan yang mengatasnamakan suku, agama atau pun ras seperti api mendapat siraman bensin. Membara dan menghancurkan siapa saja yang menghadangnya.
Diperlukan kerja keras serta sikap toleransi yang tinggi dari berbagai golongan dan lapisan masyarakat untuk mengikis pluralisme setengah hati yang sudah menjadi penyakit kronis. Langkah awal dan paling sederhana yang bisa dilakukan adalah dengan saling mengucapkan selamat hari raya kepada siapa saja dan dari latar belakang agama apa saja. Sebab banyak tokoh-tokoh masyarakat yang seharusnya menjadi panutan toleransi ternyata tidak mau menyampaikan selamat hari raya kepada agama lain.
* Penulis adalah jamaah pengajian mingguan Darul Ummah di Tangerang, sekaligus Anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Jabodetabek.
** Siapa saja dipersilahkan mengutip, menggandakan, menyebarluaskan sebagian atau seluruh materi yang termuat dalam portal ini selama untuk kajian dan mendukung gerakan rakyat. Untuk keperluan komersial pengguna harus mendapatkan ijin tertulis dari pengelola portal Prakarsa Rakyat. Setiap pengutipan, penggandaan dan penyebarluasan sebagian atau seluruh materi harus mencantumkan sumber (portal Prakarsa Rakyat atau www.prakarsa-rakyat.org).
Pada saat Susilo Bambang Yudhyono naik menjadi presiden dan berkuasa sampai sekarang, konflik berbau suku, agama dan ras bahkan mulai merasuki kota-kota besar yang notabene sebenarnya banyak golongan terpelajar. Bentuknya pun semakin variatif. Bisa pemberlakuan peraturan daerah yang berbasiskan satu agama tertentu dan aksi massa yang terus-menerus melakukan tindakan anarkis terstruktur tapi tidak mampu dihentikan oleh aparatus negara.
Undang-Undang Pendidikan Nasional yang seharusnya menjadi acuan peningkatan kualitas kecerdasan dalam dunia pendidikan ternyata lebih mengutamakan persoalan akhlak dan moral. Sebelum disahkan menjadi undang-undang, mulai dari pembahasannya sudah diwarnai dengan beragam kontroversi. Ujung-ujungnya mengerahkan massa sebanyak-banyaknya untuk menekan satu sama lain. Lahirnya UU Pendidikan Nasional hanya merupakan bentuk lain dari pluralisme setengah hati itu.
Negara dalam kondisi seperti ini ternyata dibuat tak berdaya. Himbauan normatif yang dilontarkan aparat lembaga negara lenyap dalam lengkingan amarah para penganut pluralisme setengah hati. Apalagi himbauan normatif itu tidak didukung oleh penegakan dan sanksi hukum yang tegas sehingga para pelaku kekerasan yang mengatasnamakan suku, agama atau pun ras seperti api mendapat siraman bensin. Membara dan menghancurkan siapa saja yang menghadangnya.
Diperlukan kerja keras serta sikap toleransi yang tinggi dari berbagai golongan dan lapisan masyarakat untuk mengikis pluralisme setengah hati yang sudah menjadi penyakit kronis. Langkah awal dan paling sederhana yang bisa dilakukan adalah dengan saling mengucapkan selamat hari raya kepada siapa saja dan dari latar belakang agama apa saja. Sebab banyak tokoh-tokoh masyarakat yang seharusnya menjadi panutan toleransi ternyata tidak mau menyampaikan selamat hari raya kepada agama lain.
* Penulis adalah jamaah pengajian mingguan Darul Ummah di Tangerang, sekaligus Anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Jabodetabek.
** Siapa saja dipersilahkan mengutip, menggandakan, menyebarluaskan sebagian atau seluruh materi yang termuat dalam portal ini selama untuk kajian dan mendukung gerakan rakyat. Untuk keperluan komersial pengguna harus mendapatkan ijin tertulis dari pengelola portal Prakarsa Rakyat. Setiap pengutipan, penggandaan dan penyebarluasan sebagian atau seluruh materi harus mencantumkan sumber (portal Prakarsa Rakyat atau www.prakarsa-rakyat.org).
Sumber: PrakarsaRakyat
Labels: bulletin sadar
0 Comments:
d-i-s-c-l-a-i-m-e-r
games tools
- agent waste
- asstroidz
- billyard
- binatang kembar
- blok 2
- bounce
- bullet snale 3
- cavern klamrisk
- chicken invaders roty
- dynomite deluxe
- feeding frenzy 2
- freeciv 2.1.9
- hell chess
- insaniquarium
- luxor
- monopoly
- moto
- pandaland
- picross mania
- pizza frenzy
- sponge bob collapse
- standing point the final stronghold
- the power
- zuma deluxe
temen gue
- adsense for feeds
- anang's blog
- angkatan sembilan belas
- babu ngeblog
- blog oranje
- blogger templates bycaz
- btemplates
- catatan dunia ira
- daleclick templates
- densu-nod
- desakuArt production
- dua mata
- facebook sunnah
- foto tanpa genre
- free blogger template layout
- free musicz mp3
- free templates
- hujan musik indonesia
- imam marsus
- indo bloger
- indo lawas
- indo metal box
- islam substantif
- karim samman
- kidz music community
- klasik rock indonesia
- lumajang music community
- media putra
- mr. ozay's blog
- music 4 sharing
- nona cantiq
- peduli buruh migran
- pers bebas, pintu demokrasi
- rindu pulang
- sanggar alif kaligrafi
- sanggar mata air
- soft 4 u
- template unik
- tunas trans solusindo
- tutorial jitu
- uc1n blog's
- underground indonesia
- unduh musik
- upex rock
- wonogiri voucher
bookmarks gue
- angel fire
- anymaking
- blog lines
- blog template 4u
- blogspot template
- blogspot templetes
- cbm card
- club brillian (id: cgd935029)
- currency converter
- cyber fret
- dhanny dhuzell site's
- dynamic tools drive
- editing foto online
- ez wp themes
- free templates online
- free warebb
- gpro tab
- gudang lagu
- guitar about
- guitar chords/scales
- guitarists
- hot frets
- html-kit-favicon
- indo mp3
- indonesia mp3
- indrakila band
- inilah indie
- isnaini blogger templates
- lumajang music
- mozilla themes
- mozilla themes
- mp3 indonesia
- musician
- musisi
- nolkoma band
- pax
- pp. daarul rahman jakarta
- rubby band
- sekolah rakyat indonesia
- smart telecom
- speed test
- speed test smart
- stafa band
- tab crawler
- tagihan pln jatim
- translator online (babelfish)
- translator online (toggle text)
- universitas terbuka
- warung mp3
- warung musik
- web2 feel
- youtube
kidz music community, desakuArt production, crew forsil songolas, sahabat forsil songolas, sekolah rakyat merdeka, perguruan rakyat merdeka, sekretariat anak merdeka indonesia, sanggar alif kaligrafi, sanggar mata air, exsongolas management, ponpes daarul rahman jakarta, ponpes an-nuqayah sumenep, boom cell cellulare, tunas trans solusindo, semeru scooter club '06 klakah, komunitas indie lumajang, solidaritas buruh migran indonesia - jawa timur, peduli buruh migran, prakarsa rakyat, bulletin sadar, praxis, dll.
(mohon maaf jika ada yang belum disebutkan)
terima kasih atas kunjungan anda, kritik saran yang membangun adalah kunci keberhasilan kami.
deditsabit@smara
thanks for the template design to skinCorner | grunged girl image from dapinoGraphics



