main |
sidebar

supported by deditsabit
supported by deditsabit
Jumlah Posting & Komentar:
buah artikel telah ditulis
buah komentar masuk


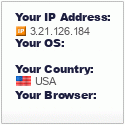



supported by deditsabit
Pertarungan memperebutkan kursi nomor satu untuk periode 2009-2014 di negeri yang bernama indonesia baru saja dimulai. Dipastikan tiga calon akan bertarung untuk memperebutkan kurang lebih 170 juta suara yang tersebar di seluruh Nusantara. Adalah pasangan JK-Wiranto, SBY-Boediono dan Mega-Prabowo berlomba demi sebuah pasangan kursi. Kursi yang akan membawa mereka untuk menahkodai sekitar 240 juta rakyat yang bernaung di bawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Janji-janji manis ditebarkan dengan romantisme ibarat orang pacaran. Senjata beserta pelurunya telah mulai diluncurkan. Perang isu tak terelakkan lagi. Meskipun masih berkutat dengan isu-isu konservatif yang tidak menyentuh persoalan mendasar yang dialami oleh rakyat semisal isu Sipil-Militer, Jawa -Luar Jawa, primordialisme suku, agama dan isu-isu basi lainnya. Namun isu ini mampu menyihir dan mengilusi rakyat. Bayangkan saja, beberapa hari yang lalu, ribuan rakyat Sulsel, tak terkecuali bagi mereka yang termasuk rakyat pekerja ikut mendeklarasikan diri untuk mendukung salah satu pasangan calon, hanya karena termakan isu “Sikampotta, Saribattang, Sibola” (jika diartikan kira-kira artinya sekampung, sahabat, dan serumah).
Pada pemilihan presiden kali ini, kemunafikan kaum borjuis memang terlihat jelas. Dengan membawa isu ekonomi kerakyatan, mereka bermaksud memperlihatkan dan mencoba meyakinkan kepada rakyat bahwa keberpihakan mereka ada pada wong cilik seperti buruh, tani, nelayan dan kaum miskin kota. Padahal entah sadar atau tidak sadar sampai kapanpun, kaum borjuis tidak mungkin akan meletakkan keperbihakannya pada kelas rakyat pekerja.
Belum lagi pelemparan isu anti neoliberal. Inilah isu yang paling lucu dan menggelikan. Salah satu pasangan calon diserang oleh pasangan calon lainnya dengan isu anti neoliberal. Dengan berlindung dari isu itu, pasangan calon lain itu ingin memperlihatkan bahwasannya dialah figur yang sangat menentang kebijakan neoliberal dan juga seakan-akan menyatakan keberpihakannya kepada rakyat.
Memang harus diakui pasangan SBY-Boediono adalah pasangan yang berani secara gamblang menyatakan aliansi asingnya kepada Amerika Serikat. Lihat saja upacara pendeklarasian pasangan calon ini dilakukan mirip dengan apa yang dilakukan oleh Barrack Obama sewaktu mendeklarasikan diri untuk maju sebagai calon presiden Amerika Serikat. Selain itu, beberapa hari yang lalu Boediono juga mengeluarkan pernyataan yang menghimbau kepada rakyat Indonesia agar tidak alergi terhadap utang. Namun terlepas dari kejujuran SBY-Boediono, yang namanya borjuis tetap saja borjuis dan tidak akan pernah memihak kepada kepentingan rakyat.
Sementara pasangan JK-Wiranto dan Mega-Prabowo notabene berlatar belakang pengusaha dan militer. JK yang merupakan bagian dari salah satu kekuatan kapitalisme di Asia Tenggara. Megawati yang kenyang dengan perusahaan distibusi BBM (SPBU) dan kebijakannya yang memprivatisasi beberapa BUMN di masa pemerintahannya di tahun 2001-2004 dan mempersilahkan Shell Helix untuk masuk ke Indonesia adalah bukti nyata bahwa ia adalah kapitalis tulen. Prabowo pengusaha distribusi minyak yang berkongsi dengan pengusaha Timur Tengah. Prabowo juga orang militer yang harus bertanggung jawab terhadap penculikan aktivis di tahun 1998-1999. Dan Wiranto yang meskipun tidak terlalu kentara watak kapitalisnya, namun ia adalah penganut paham militerisme yang juga harus bertangung jawab terhadap tragedi 1998-1999.
Sekal lagi, apapun namanya, bagaimanapun ketiga pasangan calon ini menyembunyikan identitas dirinya, selihai apapun mereka mengilusi rakyat, yang pasti watak kapitalis akan melekat padanya. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa kapitalisme hari ini telah memasuki fase neoliberalisme, sehingga kapitalisme varian apapun, senang tidak senang, mau tidak mau, harus mengikut dan membonceng di belakang neoliberalisme.
Watak Neoliberal pada Proses Pemilu
Sebelumnya kita telah memahami bahwa ketiga pasangan calon ini adalah antek-antek neoliberal di Indonesia. Kita telah melihat pada seluruh kasus, kaum neoliberal tidak mengkampanyekan program politiknya. Mereka tidak menjanjikan upah yang lebih rendah, menghancurkan negara kesejahteraan, mengurangi pensiun, meningkatkan harga bahan-bahan makanan dan pelayanan sosial yang mendasar. Sebaliknya, kaum neoliberal mengidentikkan dirinya sebagai populis, mengecam pejabat-pejabat neoliberal dan menjanjikan perubahan yang mendasar. Dalam pertarungan untuk menempati jabatan kepresidenan, slogan populis dan nasionalis sangat mendominasi. Para kandidat berjanji untuk menyelesaiakn masalah-masalah kemiskinan dan pengangguran. Para penganjur utama doktrin pasar bebas dikecamnya habis-habisan sehingga di mata rakyat mereka tampak sebagai musuh bersama yang mesti dienyahkan dari panggung kekuasaan politik. Tetapi, sekali kursi kepresidenan sudah didudukinya, komitmen penganut pembaharuan adalah menjadi budak kepada penyesuaian gaya IMF, World Bank dan program stabilisasi yang sama kerasnya dengan rejim neoliberal sebelumnya yang telah dihujatnya habis-habisan. Rejm baru ini menghancurkan seluruh sistem kesejahteraan sosial, menghapuskan undang-undang perlindungan pekerja, menarik ke bahwa spiral upah, meningkatkan pengangguran dan pertumbuhan sektor ekonomi informal, sehingga menyebabkan kemiskinan rakyat yang semakin meluas.
Program kampanye pemilu berhubungan terbalik dengan politik paska pemilu. Neoliberalisme telah menghina proses pemilu dengan memarjinalkan badan pembuat undang-undang, pada periode paska pemilu. Di bawah neoliberalisme, politik pemilu menjadi tidak berarti sebagai metode yang menyediakan aneka pilihan yang penuh arti kepada pemilih, dimana harapan pemberi suara berkorelasi dengan hasil pemilu. Hasilnya menyangsikan keseluruhan isu dari pemerintah pilihan rakyat. Pemilu yang tidak representatif adalah hasil fundamental dari karakter elitis neoliberalisme, dimana kebijakan sosial ekonomi bertentangan dengan pemilu yang bebas.
Di bawah pemerintahan militer, tindakan-tindakan neoliberal diumumkan secara terbuka dan dipaksakan. Di bawah pemerintahan sipil, kebijakan neoliberal diterapkan secara terselubung dan dipaksakan melalui mandat pemilu palsu. Legitimasi palsu (pseudo legitimacy) dari rejim neoliberal menyandarkan dirinya pada asumsi palsu bahwa pemerintah “dipilih secara bebas.” Tetapi politikus hasil pemilu hanya merupakan wakil sebuah posisi yang dipertahankan di depan umum. Dari konteks politik, proses pemilu kekurangan legitimasi sebagaimana pada contoh lainnya disebut politik kotor.
Secara umum, kampanye pemilu neoliberal adalah manipulatif untuk mengamankan perolehan suara yang secara diametral bertentangan dengan dukungan mayoritas pemilih. Oposisi itu tak hanya dalam bentuk luruhnya kepercayaan tapi, terutama pada gagasan tentang pemerintahan perwakilan. James Petras mengungkapkan bahwa siklus neoliberal, reproduksi rejim neoliberal, juga menjadi basis bagi para politisi tangguh untuk mendistorsi (menyimpangkan) proses pemilu melalui manipulasi kesadaran, kian mendalamnya jurang antara pilihan (preferensi) pemilih dengan praktek dari kelas politik dan antara proses pemilu dan kebijakan yang dihasilkannya.
Masih ingatkah kita dengan SKB 4 Menteri, masih ingatkah kita dengan privatisasi beberapa BUMN yang menguasai hajat hidup oang banyak dan pengesahan UU BHP? Masih ingatkah kita denan praktek-praktek antara lain munculnya PHK massal akibat kebijakan-kebijakan neoliberal yang mencabut subsidi, menaikkan harga BBM dan TDL? Ditambah lagi dengan pelegalan sistem buruh kontrak, outsourcing dan kebijakan perburuhan lainnya yang pro modal asing dan mengebiri hak kaum pekerja.
Juga pengingkaran terhadap penuntasan kasus pelanggaran HAM. Hadirnya kembali wajah-wajah lama dalam bursa pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia membuat penuntasan berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu kian sulit. Apalagi rekam jejak mereka terkait dengan isu pelanggaran HAM jauh dari baik apalagi memuaskan.
Selama belum ada blok politik yang menjadi rival sejati bagi blok politik borjuis, maka niscaya yang ada hanyalah ilusi semata. Perubahan yang terjadi bukanlah perubahan yang substansial, melainkan perubahan yang formalistis belaka. Borjuis tetap berjaya sementara kaum rakyat pekerja semakin terpuruk dalam keproletariannya.
Pemilu presiden memang tinggal menghitung hari. Sekali lagi tokoh-tokoh yang bertarung adalah tokoh-tokoh yang secara ideologi dan kelas berpihak pada kepentingan kapitalis. Sudah saatnya rakyat sebagai stake owner bangkit melawan. Kelas-kelas revolusioner harus mulai mengkonsolidasikan diri dan membentuk blok politik alternatif. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menyatakan sikap dengan memilih untuk tidak memilih pada pemilu presiden 2009.
* Penulis adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, sekaligus anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Sulawesi Selatan.
** Siapa saja dipersilahkan mengutip, menggandakan, menyebarluaskan sebagian atau seluruh materi yang termuat dalam portal ini selama untuk kajian dan mendukung gerakan rakyat. Untuk keperluan komersial pengguna harus mendapatkan ijin tertulis dari pengelola portal Prakarsa Rakyat. Setiap pengutipan, penggandaan dan penyebarluasan sebagian atau seluruh materi harus mencantumkan sumber (portal Prakarsa Rakyat atau www.prakarsa-rakyat.org).
supported by deditsabit
deditsabit bekerjasama dengan dan atas dukungan:
kidz music community, desakuArt production, crew forsil songolas, sahabat forsil songolas, sekolah rakyat merdeka, perguruan rakyat merdeka, sekretariat anak merdeka indonesia, sanggar alif kaligrafi, sanggar mata air, exsongolas management, ponpes daarul rahman jakarta, ponpes an-nuqayah sumenep, boom cell cellulare, tunas trans solusindo, semeru scooter club '06 klakah, komunitas indie lumajang, solidaritas buruh migran indonesia - jawa timur, peduli buruh migran, prakarsa rakyat, bulletin sadar, praxis, dll.
(mohon maaf jika ada yang belum disebutkan)
terima kasih atas kunjungan anda, kritik saran yang membangun adalah kunci keberhasilan kami.
deditsabit@smara

supported by deditsabit
play musik gue
blogroll gue
menurut label
- adsense (1)
- advokasi (2)
- anak (8)
- artikel (11)
- bakat (1)
- bisnis (2)
- budaya (3)
- bulletin sadar (198)
- buruh (1)
- buruh migran (10)
- cdma (1)
- cellulare (4)
- cerita gambar (2)
- deditsabit (4)
- elektronik (2)
- energi (1)
- event (5)
- facebook (4)
- gsm (1)
- ham (1)
- hukum (2)
- informatika (6)
- internet (4)
- jejaring (2)
- kartun (1)
- kdrt (1)
- kesehatan (4)
- kesenian (1)
- keyakinan (8)
- komputer (3)
- konservasi (1)
- korupsi (2)
- lingkungan (2)
- lomba (1)
- lumajang (1)
- maulid hijau (1)
- movie review (19)
- muhammad saw. (1)
- musik (14)
- nuklir (1)
- olah raga (4)
- pendidikan (7)
- perda (1)
- perempuan (9)
- Perguruan Rakyat Merdeka (56)
- peristiwa (7)
- politik (70)
- prestasi (1)
- produk (1)
- qur'an (1)
- radiasi (1)
- religi (9)
- remaja (9)
- resensi buku (27)
- rohani (3)
- sejarah (4)
- serial number (1)
- siswa (1)
- software (1)
- sosial (3)
- ssc '06 klakah (2)
- teknologi (3)
- tv kabel (2)
- undang-undang (1)
- undangan (3)
- video (2)
- website (1)
- wisata (1)
ngikut gak ni...?
statistik blog:
buah artikel telah ditulis
buah komentar masuk

supported by deditsabit
Oleh Achmad R. Hamzah*
Pertarungan memperebutkan kursi nomor satu untuk periode 2009-2014 di negeri yang bernama indonesia baru saja dimulai. Dipastikan tiga calon akan bertarung untuk memperebutkan kurang lebih 170 juta suara yang tersebar di seluruh Nusantara. Adalah pasangan JK-Wiranto, SBY-Boediono dan Mega-Prabowo berlomba demi sebuah pasangan kursi. Kursi yang akan membawa mereka untuk menahkodai sekitar 240 juta rakyat yang bernaung di bawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Janji-janji manis ditebarkan dengan romantisme ibarat orang pacaran. Senjata beserta pelurunya telah mulai diluncurkan. Perang isu tak terelakkan lagi. Meskipun masih berkutat dengan isu-isu konservatif yang tidak menyentuh persoalan mendasar yang dialami oleh rakyat semisal isu Sipil-Militer, Jawa -Luar Jawa, primordialisme suku, agama dan isu-isu basi lainnya. Namun isu ini mampu menyihir dan mengilusi rakyat. Bayangkan saja, beberapa hari yang lalu, ribuan rakyat Sulsel, tak terkecuali bagi mereka yang termasuk rakyat pekerja ikut mendeklarasikan diri untuk mendukung salah satu pasangan calon, hanya karena termakan isu “Sikampotta, Saribattang, Sibola” (jika diartikan kira-kira artinya sekampung, sahabat, dan serumah).
Pada pemilihan presiden kali ini, kemunafikan kaum borjuis memang terlihat jelas. Dengan membawa isu ekonomi kerakyatan, mereka bermaksud memperlihatkan dan mencoba meyakinkan kepada rakyat bahwa keberpihakan mereka ada pada wong cilik seperti buruh, tani, nelayan dan kaum miskin kota. Padahal entah sadar atau tidak sadar sampai kapanpun, kaum borjuis tidak mungkin akan meletakkan keperbihakannya pada kelas rakyat pekerja.
Belum lagi pelemparan isu anti neoliberal. Inilah isu yang paling lucu dan menggelikan. Salah satu pasangan calon diserang oleh pasangan calon lainnya dengan isu anti neoliberal. Dengan berlindung dari isu itu, pasangan calon lain itu ingin memperlihatkan bahwasannya dialah figur yang sangat menentang kebijakan neoliberal dan juga seakan-akan menyatakan keberpihakannya kepada rakyat.
Memang harus diakui pasangan SBY-Boediono adalah pasangan yang berani secara gamblang menyatakan aliansi asingnya kepada Amerika Serikat. Lihat saja upacara pendeklarasian pasangan calon ini dilakukan mirip dengan apa yang dilakukan oleh Barrack Obama sewaktu mendeklarasikan diri untuk maju sebagai calon presiden Amerika Serikat. Selain itu, beberapa hari yang lalu Boediono juga mengeluarkan pernyataan yang menghimbau kepada rakyat Indonesia agar tidak alergi terhadap utang. Namun terlepas dari kejujuran SBY-Boediono, yang namanya borjuis tetap saja borjuis dan tidak akan pernah memihak kepada kepentingan rakyat.
Sementara pasangan JK-Wiranto dan Mega-Prabowo notabene berlatar belakang pengusaha dan militer. JK yang merupakan bagian dari salah satu kekuatan kapitalisme di Asia Tenggara. Megawati yang kenyang dengan perusahaan distibusi BBM (SPBU) dan kebijakannya yang memprivatisasi beberapa BUMN di masa pemerintahannya di tahun 2001-2004 dan mempersilahkan Shell Helix untuk masuk ke Indonesia adalah bukti nyata bahwa ia adalah kapitalis tulen. Prabowo pengusaha distribusi minyak yang berkongsi dengan pengusaha Timur Tengah. Prabowo juga orang militer yang harus bertanggung jawab terhadap penculikan aktivis di tahun 1998-1999. Dan Wiranto yang meskipun tidak terlalu kentara watak kapitalisnya, namun ia adalah penganut paham militerisme yang juga harus bertangung jawab terhadap tragedi 1998-1999.
Sekal lagi, apapun namanya, bagaimanapun ketiga pasangan calon ini menyembunyikan identitas dirinya, selihai apapun mereka mengilusi rakyat, yang pasti watak kapitalis akan melekat padanya. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa kapitalisme hari ini telah memasuki fase neoliberalisme, sehingga kapitalisme varian apapun, senang tidak senang, mau tidak mau, harus mengikut dan membonceng di belakang neoliberalisme.
Watak Neoliberal pada Proses Pemilu
Sebelumnya kita telah memahami bahwa ketiga pasangan calon ini adalah antek-antek neoliberal di Indonesia. Kita telah melihat pada seluruh kasus, kaum neoliberal tidak mengkampanyekan program politiknya. Mereka tidak menjanjikan upah yang lebih rendah, menghancurkan negara kesejahteraan, mengurangi pensiun, meningkatkan harga bahan-bahan makanan dan pelayanan sosial yang mendasar. Sebaliknya, kaum neoliberal mengidentikkan dirinya sebagai populis, mengecam pejabat-pejabat neoliberal dan menjanjikan perubahan yang mendasar. Dalam pertarungan untuk menempati jabatan kepresidenan, slogan populis dan nasionalis sangat mendominasi. Para kandidat berjanji untuk menyelesaiakn masalah-masalah kemiskinan dan pengangguran. Para penganjur utama doktrin pasar bebas dikecamnya habis-habisan sehingga di mata rakyat mereka tampak sebagai musuh bersama yang mesti dienyahkan dari panggung kekuasaan politik. Tetapi, sekali kursi kepresidenan sudah didudukinya, komitmen penganut pembaharuan adalah menjadi budak kepada penyesuaian gaya IMF, World Bank dan program stabilisasi yang sama kerasnya dengan rejim neoliberal sebelumnya yang telah dihujatnya habis-habisan. Rejm baru ini menghancurkan seluruh sistem kesejahteraan sosial, menghapuskan undang-undang perlindungan pekerja, menarik ke bahwa spiral upah, meningkatkan pengangguran dan pertumbuhan sektor ekonomi informal, sehingga menyebabkan kemiskinan rakyat yang semakin meluas.
Program kampanye pemilu berhubungan terbalik dengan politik paska pemilu. Neoliberalisme telah menghina proses pemilu dengan memarjinalkan badan pembuat undang-undang, pada periode paska pemilu. Di bawah neoliberalisme, politik pemilu menjadi tidak berarti sebagai metode yang menyediakan aneka pilihan yang penuh arti kepada pemilih, dimana harapan pemberi suara berkorelasi dengan hasil pemilu. Hasilnya menyangsikan keseluruhan isu dari pemerintah pilihan rakyat. Pemilu yang tidak representatif adalah hasil fundamental dari karakter elitis neoliberalisme, dimana kebijakan sosial ekonomi bertentangan dengan pemilu yang bebas.
Di bawah pemerintahan militer, tindakan-tindakan neoliberal diumumkan secara terbuka dan dipaksakan. Di bawah pemerintahan sipil, kebijakan neoliberal diterapkan secara terselubung dan dipaksakan melalui mandat pemilu palsu. Legitimasi palsu (pseudo legitimacy) dari rejim neoliberal menyandarkan dirinya pada asumsi palsu bahwa pemerintah “dipilih secara bebas.” Tetapi politikus hasil pemilu hanya merupakan wakil sebuah posisi yang dipertahankan di depan umum. Dari konteks politik, proses pemilu kekurangan legitimasi sebagaimana pada contoh lainnya disebut politik kotor.
Secara umum, kampanye pemilu neoliberal adalah manipulatif untuk mengamankan perolehan suara yang secara diametral bertentangan dengan dukungan mayoritas pemilih. Oposisi itu tak hanya dalam bentuk luruhnya kepercayaan tapi, terutama pada gagasan tentang pemerintahan perwakilan. James Petras mengungkapkan bahwa siklus neoliberal, reproduksi rejim neoliberal, juga menjadi basis bagi para politisi tangguh untuk mendistorsi (menyimpangkan) proses pemilu melalui manipulasi kesadaran, kian mendalamnya jurang antara pilihan (preferensi) pemilih dengan praktek dari kelas politik dan antara proses pemilu dan kebijakan yang dihasilkannya.
Masih ingatkah kita dengan SKB 4 Menteri, masih ingatkah kita dengan privatisasi beberapa BUMN yang menguasai hajat hidup oang banyak dan pengesahan UU BHP? Masih ingatkah kita denan praktek-praktek antara lain munculnya PHK massal akibat kebijakan-kebijakan neoliberal yang mencabut subsidi, menaikkan harga BBM dan TDL? Ditambah lagi dengan pelegalan sistem buruh kontrak, outsourcing dan kebijakan perburuhan lainnya yang pro modal asing dan mengebiri hak kaum pekerja.
Juga pengingkaran terhadap penuntasan kasus pelanggaran HAM. Hadirnya kembali wajah-wajah lama dalam bursa pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia membuat penuntasan berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu kian sulit. Apalagi rekam jejak mereka terkait dengan isu pelanggaran HAM jauh dari baik apalagi memuaskan.
Selama belum ada blok politik yang menjadi rival sejati bagi blok politik borjuis, maka niscaya yang ada hanyalah ilusi semata. Perubahan yang terjadi bukanlah perubahan yang substansial, melainkan perubahan yang formalistis belaka. Borjuis tetap berjaya sementara kaum rakyat pekerja semakin terpuruk dalam keproletariannya.
Pemilu presiden memang tinggal menghitung hari. Sekali lagi tokoh-tokoh yang bertarung adalah tokoh-tokoh yang secara ideologi dan kelas berpihak pada kepentingan kapitalis. Sudah saatnya rakyat sebagai stake owner bangkit melawan. Kelas-kelas revolusioner harus mulai mengkonsolidasikan diri dan membentuk blok politik alternatif. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menyatakan sikap dengan memilih untuk tidak memilih pada pemilu presiden 2009.
* Penulis adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, sekaligus anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Sulawesi Selatan.
** Siapa saja dipersilahkan mengutip, menggandakan, menyebarluaskan sebagian atau seluruh materi yang termuat dalam portal ini selama untuk kajian dan mendukung gerakan rakyat. Untuk keperluan komersial pengguna harus mendapatkan ijin tertulis dari pengelola portal Prakarsa Rakyat. Setiap pengutipan, penggandaan dan penyebarluasan sebagian atau seluruh materi harus mencantumkan sumber (portal Prakarsa Rakyat atau www.prakarsa-rakyat.org).
Labels: bulletin sadar
0 Comments:
d-i-s-c-l-a-i-m-e-r
games tools
- agent waste
- asstroidz
- billyard
- binatang kembar
- blok 2
- bounce
- bullet snale 3
- cavern klamrisk
- chicken invaders roty
- dynomite deluxe
- feeding frenzy 2
- freeciv 2.1.9
- hell chess
- insaniquarium
- luxor
- monopoly
- moto
- pandaland
- picross mania
- pizza frenzy
- sponge bob collapse
- standing point the final stronghold
- the power
- zuma deluxe
temen gue
- adsense for feeds
- anang's blog
- angkatan sembilan belas
- babu ngeblog
- blog oranje
- blogger templates bycaz
- btemplates
- catatan dunia ira
- daleclick templates
- densu-nod
- desakuArt production
- dua mata
- facebook sunnah
- foto tanpa genre
- free blogger template layout
- free musicz mp3
- free templates
- hujan musik indonesia
- imam marsus
- indo bloger
- indo lawas
- indo metal box
- islam substantif
- karim samman
- kidz music community
- klasik rock indonesia
- lumajang music community
- media putra
- mr. ozay's blog
- music 4 sharing
- nona cantiq
- peduli buruh migran
- pers bebas, pintu demokrasi
- rindu pulang
- sanggar alif kaligrafi
- sanggar mata air
- soft 4 u
- template unik
- tunas trans solusindo
- tutorial jitu
- uc1n blog's
- underground indonesia
- unduh musik
- upex rock
- wonogiri voucher
bookmarks gue
- angel fire
- anymaking
- blog lines
- blog template 4u
- blogspot template
- blogspot templetes
- cbm card
- club brillian (id: cgd935029)
- currency converter
- cyber fret
- dhanny dhuzell site's
- dynamic tools drive
- editing foto online
- ez wp themes
- free templates online
- free warebb
- gpro tab
- gudang lagu
- guitar about
- guitar chords/scales
- guitarists
- hot frets
- html-kit-favicon
- indo mp3
- indonesia mp3
- indrakila band
- inilah indie
- isnaini blogger templates
- lumajang music
- mozilla themes
- mozilla themes
- mp3 indonesia
- musician
- musisi
- nolkoma band
- pax
- pp. daarul rahman jakarta
- rubby band
- sekolah rakyat indonesia
- smart telecom
- speed test
- speed test smart
- stafa band
- tab crawler
- tagihan pln jatim
- translator online (babelfish)
- translator online (toggle text)
- universitas terbuka
- warung mp3
- warung musik
- web2 feel
- youtube
kidz music community, desakuArt production, crew forsil songolas, sahabat forsil songolas, sekolah rakyat merdeka, perguruan rakyat merdeka, sekretariat anak merdeka indonesia, sanggar alif kaligrafi, sanggar mata air, exsongolas management, ponpes daarul rahman jakarta, ponpes an-nuqayah sumenep, boom cell cellulare, tunas trans solusindo, semeru scooter club '06 klakah, komunitas indie lumajang, solidaritas buruh migran indonesia - jawa timur, peduli buruh migran, prakarsa rakyat, bulletin sadar, praxis, dll.
(mohon maaf jika ada yang belum disebutkan)
terima kasih atas kunjungan anda, kritik saran yang membangun adalah kunci keberhasilan kami.
deditsabit@smara
thanks for the template design to skinCorner | grunged girl image from dapinoGraphics



