main |
sidebar

supported by deditsabit
supported by deditsabit
Jumlah Posting & Komentar:
buah artikel telah ditulis
buah komentar masuk


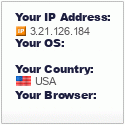



supported by deditsabit
supported by deditsabit
deditsabit bekerjasama dengan dan atas dukungan:
kidz music community, desakuArt production, crew forsil songolas, sahabat forsil songolas, sekolah rakyat merdeka, perguruan rakyat merdeka, sekretariat anak merdeka indonesia, sanggar alif kaligrafi, sanggar mata air, exsongolas management, ponpes daarul rahman jakarta, ponpes an-nuqayah sumenep, boom cell cellulare, tunas trans solusindo, semeru scooter club '06 klakah, komunitas indie lumajang, solidaritas buruh migran indonesia - jawa timur, peduli buruh migran, prakarsa rakyat, bulletin sadar, praxis, dll.
(mohon maaf jika ada yang belum disebutkan)
terima kasih atas kunjungan anda, kritik saran yang membangun adalah kunci keberhasilan kami.
deditsabit@smara

supported by deditsabit
play musik gue
blogroll gue
menurut label
- adsense (1)
- advokasi (2)
- anak (8)
- artikel (11)
- bakat (1)
- bisnis (2)
- budaya (3)
- bulletin sadar (198)
- buruh (1)
- buruh migran (10)
- cdma (1)
- cellulare (4)
- cerita gambar (2)
- deditsabit (4)
- elektronik (2)
- energi (1)
- event (5)
- facebook (4)
- gsm (1)
- ham (1)
- hukum (2)
- informatika (6)
- internet (4)
- jejaring (2)
- kartun (1)
- kdrt (1)
- kesehatan (4)
- kesenian (1)
- keyakinan (8)
- komputer (3)
- konservasi (1)
- korupsi (2)
- lingkungan (2)
- lomba (1)
- lumajang (1)
- maulid hijau (1)
- movie review (19)
- muhammad saw. (1)
- musik (14)
- nuklir (1)
- olah raga (4)
- pendidikan (7)
- perda (1)
- perempuan (9)
- Perguruan Rakyat Merdeka (56)
- peristiwa (7)
- politik (70)
- prestasi (1)
- produk (1)
- qur'an (1)
- radiasi (1)
- religi (9)
- remaja (9)
- resensi buku (27)
- rohani (3)
- sejarah (4)
- serial number (1)
- siswa (1)
- software (1)
- sosial (3)
- ssc '06 klakah (2)
- teknologi (3)
- tv kabel (2)
- undang-undang (1)
- undangan (3)
- video (2)
- website (1)
- wisata (1)
ngikut gak ni...?
statistik blog:
buah artikel telah ditulis
buah komentar masuk

supported by deditsabit
Bulletin SADAR Edisi: 205 Tahun V - 2009, REVITALISASI INGATAN ATAS BUDAYA KEKERASAN DI INDONESIA UNTUK REKONSILIASI ANAK BANGSA
SADAR
Simpul Untuk Keadilan dan Demokrasi
Edisi: 205 Tahun V - 2009
Sumber: www.prakarsa-rakyat.org
REVITALISASI INGATAN ATAS BUDAYA KEKERASAN DI INDONESIA UNTUK REKONSILIASI ANAK BANGSA
Oleh Sapto Raharjanto *
Bila ingin melihat sejarah Indonesia abad ke-20 dan awal abad ke 21 dengan jernih, niscaya kita akan menemukan betapa banyaknya darah yang telah tumpah di bumi pertiwi. Bahkan ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwa Indonesia is a violent country. Yang menyedihkan, sebagian tragedi tersebut disebabkan atau dilakukan oleh pihak yang paling berkuasa, negara. Para ahli lalu menyebut fenomena ini sebagai kekerasan oleh Negara. Menurut Andrianus Meliala, kekerasan oleh negara bisa diasosiasikan dengan kekerasan politik, teror politik, kebrutalan rezim, penindasan oleh penguasa, kejahatan oleh negara dan pelanggaran HAM berat. Bentuk-bentuknya antara lain, beating, (arbritrarily) killing, illegal detention, robbing, (systematic) raping, assaults on civilian, forced relocation, torturing, indiscriminate use of weapon, isolation, stigmatization, blocking acces, dan election fraud.
Di Indonesia, catatan sejarah mengindikasikan bahwa negara maupun istitusi sipil, seperti laskar paramiliter telah berulangkali menjadi pemicu bahkan pelaku kekerasan terhadap warga negara dalam catatan sejarah, pemberontakan dan gerakan separatis seperti Darul Islam dan PRRI/Permesta pada masa Soekarno diselesaikan bukan lewat jalur diplomasi, melainkan operasi militer yang memilukan hati.
Bagi Indonesia, tahun 1965 merupakan suatu tahun yang luar biasa penting. Sebab saat itu adalah tahun terjadinya peristiwa 1 Oktober 1965, yang memutar balik proses sejarah perkembangan negara ini. Sejarah Indonesia sendiri pada masa Orde Baru Soeharto adalah merupakan penjaga kekuasaan bagi rezim yang berkuasa, dalam hal ini termasuk ketika rezim Orde Baru memaknai tafsir mengenai peristiwa tragedi nasional 1 Oktober 1965. Kemudian berujung kepada kesimpulan bahwa PKI menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atau dalang atas semua kejadian berdarah. Peristiwa ini menjadi tragedi pembunuhan massal yang diperkirakan menghilangkan nyawa setengah hingga satu juta nyawa orang Indonesia oleh orang Indonesia sendiri.
Tragedi 65 adalah merupakan titik tolak dari krisis kebangsaan di Indonesia, dikarenakan ketika membicarakan mengenai tragedi 65 kita tidak hanya membicarakan mengenai pembunuhan 7 jenderal di Lubang Buaya. Ataupun adanya sebuah gerakan yang pada akhirnya mengarah kepada pergantian kekuasaan di Indonesia. Tetapi ketika kita membicarakan permasalahan tragedi 65 maka di Indonesia dimulailah sebuah masa yang penuh dengan ketakutan. Budaya teror dan kekerasan menjadi sebuah hal yang lumrah bagi penguasa untuk melanggengkan kekuasaan dan hegemoninya jauh lebih terstruktur dari era Soekarno.
Dalam praktek politiknya pemerintahan Orde Baru menerapkan tiga hal: Pertama, melakukan proses ideologisasi, yaitu menerapkan tunggal negara. Pada fase ini berkembang jargon-jargon yang sifatnya top-down, seperti ide pembangunanisme. Kedua, kalaupun terdapat protes dari adanya ideologisasi tersebut, masih menyisakan ketidaksepakatan di tingkat massa rakyat, yang berlaku kemudian adalah proses stigmatisasi dengan mengembangkan jargon politik: anti pembangunan, anti ideologi negara (Pancasila) dan berpaham komunis dan lain sebagainya. Sedangkan yang ketiga adalah bila terdapat perlawanan yang keras, seperti demonstrasi maka pemerintah dengan segera menggunakan pendekatan keamanan.
Adanya praktik tindak kekerasan dan budaya teror yang diwariskan baik pada masa Soekarno maupun Soeharto terus berlangsung pada era reformasi yang dianggap jauh lebih demokratis. Tercatat peristiwa Madiun (1948), DI/TII (1960), PRRI/Permesta (1960), Peristiwa Aksi Sepihak (1964), Peristiwa G-30-S (1965), Pembunuhan Massal pasca G-30-S (1965-1966), Pemenjaraan, Penyiksaan, Pembuangan massal pasca G-30-S (1966-1980), Pemenjaraan, Penyiksaan Kyai (1971), Peristiwa Tanjung Priok (1984), Peristiwa Talangsari (1989), Peristiwa Kudatuli (1996), Peristiwa Mei, Trisakti, Semanggi, Dukun Santet (1998), DOM Aceh (1980-2000), Tragedi Monas (2008).
Yang juga patut menjadi perhatian, selain kasus-kasus yang bersifat massal, ada lagi perkara kekerasan yang bersifat pribadi-pribadi terhadap orang-orang yang dianggap membahayakan. Kekerasan yang terjadi bukan dikaitkan pada tanggal atau tempat terjadinya, melainkan identitas si korban. Si korban dianggap sebagai representasi yang memiliki banyak perbedaan bahkan berlawanan dengan visi Negara. Bisa jadi negara maupun pendukung-pendukungnya terusik dengan perlawanan ini sehingga berusaha mencari jalan untuk menghentikannya. Caranya tentu beragam, mulai dari yang halus sampai yang kasar, tercatat nama Tan Malaka, Marsinah, Fuad Muhammad Syafrudin (Udin), Wiji Thukul, Baharudin Lopa dan Munir.
Akhirnya sebuah kata-kata bijak yang diungkapkan oleh Amstutz, “Ingatan bagi korban kekerasan masa lalu bukan hanya sekedar rekaman sebuah peristiwa, melainkan juga bentuk penagihan atas masa lalu yang pernah dideritanya, sangat diperlukan untuk mendudukkan persoalan pada tempatnya untuk memulai hidup baru yang terbebas dari dendam sejarah. Ingatan perlu disampaikan kepada generasi selanjutnya agar mereka dapat belajar untuk memahami derita orang lain, berlapang dada memaafkan masa lalu, dan berupaya memutus spiral kekerasan dengan menciptakan peradaban yang anti kekerasan.
* Penulis adalah Anggota Regio Jawa Timur Masyarakat Santri Untuk Advokasi Rakyat Indonesia (Syarikat Indonesia).
** Siapa saja dipersilahkan mengutip, menggandakan, menyebarluaskan sebagian atau seluruh materi yang termuat dalam portal ini selama untuk kajian dan mendukung gerakan rakyat. Untuk keperluan komersial pengguna harus mendapatkan ijin tertulis dari pengelola portal Prakarsa Rakyat. Setiap pengutipan, penggandaan dan penyebarluasan sebagian atau seluruh materi harus mencantumkan sumber (portal Prakarsa Rakyat atau www.prakarsa-rakyat.org).
Simpul Untuk Keadilan dan Demokrasi
Edisi: 205 Tahun V - 2009
Sumber: www.prakarsa-rakyat.org
REVITALISASI INGATAN ATAS BUDAYA KEKERASAN DI INDONESIA UNTUK REKONSILIASI ANAK BANGSA
Oleh Sapto Raharjanto *
Bila ingin melihat sejarah Indonesia abad ke-20 dan awal abad ke 21 dengan jernih, niscaya kita akan menemukan betapa banyaknya darah yang telah tumpah di bumi pertiwi. Bahkan ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwa Indonesia is a violent country. Yang menyedihkan, sebagian tragedi tersebut disebabkan atau dilakukan oleh pihak yang paling berkuasa, negara. Para ahli lalu menyebut fenomena ini sebagai kekerasan oleh Negara. Menurut Andrianus Meliala, kekerasan oleh negara bisa diasosiasikan dengan kekerasan politik, teror politik, kebrutalan rezim, penindasan oleh penguasa, kejahatan oleh negara dan pelanggaran HAM berat. Bentuk-bentuknya antara lain, beating, (arbritrarily) killing, illegal detention, robbing, (systematic) raping, assaults on civilian, forced relocation, torturing, indiscriminate use of weapon, isolation, stigmatization, blocking acces, dan election fraud.
Di Indonesia, catatan sejarah mengindikasikan bahwa negara maupun istitusi sipil, seperti laskar paramiliter telah berulangkali menjadi pemicu bahkan pelaku kekerasan terhadap warga negara dalam catatan sejarah, pemberontakan dan gerakan separatis seperti Darul Islam dan PRRI/Permesta pada masa Soekarno diselesaikan bukan lewat jalur diplomasi, melainkan operasi militer yang memilukan hati.
Bagi Indonesia, tahun 1965 merupakan suatu tahun yang luar biasa penting. Sebab saat itu adalah tahun terjadinya peristiwa 1 Oktober 1965, yang memutar balik proses sejarah perkembangan negara ini. Sejarah Indonesia sendiri pada masa Orde Baru Soeharto adalah merupakan penjaga kekuasaan bagi rezim yang berkuasa, dalam hal ini termasuk ketika rezim Orde Baru memaknai tafsir mengenai peristiwa tragedi nasional 1 Oktober 1965. Kemudian berujung kepada kesimpulan bahwa PKI menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atau dalang atas semua kejadian berdarah. Peristiwa ini menjadi tragedi pembunuhan massal yang diperkirakan menghilangkan nyawa setengah hingga satu juta nyawa orang Indonesia oleh orang Indonesia sendiri.
Tragedi 65 adalah merupakan titik tolak dari krisis kebangsaan di Indonesia, dikarenakan ketika membicarakan mengenai tragedi 65 kita tidak hanya membicarakan mengenai pembunuhan 7 jenderal di Lubang Buaya. Ataupun adanya sebuah gerakan yang pada akhirnya mengarah kepada pergantian kekuasaan di Indonesia. Tetapi ketika kita membicarakan permasalahan tragedi 65 maka di Indonesia dimulailah sebuah masa yang penuh dengan ketakutan. Budaya teror dan kekerasan menjadi sebuah hal yang lumrah bagi penguasa untuk melanggengkan kekuasaan dan hegemoninya jauh lebih terstruktur dari era Soekarno.
Dalam praktek politiknya pemerintahan Orde Baru menerapkan tiga hal: Pertama, melakukan proses ideologisasi, yaitu menerapkan tunggal negara. Pada fase ini berkembang jargon-jargon yang sifatnya top-down, seperti ide pembangunanisme. Kedua, kalaupun terdapat protes dari adanya ideologisasi tersebut, masih menyisakan ketidaksepakatan di tingkat massa rakyat, yang berlaku kemudian adalah proses stigmatisasi dengan mengembangkan jargon politik: anti pembangunan, anti ideologi negara (Pancasila) dan berpaham komunis dan lain sebagainya. Sedangkan yang ketiga adalah bila terdapat perlawanan yang keras, seperti demonstrasi maka pemerintah dengan segera menggunakan pendekatan keamanan.
Adanya praktik tindak kekerasan dan budaya teror yang diwariskan baik pada masa Soekarno maupun Soeharto terus berlangsung pada era reformasi yang dianggap jauh lebih demokratis. Tercatat peristiwa Madiun (1948), DI/TII (1960), PRRI/Permesta (1960), Peristiwa Aksi Sepihak (1964), Peristiwa G-30-S (1965), Pembunuhan Massal pasca G-30-S (1965-1966), Pemenjaraan, Penyiksaan, Pembuangan massal pasca G-30-S (1966-1980), Pemenjaraan, Penyiksaan Kyai (1971), Peristiwa Tanjung Priok (1984), Peristiwa Talangsari (1989), Peristiwa Kudatuli (1996), Peristiwa Mei, Trisakti, Semanggi, Dukun Santet (1998), DOM Aceh (1980-2000), Tragedi Monas (2008).
Yang juga patut menjadi perhatian, selain kasus-kasus yang bersifat massal, ada lagi perkara kekerasan yang bersifat pribadi-pribadi terhadap orang-orang yang dianggap membahayakan. Kekerasan yang terjadi bukan dikaitkan pada tanggal atau tempat terjadinya, melainkan identitas si korban. Si korban dianggap sebagai representasi yang memiliki banyak perbedaan bahkan berlawanan dengan visi Negara. Bisa jadi negara maupun pendukung-pendukungnya terusik dengan perlawanan ini sehingga berusaha mencari jalan untuk menghentikannya. Caranya tentu beragam, mulai dari yang halus sampai yang kasar, tercatat nama Tan Malaka, Marsinah, Fuad Muhammad Syafrudin (Udin), Wiji Thukul, Baharudin Lopa dan Munir.
Akhirnya sebuah kata-kata bijak yang diungkapkan oleh Amstutz, “Ingatan bagi korban kekerasan masa lalu bukan hanya sekedar rekaman sebuah peristiwa, melainkan juga bentuk penagihan atas masa lalu yang pernah dideritanya, sangat diperlukan untuk mendudukkan persoalan pada tempatnya untuk memulai hidup baru yang terbebas dari dendam sejarah. Ingatan perlu disampaikan kepada generasi selanjutnya agar mereka dapat belajar untuk memahami derita orang lain, berlapang dada memaafkan masa lalu, dan berupaya memutus spiral kekerasan dengan menciptakan peradaban yang anti kekerasan.
* Penulis adalah Anggota Regio Jawa Timur Masyarakat Santri Untuk Advokasi Rakyat Indonesia (Syarikat Indonesia).
** Siapa saja dipersilahkan mengutip, menggandakan, menyebarluaskan sebagian atau seluruh materi yang termuat dalam portal ini selama untuk kajian dan mendukung gerakan rakyat. Untuk keperluan komersial pengguna harus mendapatkan ijin tertulis dari pengelola portal Prakarsa Rakyat. Setiap pengutipan, penggandaan dan penyebarluasan sebagian atau seluruh materi harus mencantumkan sumber (portal Prakarsa Rakyat atau www.prakarsa-rakyat.org).
Labels: bulletin sadar
0 Comments:
d-i-s-c-l-a-i-m-e-r
games tools
- agent waste
- asstroidz
- billyard
- binatang kembar
- blok 2
- bounce
- bullet snale 3
- cavern klamrisk
- chicken invaders roty
- dynomite deluxe
- feeding frenzy 2
- freeciv 2.1.9
- hell chess
- insaniquarium
- luxor
- monopoly
- moto
- pandaland
- picross mania
- pizza frenzy
- sponge bob collapse
- standing point the final stronghold
- the power
- zuma deluxe
temen gue
- adsense for feeds
- anang's blog
- angkatan sembilan belas
- babu ngeblog
- blog oranje
- blogger templates bycaz
- btemplates
- catatan dunia ira
- daleclick templates
- densu-nod
- desakuArt production
- dua mata
- facebook sunnah
- foto tanpa genre
- free blogger template layout
- free musicz mp3
- free templates
- hujan musik indonesia
- imam marsus
- indo bloger
- indo lawas
- indo metal box
- islam substantif
- karim samman
- kidz music community
- klasik rock indonesia
- lumajang music community
- media putra
- mr. ozay's blog
- music 4 sharing
- nona cantiq
- peduli buruh migran
- pers bebas, pintu demokrasi
- rindu pulang
- sanggar alif kaligrafi
- sanggar mata air
- soft 4 u
- template unik
- tunas trans solusindo
- tutorial jitu
- uc1n blog's
- underground indonesia
- unduh musik
- upex rock
- wonogiri voucher
bookmarks gue
- angel fire
- anymaking
- blog lines
- blog template 4u
- blogspot template
- blogspot templetes
- cbm card
- club brillian (id: cgd935029)
- currency converter
- cyber fret
- dhanny dhuzell site's
- dynamic tools drive
- editing foto online
- ez wp themes
- free templates online
- free warebb
- gpro tab
- gudang lagu
- guitar about
- guitar chords/scales
- guitarists
- hot frets
- html-kit-favicon
- indo mp3
- indonesia mp3
- indrakila band
- inilah indie
- isnaini blogger templates
- lumajang music
- mozilla themes
- mozilla themes
- mp3 indonesia
- musician
- musisi
- nolkoma band
- pax
- pp. daarul rahman jakarta
- rubby band
- sekolah rakyat indonesia
- smart telecom
- speed test
- speed test smart
- stafa band
- tab crawler
- tagihan pln jatim
- translator online (babelfish)
- translator online (toggle text)
- universitas terbuka
- warung mp3
- warung musik
- web2 feel
- youtube
kidz music community, desakuArt production, crew forsil songolas, sahabat forsil songolas, sekolah rakyat merdeka, perguruan rakyat merdeka, sekretariat anak merdeka indonesia, sanggar alif kaligrafi, sanggar mata air, exsongolas management, ponpes daarul rahman jakarta, ponpes an-nuqayah sumenep, boom cell cellulare, tunas trans solusindo, semeru scooter club '06 klakah, komunitas indie lumajang, solidaritas buruh migran indonesia - jawa timur, peduli buruh migran, prakarsa rakyat, bulletin sadar, praxis, dll.
(mohon maaf jika ada yang belum disebutkan)
terima kasih atas kunjungan anda, kritik saran yang membangun adalah kunci keberhasilan kami.
deditsabit@smara
thanks for the template design to skinCorner | grunged girl image from dapinoGraphics



