main |
sidebar

supported by deditsabit
supported by deditsabit
Jumlah Posting & Komentar:
buah artikel telah ditulis
buah komentar masuk


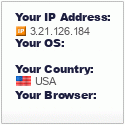



supported by deditsabit
supported by deditsabit
deditsabit bekerjasama dengan dan atas dukungan:
kidz music community, desakuArt production, crew forsil songolas, sahabat forsil songolas, sekolah rakyat merdeka, perguruan rakyat merdeka, sekretariat anak merdeka indonesia, sanggar alif kaligrafi, sanggar mata air, exsongolas management, ponpes daarul rahman jakarta, ponpes an-nuqayah sumenep, boom cell cellulare, tunas trans solusindo, semeru scooter club '06 klakah, komunitas indie lumajang, solidaritas buruh migran indonesia - jawa timur, peduli buruh migran, prakarsa rakyat, bulletin sadar, praxis, dll.
(mohon maaf jika ada yang belum disebutkan)
terima kasih atas kunjungan anda, kritik saran yang membangun adalah kunci keberhasilan kami.
deditsabit@smara

supported by deditsabit
play musik gue
blogroll gue
menurut label
- adsense (1)
- advokasi (2)
- anak (8)
- artikel (11)
- bakat (1)
- bisnis (2)
- budaya (3)
- bulletin sadar (198)
- buruh (1)
- buruh migran (10)
- cdma (1)
- cellulare (4)
- cerita gambar (2)
- deditsabit (4)
- elektronik (2)
- energi (1)
- event (5)
- facebook (4)
- gsm (1)
- ham (1)
- hukum (2)
- informatika (6)
- internet (4)
- jejaring (2)
- kartun (1)
- kdrt (1)
- kesehatan (4)
- kesenian (1)
- keyakinan (8)
- komputer (3)
- konservasi (1)
- korupsi (2)
- lingkungan (2)
- lomba (1)
- lumajang (1)
- maulid hijau (1)
- movie review (19)
- muhammad saw. (1)
- musik (14)
- nuklir (1)
- olah raga (4)
- pendidikan (7)
- perda (1)
- perempuan (9)
- Perguruan Rakyat Merdeka (56)
- peristiwa (7)
- politik (70)
- prestasi (1)
- produk (1)
- qur'an (1)
- radiasi (1)
- religi (9)
- remaja (9)
- resensi buku (27)
- rohani (3)
- sejarah (4)
- serial number (1)
- siswa (1)
- software (1)
- sosial (3)
- ssc '06 klakah (2)
- teknologi (3)
- tv kabel (2)
- undang-undang (1)
- undangan (3)
- video (2)
- website (1)
- wisata (1)
ngikut gak ni...?
statistik blog:
buah artikel telah ditulis
buah komentar masuk

supported by deditsabit
Buletin SADAR Edisi: 338 Tahun VII - 2011, ISSN: 2086-2024, PSSI DAN LPI: WAJAH POLITIK DALAM BISNIS OLAHRAGA
Oleh : Sentiko*
Pada penutup tahun 2010 lalu kita disuguhi berita media massa dengan euforia masyarakat terhadap Timnas sepak bola Indonesia. Sesuatu yang sangat luar biasa sehingga mampu menyihir pemberitaan lainnya. Namun selesainya hajat Piala AFF 2010, memunculkan peristiwa menarik karena lahirnya kompetisi di luar kendali dan pengaruh PSSI yakni Liga Primer Indonesia (LPI). Walau telah berlangsung persiapan selama hampir setengah tahun lalu, tetapi konflik terbuka antara PSSI yang menyatakan dirinya penguasa sepak bola Indonesia baru bereaksi keras karena LPI benar-benar berjalan.
Ada apa sesungguhnya? Apakah benar karena penggunaan APBN-APBD dan prestasi yang melandasinya? Patut kita berpikir mendalam, tanpa terjebak pada kepentingan keduanya, tetapi kepentingan nasional khususnya olahraga adalah yang pokok.
Lepas dari semua kontroversi hukum, mayoritas masyarakat pecinta sepak bola negeri ini akan terseret pada dinamika adanya dua kompetisi level tinggi di negeri ini. Sepak bola bukan lagi murni sepak bola, tetapi sudah menjadi perpaduan antara hobi, seni, politik dan bisnis. Dalam dunia neoliberalisme, olahraga dibagi dalam dua level sesuai peruntukkannya. Yang pertama adalah amatir, dimana sebagai tempat menyalurkan hobi, pembibitan dan masih dalam tanggungan negara. Sementara di lain pihak adalah level profesional, dimana level ini sudah bersifat pertandingan dengan nilai komersial tinggi, atlet dan cabang olahraganya menjadi obyek pasar. Level ini melepaskan peran negara, dikuasai oleh korporasi untuk kepentingan bisnis mereka. Kita bisa lihat banyak contoh pada level ini, baik sepak bola, tenis, maupun motor GP.
Bagaimana dengan sepak bola Indonesia?
Bila menilik situasi sekarang, Liga Premier Indonesia (LPI) memberi jawaban atas level profesional. Dan PSSI yang membuat kompetisi Liga Super Indonesia (LSI) belum mampu menjawab apa yang seharusnya dilakukan dalam memperlakukan kompetisi olahraga. Dalam situasi negara menerapkan neoliberalisme maka kompetisi seharusnya memberikan keuntungan finansial, bukan sebaliknya merugikan dan menggerogoti keuangan negara. Catatan yang ada menunjukkan PSSI masih harus menyedot anggaran APBN sekitar 80 miliar rupiah setahun dan masih mendapatkan suntikan dari sponsor. Belum lagi setiap klub sepak bola mendapatkan anggaran dari APBD dan juga sponsor.
Sementara LPI menawarkan kompetisi yang lepas dari dana-dana APBN dan APBD. Logika di sini LPI tepat, namun di hal lain masih harus dipertanyakan, yakni soal kualitas pemain secara umum yang masih sangat tidak dikenal insan sepak bola, kecuali Irfan Bachdim atau beberapa saja.
LPI ini meniru model kompetisi di Inggris. Dan sebenarnya PSSI juga mencoba hal yang sama dengan membuat PT BLI (Badan Liga Indonesia), tetapi PSSI tidak berani membangun BLI yang lepas dari anggaran negara. Bila menyadari ada kekeliruan yang dilakukan seharusnya PSSI mengambil langkah kompromi dengan LPI bukan konfrontatif, karena merugikan semua pihak dan menghambat kemajuan sepak bola Indonesia, apalagi ada ancaman bagi klub dan pemain yang tergabung dalam LPI.
Seperti diketahui secara umum, bahwa permusuhan yang terjadi antara PSSI yang menggelar LSI dengan BLI-nya dan LPI adalah semata pertarungan bisnis dan juga politik. PSSI didukung kuat oleh kerajaan bisnis grup Bakrie dengan partainya. Sedangkan LPI didukung penuh oleh Arifin Panigoro sertai jaringan partai politiknya. Tarik-menarik kepentingan bisnis bernilai besar ini mulai diungkap banyak kalangan, sayangnya tidak ada langkah konkrit upaya menyelamatkan sepak bola Indonesia. Pertarungan dua kubu kerajaan bisnis ini tentu berdampak negatif dan tidak mendidik, baik bagi masyarakat bola maupun politik masyarakat itu sendiri. Tentu, kita tidak mau masuk dalam dua kubu tersebut. Kita masuk dalam kubu yang ingin memajukan sepak bola Indonesia.
Seharusnya kompetisi profesional dilepas dari PSSI dan dibuat satu badan khusus, seperti konsorsium serta lepas dari anggaran negara maupun campur tangan PSSI. Kompromi antara BLI dengan LPI bisa dilakukan untuk menjadi penyelenggara berorientasi komersial. Dan PSSI mengambil peran pembinaan klub amatir hingga semi profesional.
Seperti Liga Utama Inggris adalah badan tersendiri dan bekerja secara profesional. Berkiprah dan berkompetisi layaknya dalam pertarungan dagang di dunia kapitalisme, siapa yang kuat dan bermodal besar akan menang. Prestasi bisa dinomorduakan. Tetapi dari proses ini negara mendapatkan keuntungan yang begitu besar. Dari mana pendapatan atau keuntungan negara? Kita bisa lihat di Inggris, Spanyol dan Italia pajak transfer pemain dan gaji pemain cukup besar berkisar antara 30-50% dari yang didapat pemain. Belum lagi pajak klub, penonton, iklan/sponsor dan sebagainya. Bisa dibayangkan pendapatan negara, mungkinkah ini tidak terbayang di para penggiat sepak bola level atas negeri ini?
Bila mau mengambil garis bisnis, maka model kompetisi di Eropa bisa diterapkan dengan pemisahan yang jelas dan pengaturan lembaga yang tepat. Jangan sampai olahraga hanya dipakai untuk kepentingan sesaat politisi yang juga berbisnis. Kondisi ini akan berdampak pada carut-marutnya prestasi sepakbola Indonesia. Bila terus-menerus dibiarkan, tentu tidak akan berkembang walau ada LSI maupun LPI. Begitulah wajah politik dan bisnis sepak bola Indonesia saat ini.
* Penulis adalah Suporter Timnas Indonesia dan anggota serikat buruh di Tangerang, sekaligus Anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Jabodetabek.
** Siapa saja dipersilahkan mengutip, menggandakan, menyebarluaskan sebagian atau seluruh materi yang termuat dalam portal ini selama untuk kajian dan mendukung gerakan rakyat. Untuk keperluan komersial pengguna harus mendapatkan ijin tertulis dari pengelola portal Prakarsa Rakyat. Setiap pengutipan, penggandaan dan penyebarluasan sebagian atau seluruh materi harus mencantumkan sumber (portal Prakarsa Rakyat atau www.prakarsa-rakyat.org).
Seperti diketahui secara umum, bahwa permusuhan yang terjadi antara PSSI yang menggelar LSI dengan BLI-nya dan LPI adalah semata pertarungan bisnis dan juga politik. PSSI didukung kuat oleh kerajaan bisnis grup Bakrie dengan partainya. Sedangkan LPI didukung penuh oleh Arifin Panigoro sertai jaringan partai politiknya. Tarik-menarik kepentingan bisnis bernilai besar ini mulai diungkap banyak kalangan, sayangnya tidak ada langkah konkrit upaya menyelamatkan sepak bola Indonesia. Pertarungan dua kubu kerajaan bisnis ini tentu berdampak negatif dan tidak mendidik, baik bagi masyarakat bola maupun politik masyarakat itu sendiri. Tentu, kita tidak mau masuk dalam dua kubu tersebut. Kita masuk dalam kubu yang ingin memajukan sepak bola Indonesia.
Seharusnya kompetisi profesional dilepas dari PSSI dan dibuat satu badan khusus, seperti konsorsium serta lepas dari anggaran negara maupun campur tangan PSSI. Kompromi antara BLI dengan LPI bisa dilakukan untuk menjadi penyelenggara berorientasi komersial. Dan PSSI mengambil peran pembinaan klub amatir hingga semi profesional.
Seperti Liga Utama Inggris adalah badan tersendiri dan bekerja secara profesional. Berkiprah dan berkompetisi layaknya dalam pertarungan dagang di dunia kapitalisme, siapa yang kuat dan bermodal besar akan menang. Prestasi bisa dinomorduakan. Tetapi dari proses ini negara mendapatkan keuntungan yang begitu besar. Dari mana pendapatan atau keuntungan negara? Kita bisa lihat di Inggris, Spanyol dan Italia pajak transfer pemain dan gaji pemain cukup besar berkisar antara 30-50% dari yang didapat pemain. Belum lagi pajak klub, penonton, iklan/sponsor dan sebagainya. Bisa dibayangkan pendapatan negara, mungkinkah ini tidak terbayang di para penggiat sepak bola level atas negeri ini?
Bila mau mengambil garis bisnis, maka model kompetisi di Eropa bisa diterapkan dengan pemisahan yang jelas dan pengaturan lembaga yang tepat. Jangan sampai olahraga hanya dipakai untuk kepentingan sesaat politisi yang juga berbisnis. Kondisi ini akan berdampak pada carut-marutnya prestasi sepakbola Indonesia. Bila terus-menerus dibiarkan, tentu tidak akan berkembang walau ada LSI maupun LPI. Begitulah wajah politik dan bisnis sepak bola Indonesia saat ini.
* Penulis adalah Suporter Timnas Indonesia dan anggota serikat buruh di Tangerang, sekaligus Anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Jabodetabek.
** Siapa saja dipersilahkan mengutip, menggandakan, menyebarluaskan sebagian atau seluruh materi yang termuat dalam portal ini selama untuk kajian dan mendukung gerakan rakyat. Untuk keperluan komersial pengguna harus mendapatkan ijin tertulis dari pengelola portal Prakarsa Rakyat. Setiap pengutipan, penggandaan dan penyebarluasan sebagian atau seluruh materi harus mencantumkan sumber (portal Prakarsa Rakyat atau www.prakarsa-rakyat.org).
Sumber: PrakarsaRakyat
Labels: bulletin sadar, olah raga
0 Comments:
d-i-s-c-l-a-i-m-e-r
games tools
- agent waste
- asstroidz
- billyard
- binatang kembar
- blok 2
- bounce
- bullet snale 3
- cavern klamrisk
- chicken invaders roty
- dynomite deluxe
- feeding frenzy 2
- freeciv 2.1.9
- hell chess
- insaniquarium
- luxor
- monopoly
- moto
- pandaland
- picross mania
- pizza frenzy
- sponge bob collapse
- standing point the final stronghold
- the power
- zuma deluxe
temen gue
- adsense for feeds
- anang's blog
- angkatan sembilan belas
- babu ngeblog
- blog oranje
- blogger templates bycaz
- btemplates
- catatan dunia ira
- daleclick templates
- densu-nod
- desakuArt production
- dua mata
- facebook sunnah
- foto tanpa genre
- free blogger template layout
- free musicz mp3
- free templates
- hujan musik indonesia
- imam marsus
- indo bloger
- indo lawas
- indo metal box
- islam substantif
- karim samman
- kidz music community
- klasik rock indonesia
- lumajang music community
- media putra
- mr. ozay's blog
- music 4 sharing
- nona cantiq
- peduli buruh migran
- pers bebas, pintu demokrasi
- rindu pulang
- sanggar alif kaligrafi
- sanggar mata air
- soft 4 u
- template unik
- tunas trans solusindo
- tutorial jitu
- uc1n blog's
- underground indonesia
- unduh musik
- upex rock
- wonogiri voucher
bookmarks gue
- angel fire
- anymaking
- blog lines
- blog template 4u
- blogspot template
- blogspot templetes
- cbm card
- club brillian (id: cgd935029)
- currency converter
- cyber fret
- dhanny dhuzell site's
- dynamic tools drive
- editing foto online
- ez wp themes
- free templates online
- free warebb
- gpro tab
- gudang lagu
- guitar about
- guitar chords/scales
- guitarists
- hot frets
- html-kit-favicon
- indo mp3
- indonesia mp3
- indrakila band
- inilah indie
- isnaini blogger templates
- lumajang music
- mozilla themes
- mozilla themes
- mp3 indonesia
- musician
- musisi
- nolkoma band
- pax
- pp. daarul rahman jakarta
- rubby band
- sekolah rakyat indonesia
- smart telecom
- speed test
- speed test smart
- stafa band
- tab crawler
- tagihan pln jatim
- translator online (babelfish)
- translator online (toggle text)
- universitas terbuka
- warung mp3
- warung musik
- web2 feel
- youtube
kidz music community, desakuArt production, crew forsil songolas, sahabat forsil songolas, sekolah rakyat merdeka, perguruan rakyat merdeka, sekretariat anak merdeka indonesia, sanggar alif kaligrafi, sanggar mata air, exsongolas management, ponpes daarul rahman jakarta, ponpes an-nuqayah sumenep, boom cell cellulare, tunas trans solusindo, semeru scooter club '06 klakah, komunitas indie lumajang, solidaritas buruh migran indonesia - jawa timur, peduli buruh migran, prakarsa rakyat, bulletin sadar, praxis, dll.
(mohon maaf jika ada yang belum disebutkan)
terima kasih atas kunjungan anda, kritik saran yang membangun adalah kunci keberhasilan kami.
deditsabit@smara
thanks for the template design to skinCorner | grunged girl image from dapinoGraphics



