main |
sidebar

supported by deditsabit
supported by deditsabit
Jumlah Posting & Komentar:
buah artikel telah ditulis
buah komentar masuk


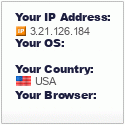



supported by deditsabit
Tingginya bencana alam gempa bumi di Indonesia tidak terlepas dari kondisi geografis negara Indonesia yang berada di atas empat lempeng bumi yaitu: Indo Australia, Pasifik, Eurasia, dan Filipina. Hampir seluruh bencana alam yang ada di Indonesia ditimbulkan dari lempeng ini. Posisi geografis yang demikian menyebabkan Indonesia sebagai negara yang rawan dengan bencana, bahkan melebihi Jepang yang berada di atas tiga lempeng. Tak pelak Indonesia kerap dijuluki sebagai “supermarket” bencana.
Julukan itu semakin tepat dengan timbulnya berbagai bencana alam di Indonesia bahkan dalam skala besar secara beruntun dalam beberapa tahun belakangan. Mulai dari bencana tsunami di Aceh di akhir tahun 2004 sampai dengan bencana gempa berkekuatan 7,6 SR yang mengguncang Sumatera Barat merembet, mendera Jambi sehari berikutnya.
Kondisi geografis negeri ini yang sangat rawan bencana sebetulnya telah menjadi kesadaran umum terutama sejak bencana Tsunami Aceh. Hampir seluruh elemen melakukan upaya-upaya menyikapi keadaan tersebut, baik dengan melakukan kajian-kajian, melakukan pelatihan-pelatihan kebencanaan termasuk melakukan upaya-upaya penanggulangan bencana oleh pemerintah maupun berbasis komunitas. Walhasil, berbagai pelatihan di pelosok negeri termasuk simulasi dalam menghadapi bencana dilakukan, terutama di daerah-daerah yang dianggap paling rawan dengan bencana gempa-tsunami, salah satunya yang paling sering adalah Provinsi Sumatera Barat. Pelatihan kesiapsiagaan bencana ini dilanjutkan sampai pada tahap membangun kesiapsiagaan komunitas dengan membangun disaster alert system yang berbasis budaya lokal. Lalu bermunculan berbagai hasil kajian mengenai kerawanan bencana termasuk buku-buku penanganan bencana untuk pengurangan resiko bencana.
Berkiblat kepada kurangnya manajemen penanganan bencana terutama penanganan kondisi darurat pada waktu bencana Tsunami Aceh, pemerintah terlihat serius menata managemen penanganan bencana, bahkan saking seriusnya pada tahun 2007 pemerintah mengeluarkan regulasi yaitu UU no 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Suatu tindakan yang patut diapresiasi terlebih hal tersebut dilatabelakangi oleh kesadaran pemerintah bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional (lihat konsideran UU tersebut).
Tentu saja keadaan tersebut sangat mengembirakan, minimal sebagai pertanda bahwa aparatur di negeri ini serius menyiapkan diri dalam menanggulangi dan menangani bencana untuk mengurangi resiko bencana. Artinya aparat di negeri ini serius belajar dari kesalahan dan ketidakcakapan menangani bencana yang selama ini terjadi baik Tsunami Aceh, gempa di Jogjakarta, dimana hal yang selalu terjadi dan sama adalah kelambanan pemerintah melakukan tindakan penanganan bencana termasuk tindakan penanganan darurat.
Hanya saja kegembiraan itu ternyata berlaku sesaat, kesalahan yang sama dalam penanganan bencana terulang lagi. Setelah sekian kali menangani bencana alam dalam skala kerusakan yang cukup besar, ternyata pemerintah tidak mampu beranjak lebih maju dalam penanggulangan bencana. Dalam penanganan gempa di Sumbar khusunya dalam penanganan darurat, muncul permasalahan yang tidak jauh beda dengan penanganan bencana alam sebelumnya. Permasalahan yang paling mencolok dan selalu terjadi adalah masalah pengelolaan bantuan utamanya mengenai pendistribusian bantuan. Yang paling sering terjadi adalah korban yang tidak kunjung mendapatkan bantuan sementara bantuan menumpuk di posko bencana.
Fakta ini dapat dicermati dari beragam testimoni korban di media massa yang mengungkapkan, betapa lambatnya pendistribusian bantuan tersebut. Mereka menyatakan tidak mendapatkan bantuan makanan, minuman dan perlengkapan mengungsi yang optimal. Walhasil, terjadi tindakan penjarahan sebagai bentuk “protes” atas kelambanan distribusi bantuan. Tanpa menafikan kerja-kerja penanganan darurat bencana yang dijalankan, dapat dipastikan bahwa “kericuhan” tersebut berasal dari buruknya manajeman penanganan bencana. Dalam penanganan darurat ini terkesan sangat tidak sistematis. Akibatnya adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar dari korban bencana.
Bahkan yang sangat menyesakkan, lambannya pendistribusian ini ternyata disebabkan oleh birokrasi yang dibuat dalam sistem pendistribusiannya. Ketakutan tidak tepatnya pemberian bantuan tersebut menjadi latar belakang adanya birokrasi yang dalam pengambilan bantuan di posko logistik. Sekilas alasan itu sangat logis. Namun bila dikaitan dengan kondisi yang ada, alasan itu menjadi tidak tepat. Ketepatan sasaran dari pendistribusian bantuan ini adalah keniscayaan. Tetapi untuk menjamin kepentingan tersebut, sepatutnya tidak dilakukan dengan pola membangun birokrasi dadakan. Dalam situasi darurat, tentu saja birokrasi dadakan ini akan menambah kacau situasi. Hasil akhirnya toh birokrasi tersebut menghasilkan bantuan yang membusuk di posko-posko logistik, sementara korban gempa tetap harus menerima nasib kekurangan kebutuhan dasar mereka.
Keadan ini tentu saja tidak akan terjadi bila pemerintah secara serius menyiapkan diri untuk menangani bencana. Dengan menyadari bahwa Indonesia rawan bencana seharusnya tidak cukup dengan membuat Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana namun gagap dalam implementasinya. Pemerintah seyogyanya melakukan tindakan-tindakan yang lebih maju dalam penanganan bencana.
Untuk itu perlu adanya perencanaan kontijensi yaitu suatu proses perencanaan ke depan dalam keadaan ketidakpastian dimana skenario dan tujuan disepakati, tindakan manajerial dan teknis sudah ditentukan, dan rancangan sistem tanggapan sudah diatur pelaksanaannya, guna mencegah dan menanggapi keadaan darurat. Perencanaan ini setidaknya dapat menyiapkan sebuah rencana respon yang cepat dan tepat dalam situasi darurat bencana, sehingga tidak lagi terjadi kebingungan dan kekacauan serta kebijakan-kebijakan yang dibuat mendadak. Alih-alih meringankan korban, yang ada korban bencana tetap menderita dan bantuan logistik membusuk di posko-posko logistik. Parahnya, kejadian ini terjadi secara berulang dalam setiap penanganan bencana. Kalau keledai saja tidak mau terjerumus ke dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya, lalu haruskah bangsa ini selalu berkutat dengan kesalahan yang sama dalam penanganan bencana?
* Penulis adalah Majelis Anggota PBHI Bali, sekaligus anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Bali.
** Siapa saja dipersilahkan mengutip, menggandakan, menyebarluaskan sebagian atau seluruh materi yang termuat dalam portal ini selama untuk kajian dan mendukung gerakan rakyat. Untuk keperluan komersial pengguna harus mendapatkan ijin tertulis dari pengelola portal Prakarsa Rakyat. Setiap pengutipan, penggandaan dan penyebarluasan sebagian atau seluruh materi harus mencantumkan sumber (portal Prakarsa Rakyat atau www.prakarsa-rakyat.org).
supported by deditsabit
deditsabit bekerjasama dengan dan atas dukungan:
kidz music community, desakuArt production, crew forsil songolas, sahabat forsil songolas, sekolah rakyat merdeka, perguruan rakyat merdeka, sekretariat anak merdeka indonesia, sanggar alif kaligrafi, sanggar mata air, exsongolas management, ponpes daarul rahman jakarta, ponpes an-nuqayah sumenep, boom cell cellulare, tunas trans solusindo, semeru scooter club '06 klakah, komunitas indie lumajang, solidaritas buruh migran indonesia - jawa timur, peduli buruh migran, prakarsa rakyat, bulletin sadar, praxis, dll.
(mohon maaf jika ada yang belum disebutkan)
terima kasih atas kunjungan anda, kritik saran yang membangun adalah kunci keberhasilan kami.
deditsabit@smara

supported by deditsabit
play musik gue
blogroll gue
menurut label
- adsense (1)
- advokasi (2)
- anak (8)
- artikel (11)
- bakat (1)
- bisnis (2)
- budaya (3)
- bulletin sadar (198)
- buruh (1)
- buruh migran (10)
- cdma (1)
- cellulare (4)
- cerita gambar (2)
- deditsabit (4)
- elektronik (2)
- energi (1)
- event (5)
- facebook (4)
- gsm (1)
- ham (1)
- hukum (2)
- informatika (6)
- internet (4)
- jejaring (2)
- kartun (1)
- kdrt (1)
- kesehatan (4)
- kesenian (1)
- keyakinan (8)
- komputer (3)
- konservasi (1)
- korupsi (2)
- lingkungan (2)
- lomba (1)
- lumajang (1)
- maulid hijau (1)
- movie review (19)
- muhammad saw. (1)
- musik (14)
- nuklir (1)
- olah raga (4)
- pendidikan (7)
- perda (1)
- perempuan (9)
- Perguruan Rakyat Merdeka (56)
- peristiwa (7)
- politik (70)
- prestasi (1)
- produk (1)
- qur'an (1)
- radiasi (1)
- religi (9)
- remaja (9)
- resensi buku (27)
- rohani (3)
- sejarah (4)
- serial number (1)
- siswa (1)
- software (1)
- sosial (3)
- ssc '06 klakah (2)
- teknologi (3)
- tv kabel (2)
- undang-undang (1)
- undangan (3)
- video (2)
- website (1)
- wisata (1)
ngikut gak ni...?
statistik blog:
buah artikel telah ditulis
buah komentar masuk

supported by deditsabit
Oleh I Wayan “Gendo” Suardana*
Tingginya bencana alam gempa bumi di Indonesia tidak terlepas dari kondisi geografis negara Indonesia yang berada di atas empat lempeng bumi yaitu: Indo Australia, Pasifik, Eurasia, dan Filipina. Hampir seluruh bencana alam yang ada di Indonesia ditimbulkan dari lempeng ini. Posisi geografis yang demikian menyebabkan Indonesia sebagai negara yang rawan dengan bencana, bahkan melebihi Jepang yang berada di atas tiga lempeng. Tak pelak Indonesia kerap dijuluki sebagai “supermarket” bencana.
Julukan itu semakin tepat dengan timbulnya berbagai bencana alam di Indonesia bahkan dalam skala besar secara beruntun dalam beberapa tahun belakangan. Mulai dari bencana tsunami di Aceh di akhir tahun 2004 sampai dengan bencana gempa berkekuatan 7,6 SR yang mengguncang Sumatera Barat merembet, mendera Jambi sehari berikutnya.
Kondisi geografis negeri ini yang sangat rawan bencana sebetulnya telah menjadi kesadaran umum terutama sejak bencana Tsunami Aceh. Hampir seluruh elemen melakukan upaya-upaya menyikapi keadaan tersebut, baik dengan melakukan kajian-kajian, melakukan pelatihan-pelatihan kebencanaan termasuk melakukan upaya-upaya penanggulangan bencana oleh pemerintah maupun berbasis komunitas. Walhasil, berbagai pelatihan di pelosok negeri termasuk simulasi dalam menghadapi bencana dilakukan, terutama di daerah-daerah yang dianggap paling rawan dengan bencana gempa-tsunami, salah satunya yang paling sering adalah Provinsi Sumatera Barat. Pelatihan kesiapsiagaan bencana ini dilanjutkan sampai pada tahap membangun kesiapsiagaan komunitas dengan membangun disaster alert system yang berbasis budaya lokal. Lalu bermunculan berbagai hasil kajian mengenai kerawanan bencana termasuk buku-buku penanganan bencana untuk pengurangan resiko bencana.
Berkiblat kepada kurangnya manajemen penanganan bencana terutama penanganan kondisi darurat pada waktu bencana Tsunami Aceh, pemerintah terlihat serius menata managemen penanganan bencana, bahkan saking seriusnya pada tahun 2007 pemerintah mengeluarkan regulasi yaitu UU no 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Suatu tindakan yang patut diapresiasi terlebih hal tersebut dilatabelakangi oleh kesadaran pemerintah bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional (lihat konsideran UU tersebut).
Tentu saja keadaan tersebut sangat mengembirakan, minimal sebagai pertanda bahwa aparatur di negeri ini serius menyiapkan diri dalam menanggulangi dan menangani bencana untuk mengurangi resiko bencana. Artinya aparat di negeri ini serius belajar dari kesalahan dan ketidakcakapan menangani bencana yang selama ini terjadi baik Tsunami Aceh, gempa di Jogjakarta, dimana hal yang selalu terjadi dan sama adalah kelambanan pemerintah melakukan tindakan penanganan bencana termasuk tindakan penanganan darurat.
Hanya saja kegembiraan itu ternyata berlaku sesaat, kesalahan yang sama dalam penanganan bencana terulang lagi. Setelah sekian kali menangani bencana alam dalam skala kerusakan yang cukup besar, ternyata pemerintah tidak mampu beranjak lebih maju dalam penanggulangan bencana. Dalam penanganan gempa di Sumbar khusunya dalam penanganan darurat, muncul permasalahan yang tidak jauh beda dengan penanganan bencana alam sebelumnya. Permasalahan yang paling mencolok dan selalu terjadi adalah masalah pengelolaan bantuan utamanya mengenai pendistribusian bantuan. Yang paling sering terjadi adalah korban yang tidak kunjung mendapatkan bantuan sementara bantuan menumpuk di posko bencana.
Fakta ini dapat dicermati dari beragam testimoni korban di media massa yang mengungkapkan, betapa lambatnya pendistribusian bantuan tersebut. Mereka menyatakan tidak mendapatkan bantuan makanan, minuman dan perlengkapan mengungsi yang optimal. Walhasil, terjadi tindakan penjarahan sebagai bentuk “protes” atas kelambanan distribusi bantuan. Tanpa menafikan kerja-kerja penanganan darurat bencana yang dijalankan, dapat dipastikan bahwa “kericuhan” tersebut berasal dari buruknya manajeman penanganan bencana. Dalam penanganan darurat ini terkesan sangat tidak sistematis. Akibatnya adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar dari korban bencana.
Bahkan yang sangat menyesakkan, lambannya pendistribusian ini ternyata disebabkan oleh birokrasi yang dibuat dalam sistem pendistribusiannya. Ketakutan tidak tepatnya pemberian bantuan tersebut menjadi latar belakang adanya birokrasi yang dalam pengambilan bantuan di posko logistik. Sekilas alasan itu sangat logis. Namun bila dikaitan dengan kondisi yang ada, alasan itu menjadi tidak tepat. Ketepatan sasaran dari pendistribusian bantuan ini adalah keniscayaan. Tetapi untuk menjamin kepentingan tersebut, sepatutnya tidak dilakukan dengan pola membangun birokrasi dadakan. Dalam situasi darurat, tentu saja birokrasi dadakan ini akan menambah kacau situasi. Hasil akhirnya toh birokrasi tersebut menghasilkan bantuan yang membusuk di posko-posko logistik, sementara korban gempa tetap harus menerima nasib kekurangan kebutuhan dasar mereka.
Keadan ini tentu saja tidak akan terjadi bila pemerintah secara serius menyiapkan diri untuk menangani bencana. Dengan menyadari bahwa Indonesia rawan bencana seharusnya tidak cukup dengan membuat Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana namun gagap dalam implementasinya. Pemerintah seyogyanya melakukan tindakan-tindakan yang lebih maju dalam penanganan bencana.
Untuk itu perlu adanya perencanaan kontijensi yaitu suatu proses perencanaan ke depan dalam keadaan ketidakpastian dimana skenario dan tujuan disepakati, tindakan manajerial dan teknis sudah ditentukan, dan rancangan sistem tanggapan sudah diatur pelaksanaannya, guna mencegah dan menanggapi keadaan darurat. Perencanaan ini setidaknya dapat menyiapkan sebuah rencana respon yang cepat dan tepat dalam situasi darurat bencana, sehingga tidak lagi terjadi kebingungan dan kekacauan serta kebijakan-kebijakan yang dibuat mendadak. Alih-alih meringankan korban, yang ada korban bencana tetap menderita dan bantuan logistik membusuk di posko-posko logistik. Parahnya, kejadian ini terjadi secara berulang dalam setiap penanganan bencana. Kalau keledai saja tidak mau terjerumus ke dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya, lalu haruskah bangsa ini selalu berkutat dengan kesalahan yang sama dalam penanganan bencana?
* Penulis adalah Majelis Anggota PBHI Bali, sekaligus anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Bali.
** Siapa saja dipersilahkan mengutip, menggandakan, menyebarluaskan sebagian atau seluruh materi yang termuat dalam portal ini selama untuk kajian dan mendukung gerakan rakyat. Untuk keperluan komersial pengguna harus mendapatkan ijin tertulis dari pengelola portal Prakarsa Rakyat. Setiap pengutipan, penggandaan dan penyebarluasan sebagian atau seluruh materi harus mencantumkan sumber (portal Prakarsa Rakyat atau www.prakarsa-rakyat.org).
Labels: bulletin sadar
0 Comments:
d-i-s-c-l-a-i-m-e-r
games tools
- agent waste
- asstroidz
- billyard
- binatang kembar
- blok 2
- bounce
- bullet snale 3
- cavern klamrisk
- chicken invaders roty
- dynomite deluxe
- feeding frenzy 2
- freeciv 2.1.9
- hell chess
- insaniquarium
- luxor
- monopoly
- moto
- pandaland
- picross mania
- pizza frenzy
- sponge bob collapse
- standing point the final stronghold
- the power
- zuma deluxe
temen gue
- adsense for feeds
- anang's blog
- angkatan sembilan belas
- babu ngeblog
- blog oranje
- blogger templates bycaz
- btemplates
- catatan dunia ira
- daleclick templates
- densu-nod
- desakuArt production
- dua mata
- facebook sunnah
- foto tanpa genre
- free blogger template layout
- free musicz mp3
- free templates
- hujan musik indonesia
- imam marsus
- indo bloger
- indo lawas
- indo metal box
- islam substantif
- karim samman
- kidz music community
- klasik rock indonesia
- lumajang music community
- media putra
- mr. ozay's blog
- music 4 sharing
- nona cantiq
- peduli buruh migran
- pers bebas, pintu demokrasi
- rindu pulang
- sanggar alif kaligrafi
- sanggar mata air
- soft 4 u
- template unik
- tunas trans solusindo
- tutorial jitu
- uc1n blog's
- underground indonesia
- unduh musik
- upex rock
- wonogiri voucher
bookmarks gue
- angel fire
- anymaking
- blog lines
- blog template 4u
- blogspot template
- blogspot templetes
- cbm card
- club brillian (id: cgd935029)
- currency converter
- cyber fret
- dhanny dhuzell site's
- dynamic tools drive
- editing foto online
- ez wp themes
- free templates online
- free warebb
- gpro tab
- gudang lagu
- guitar about
- guitar chords/scales
- guitarists
- hot frets
- html-kit-favicon
- indo mp3
- indonesia mp3
- indrakila band
- inilah indie
- isnaini blogger templates
- lumajang music
- mozilla themes
- mozilla themes
- mp3 indonesia
- musician
- musisi
- nolkoma band
- pax
- pp. daarul rahman jakarta
- rubby band
- sekolah rakyat indonesia
- smart telecom
- speed test
- speed test smart
- stafa band
- tab crawler
- tagihan pln jatim
- translator online (babelfish)
- translator online (toggle text)
- universitas terbuka
- warung mp3
- warung musik
- web2 feel
- youtube
kidz music community, desakuArt production, crew forsil songolas, sahabat forsil songolas, sekolah rakyat merdeka, perguruan rakyat merdeka, sekretariat anak merdeka indonesia, sanggar alif kaligrafi, sanggar mata air, exsongolas management, ponpes daarul rahman jakarta, ponpes an-nuqayah sumenep, boom cell cellulare, tunas trans solusindo, semeru scooter club '06 klakah, komunitas indie lumajang, solidaritas buruh migran indonesia - jawa timur, peduli buruh migran, prakarsa rakyat, bulletin sadar, praxis, dll.
(mohon maaf jika ada yang belum disebutkan)
terima kasih atas kunjungan anda, kritik saran yang membangun adalah kunci keberhasilan kami.
deditsabit@smara
thanks for the template design to skinCorner | grunged girl image from dapinoGraphics



