main |
sidebar

supported by deditsabit
supported by deditsabit
Jumlah Posting & Komentar:
buah artikel telah ditulis
buah komentar masuk


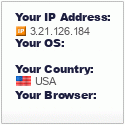



supported by deditsabit
“...Pengadilan Negeri Tangerang menyidangkan 10 orang anak. Mereka dijerat dengan pasal 303 KUHP tentang perjudian. Mereka ditangkap Polisi karena bermain macan buram (permainan lempar koin). Akibat dari permainan tebak-tebakan itu dengan taruhan uang Rp. 1000, 10 anak usia 12-16 tahun tersebut menjadi tahanan polisi karena disangka berjudi...”
Penggalan berita yang marak diberitakan di media cetak dan bahkan elektronik itu, menjadi berita menyedihkan sekaligus menjadi kado pahit bagi anak-anak Indonesia yang pada tanggal 23 Juli lalu merayakan Hari Anak Indonesia (HAI). Sebuah peringatan yang sejatinya didedikasikan untuk memacu keceriaan anak-anak Indonesia, mendorong kemandirian dan tentu saja dorongan motivasi bagi anak-anak Indonesia bahwa eksistensi dirinya “dianggap” ada oleh negara. Meski, dalam keseharian, kita melihat fakta yang sebenarnya dan penangkapan, penyidangan serta penahanan anak-anak sebagaimana dilansir media itu membuktikan yang sebaliknya, bukan saja pada jaman gelap gulita bernama Orde Baru, namun hingga kini ketika Indonesia mampu menyelenggarakan pemilu yang (katanya) langsung, jujur dan adil.
Kesepuluh anak tersebut, sudah hampir sebulan dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang. Selama itu pula mereka terpisah dari orang tuanya dan mereka kehilangan hak untuk belajar di sekolah. Orang tua mereka sangat khawatir terhadap kelanjutan dari kasus ini. Terlebih lagi mereka buta hukum. Yang ada dalam pikiran mereka adalah bagaimana cara untuk mencari uang jika anak-anak mereka sampai di penjara. Untuk mengikuti proses persidangan ini pun tidak cukup dengan uang sedikit. Bahkan ada orang tua terdakwa yang sudah berhutang sampai Rp. 1 juta sejak anaknya ditangkap polisi. Sebuah potret lazim yang terjadi di masyarakat awam Indonesia. Berhadapan dengan hukum yang berisi ketidakpastian, kemudian diperas oleh oknum dan tetap saja nasibnya terombang-ambing oleh ketidakpastian hukum yang bagai pisau dapur, tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Sialnya mereka, sepuluh anak-anak tak berdosa itu beserta keluarganya berada dalam posisi di bawah irisan pisau hukum yang bagi mereka berlaku amat tajam.
Anak-Anak Indonesia, Potret Buram Kita
Kesepuluh anak itu, pada dasarnya menggambarkan sebuah potret yang buram, dan meski buram kita harus mengakuinya bahwa itulah wajah kita saat ini. Sebuah potret yang abai terhadap nasib anak-anak, tunas bagi masa depan negeri ini dan konon simpul utama lahirnya sebuah generasi tangguh ke depan justru terancam menjadi pembenaran akan hilang satu generasi. Simak saja, keseharian anak-anak itu: selain bersekolah (yang dapat dipastikan sekolah dengan kualitas kurang baik, bukan unggulan, mutu pelajaran seadanya kalau tidak boleh dikatakan sangat buruk), anak-anak ini pun (memiliki pekerjaan utama) mencari nafkah tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Kenapa pekerjaan utama? Tentu saja karena jam kerja yang pasti jauh lebih panjang dari jam sekolah di lingkungan yang tidak bersahabat dan tentu saja sebuah aktvitas yang sebenarnya tidak dipebolehkan untuk mereka. Mereka bekerja sebagai penyemir sepatu di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Orang tua mereka bekerja sebagai buruh tani, buruh pencuci plastik, buruh bagunan, dan penarik becak.
Gambaran di atas memberikan sebuah potret yang benar-benar buram bagi kita, anak-anak sekolah dengan kualitas buruk, eksploitasi anak-anak terbuka, orang tua dengan pekerjaan tak pasti serta keterpaksaan mereka berhadap-hadapan dengan pisau hukum yang sisi tajamnya menghadap tepat di hadapan mereka. Benar-benar sebuah pemandangan mengenaskan dan kita harus meyakini, bahwa masyarakat model seperti ini, adalah masyarakat yang akan mendapatkan giliran memotong kue pembangunan paling akhir bikinan presiden pemenang pemilu 2009. Tapi, mereka adalah model masyarakat yang paling banyak fotonya di media-media sebagai bagian masyarakat yang paling sering dikunjungi pasangan capres-cawapres ketika berkampanye.
Sebagai sedikit gambaran, bolehlah kita buka sedikit rekaman “gugatan” masyarakat terhadap kinerja para capres-cawapres dalam kampanye tempo hari. Pendidikan, bukankah ini bidang yang paling banyak digugat karena minimnya komitmen negara untuk merealisasikan dana APBN 20 % secara utuh sesuai amanat konstitusi? Ditambah ujian nasional yang tidak berperspektif memajukan selain menjadikan siswa sebagai robot yang dipaksa menelurkan angka-angka di ijazah? Gedung sekolah dengan kualitas buruk? Bangku-bangku yang dapat diambil lagi oleh toko meubel karena ternyata uangnya masih “disimpan” pak bupati? Dan seribu catatan lain. Kemudian eksploitasi anak, ketiadaan jaminan kerja bagi masyarakat, ketidakpastian hukum. Semua tentu akan berjajar panjang melebihi nalar sehat kita dalam bingkai potret buruk saja. Dan hari ini, anak Indonesia adalah korban yang bisa dikatakan paling rentan akan hal itu.
Keadilan adalah Kunci Hukum
Dalam kacamata hukum positif, kita pasti bersepakat bahwa tindakan judi, apapun bentuknya apalagi dilakukan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, tentu tidak dapat dibenarkan dan harus ditindak tegas. Namun, kita juga harus berani mengatakan bahwa hukum, setidaknya dibuat untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Rasa keadilan itu sebagai kunci utamanya. Anak-anak yang mendapat pendidikan dari sekolah dengan kualitas buruk, kondisi gedung rusak, harus bekerja karena orangtuanya tidak mendapatkan jaminan kepastian kerja (bahkan bisa jadi korban PHK atau penggusuran) tentu saja harus diposisikan sebagai warga negara yang sudah diperlakukan secara sangat tidak adil oleh negara. Betapa tidak derajat, harkat dan martabat mereka sesuai amanat UUD 1945, sesuai amanat para pendiri republik ini harusnya ditinggikan. Dipelihara, diasuh dan dilindungi. Jadi kelalaian negara menelantarkan mereka jauh lebih besar dan fatal dibandingkan dengan aktivitas mereka yang sekedar bermain-main di bandara. Di sini, letak kesalahan fatalnya terjadi.
Walaupun terdakwa diadili dengan peradilan anak, tetap saja akan meninggalkan dampak psikologis yang kurang baik, terlebih mereka sudah tidak bisa sekolah lantaran harus berada di LP Anak Pria Tangerang. Berbeda dengan anak-anak seusia mereka yang seharusnya tanggal 13 Juli lalu adalah hari pertama masuk sekolah justru mereka memasuki tahap persidangan yang harus mereka jalani. Bukan sebuah rasa suka cita yang mereka gapai tapi sebuah kesedihan yang tidak hanya menimpa anak-anak tapi juga orang tua mereka.
Negara tidak melihat faktor psikologis dan lingkungan yang jauh lebih penting bagi perkembangan anak ke depan dari pada menghukumnya. Terlebih label bekas narapidana akan mereka sandang seumur hidup mereka. Kasus ini tidak perlu disidangkan, cukup dengan memanggil kedua orang tuanya untuk menyelesaikan masalah ini. Karena mereka masih anak-anak dan mempunyai hak untuk belajar, maka mereka perlu dibina bukan malah justru sebaliknya dibinasakan masa depannya. Jika mereka dipenjara, maka anak-anak akan tidak bisa bersekolah, mencari nafkah tambahan untuk biaya hidup pun tidak bisa mereka lakukan lagi. Kita bisa melihat di media massa ataupun elektronik, 10 orang anak tersebut harus menggunakan topeng, dan tampak kesedihan yang terlihat dari wajah ibu dari anak-anak tersebut.
Sungguh, sebuah kejadian yang ironis. Sebuah potret yang benar-benar buram dan paradoks. Benar bahwa kejadian ini “hanya” menimpa 10 orang anak di Tangerang. Namun, semua itu hanya permukaan gunung es yang di dalamnya terkandung gelegak magma akan kondisi masyarakat kita yang miskin, hidup tanpa jaminan kelayakan dari negara, tergusur oleh Satpol PP, hukum yang tidak berperspektif keadilan. Dan sialnya, kondisi masyarakat yang demikian itu adalah gambaran mayoritas rakyat Indonesia. Meski tentu saja survey BPS tidak memasukkannya dalam kategori penduduk miskin.
Dirgahayu Anak Indonesia, meski tak sempat nikmati waktu. Dipaksa pecahkan karang, lemah jarimu terkepal!
* Penulis saat ini sedang menempuh studi di Universitas Negeri Jakarta, sekaligus Anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Jabodetabek.
** Siapa saja dipersilahkan mengutip, menggandakan, menyebarluaskan sebagian atau seluruh materi yang termuat dalam portal ini selama untuk kajian dan mendukung gerakan rakyat. Untuk keperluan komersial pengguna harus mendapatkan ijin tertulis dari pengelola portal Prakarsa Rakyat. Setiap pengutipan, penggandaan dan penyebarluasan sebagian atau seluruh materi harus mencantumkan sumber (portal Prakarsa Rakyat atau www.prakarsa-rakyat.org).
supported by deditsabit
deditsabit bekerjasama dengan dan atas dukungan:
kidz music community, desakuArt production, crew forsil songolas, sahabat forsil songolas, sekolah rakyat merdeka, perguruan rakyat merdeka, sekretariat anak merdeka indonesia, sanggar alif kaligrafi, sanggar mata air, exsongolas management, ponpes daarul rahman jakarta, ponpes an-nuqayah sumenep, boom cell cellulare, tunas trans solusindo, semeru scooter club '06 klakah, komunitas indie lumajang, solidaritas buruh migran indonesia - jawa timur, peduli buruh migran, prakarsa rakyat, bulletin sadar, praxis, dll.
(mohon maaf jika ada yang belum disebutkan)
terima kasih atas kunjungan anda, kritik saran yang membangun adalah kunci keberhasilan kami.
deditsabit@smara

supported by deditsabit
play musik gue
blogroll gue
menurut label
- adsense (1)
- advokasi (2)
- anak (8)
- artikel (11)
- bakat (1)
- bisnis (2)
- budaya (3)
- bulletin sadar (198)
- buruh (1)
- buruh migran (10)
- cdma (1)
- cellulare (4)
- cerita gambar (2)
- deditsabit (4)
- elektronik (2)
- energi (1)
- event (5)
- facebook (4)
- gsm (1)
- ham (1)
- hukum (2)
- informatika (6)
- internet (4)
- jejaring (2)
- kartun (1)
- kdrt (1)
- kesehatan (4)
- kesenian (1)
- keyakinan (8)
- komputer (3)
- konservasi (1)
- korupsi (2)
- lingkungan (2)
- lomba (1)
- lumajang (1)
- maulid hijau (1)
- movie review (19)
- muhammad saw. (1)
- musik (14)
- nuklir (1)
- olah raga (4)
- pendidikan (7)
- perda (1)
- perempuan (9)
- Perguruan Rakyat Merdeka (56)
- peristiwa (7)
- politik (70)
- prestasi (1)
- produk (1)
- qur'an (1)
- radiasi (1)
- religi (9)
- remaja (9)
- resensi buku (27)
- rohani (3)
- sejarah (4)
- serial number (1)
- siswa (1)
- software (1)
- sosial (3)
- ssc '06 klakah (2)
- teknologi (3)
- tv kabel (2)
- undang-undang (1)
- undangan (3)
- video (2)
- website (1)
- wisata (1)
ngikut gak ni...?
statistik blog:
buah artikel telah ditulis
buah komentar masuk

supported by deditsabit
Oleh Ade Fawziah *
“...Pengadilan Negeri Tangerang menyidangkan 10 orang anak. Mereka dijerat dengan pasal 303 KUHP tentang perjudian. Mereka ditangkap Polisi karena bermain macan buram (permainan lempar koin). Akibat dari permainan tebak-tebakan itu dengan taruhan uang Rp. 1000, 10 anak usia 12-16 tahun tersebut menjadi tahanan polisi karena disangka berjudi...”
Penggalan berita yang marak diberitakan di media cetak dan bahkan elektronik itu, menjadi berita menyedihkan sekaligus menjadi kado pahit bagi anak-anak Indonesia yang pada tanggal 23 Juli lalu merayakan Hari Anak Indonesia (HAI). Sebuah peringatan yang sejatinya didedikasikan untuk memacu keceriaan anak-anak Indonesia, mendorong kemandirian dan tentu saja dorongan motivasi bagi anak-anak Indonesia bahwa eksistensi dirinya “dianggap” ada oleh negara. Meski, dalam keseharian, kita melihat fakta yang sebenarnya dan penangkapan, penyidangan serta penahanan anak-anak sebagaimana dilansir media itu membuktikan yang sebaliknya, bukan saja pada jaman gelap gulita bernama Orde Baru, namun hingga kini ketika Indonesia mampu menyelenggarakan pemilu yang (katanya) langsung, jujur dan adil.
Kesepuluh anak tersebut, sudah hampir sebulan dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang. Selama itu pula mereka terpisah dari orang tuanya dan mereka kehilangan hak untuk belajar di sekolah. Orang tua mereka sangat khawatir terhadap kelanjutan dari kasus ini. Terlebih lagi mereka buta hukum. Yang ada dalam pikiran mereka adalah bagaimana cara untuk mencari uang jika anak-anak mereka sampai di penjara. Untuk mengikuti proses persidangan ini pun tidak cukup dengan uang sedikit. Bahkan ada orang tua terdakwa yang sudah berhutang sampai Rp. 1 juta sejak anaknya ditangkap polisi. Sebuah potret lazim yang terjadi di masyarakat awam Indonesia. Berhadapan dengan hukum yang berisi ketidakpastian, kemudian diperas oleh oknum dan tetap saja nasibnya terombang-ambing oleh ketidakpastian hukum yang bagai pisau dapur, tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Sialnya mereka, sepuluh anak-anak tak berdosa itu beserta keluarganya berada dalam posisi di bawah irisan pisau hukum yang bagi mereka berlaku amat tajam.
Anak-Anak Indonesia, Potret Buram Kita
Kesepuluh anak itu, pada dasarnya menggambarkan sebuah potret yang buram, dan meski buram kita harus mengakuinya bahwa itulah wajah kita saat ini. Sebuah potret yang abai terhadap nasib anak-anak, tunas bagi masa depan negeri ini dan konon simpul utama lahirnya sebuah generasi tangguh ke depan justru terancam menjadi pembenaran akan hilang satu generasi. Simak saja, keseharian anak-anak itu: selain bersekolah (yang dapat dipastikan sekolah dengan kualitas kurang baik, bukan unggulan, mutu pelajaran seadanya kalau tidak boleh dikatakan sangat buruk), anak-anak ini pun (memiliki pekerjaan utama) mencari nafkah tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Kenapa pekerjaan utama? Tentu saja karena jam kerja yang pasti jauh lebih panjang dari jam sekolah di lingkungan yang tidak bersahabat dan tentu saja sebuah aktvitas yang sebenarnya tidak dipebolehkan untuk mereka. Mereka bekerja sebagai penyemir sepatu di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Orang tua mereka bekerja sebagai buruh tani, buruh pencuci plastik, buruh bagunan, dan penarik becak.
Gambaran di atas memberikan sebuah potret yang benar-benar buram bagi kita, anak-anak sekolah dengan kualitas buruk, eksploitasi anak-anak terbuka, orang tua dengan pekerjaan tak pasti serta keterpaksaan mereka berhadap-hadapan dengan pisau hukum yang sisi tajamnya menghadap tepat di hadapan mereka. Benar-benar sebuah pemandangan mengenaskan dan kita harus meyakini, bahwa masyarakat model seperti ini, adalah masyarakat yang akan mendapatkan giliran memotong kue pembangunan paling akhir bikinan presiden pemenang pemilu 2009. Tapi, mereka adalah model masyarakat yang paling banyak fotonya di media-media sebagai bagian masyarakat yang paling sering dikunjungi pasangan capres-cawapres ketika berkampanye.
Sebagai sedikit gambaran, bolehlah kita buka sedikit rekaman “gugatan” masyarakat terhadap kinerja para capres-cawapres dalam kampanye tempo hari. Pendidikan, bukankah ini bidang yang paling banyak digugat karena minimnya komitmen negara untuk merealisasikan dana APBN 20 % secara utuh sesuai amanat konstitusi? Ditambah ujian nasional yang tidak berperspektif memajukan selain menjadikan siswa sebagai robot yang dipaksa menelurkan angka-angka di ijazah? Gedung sekolah dengan kualitas buruk? Bangku-bangku yang dapat diambil lagi oleh toko meubel karena ternyata uangnya masih “disimpan” pak bupati? Dan seribu catatan lain. Kemudian eksploitasi anak, ketiadaan jaminan kerja bagi masyarakat, ketidakpastian hukum. Semua tentu akan berjajar panjang melebihi nalar sehat kita dalam bingkai potret buruk saja. Dan hari ini, anak Indonesia adalah korban yang bisa dikatakan paling rentan akan hal itu.
Keadilan adalah Kunci Hukum
Dalam kacamata hukum positif, kita pasti bersepakat bahwa tindakan judi, apapun bentuknya apalagi dilakukan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, tentu tidak dapat dibenarkan dan harus ditindak tegas. Namun, kita juga harus berani mengatakan bahwa hukum, setidaknya dibuat untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Rasa keadilan itu sebagai kunci utamanya. Anak-anak yang mendapat pendidikan dari sekolah dengan kualitas buruk, kondisi gedung rusak, harus bekerja karena orangtuanya tidak mendapatkan jaminan kepastian kerja (bahkan bisa jadi korban PHK atau penggusuran) tentu saja harus diposisikan sebagai warga negara yang sudah diperlakukan secara sangat tidak adil oleh negara. Betapa tidak derajat, harkat dan martabat mereka sesuai amanat UUD 1945, sesuai amanat para pendiri republik ini harusnya ditinggikan. Dipelihara, diasuh dan dilindungi. Jadi kelalaian negara menelantarkan mereka jauh lebih besar dan fatal dibandingkan dengan aktivitas mereka yang sekedar bermain-main di bandara. Di sini, letak kesalahan fatalnya terjadi.
Walaupun terdakwa diadili dengan peradilan anak, tetap saja akan meninggalkan dampak psikologis yang kurang baik, terlebih mereka sudah tidak bisa sekolah lantaran harus berada di LP Anak Pria Tangerang. Berbeda dengan anak-anak seusia mereka yang seharusnya tanggal 13 Juli lalu adalah hari pertama masuk sekolah justru mereka memasuki tahap persidangan yang harus mereka jalani. Bukan sebuah rasa suka cita yang mereka gapai tapi sebuah kesedihan yang tidak hanya menimpa anak-anak tapi juga orang tua mereka.
Negara tidak melihat faktor psikologis dan lingkungan yang jauh lebih penting bagi perkembangan anak ke depan dari pada menghukumnya. Terlebih label bekas narapidana akan mereka sandang seumur hidup mereka. Kasus ini tidak perlu disidangkan, cukup dengan memanggil kedua orang tuanya untuk menyelesaikan masalah ini. Karena mereka masih anak-anak dan mempunyai hak untuk belajar, maka mereka perlu dibina bukan malah justru sebaliknya dibinasakan masa depannya. Jika mereka dipenjara, maka anak-anak akan tidak bisa bersekolah, mencari nafkah tambahan untuk biaya hidup pun tidak bisa mereka lakukan lagi. Kita bisa melihat di media massa ataupun elektronik, 10 orang anak tersebut harus menggunakan topeng, dan tampak kesedihan yang terlihat dari wajah ibu dari anak-anak tersebut.
Sungguh, sebuah kejadian yang ironis. Sebuah potret yang benar-benar buram dan paradoks. Benar bahwa kejadian ini “hanya” menimpa 10 orang anak di Tangerang. Namun, semua itu hanya permukaan gunung es yang di dalamnya terkandung gelegak magma akan kondisi masyarakat kita yang miskin, hidup tanpa jaminan kelayakan dari negara, tergusur oleh Satpol PP, hukum yang tidak berperspektif keadilan. Dan sialnya, kondisi masyarakat yang demikian itu adalah gambaran mayoritas rakyat Indonesia. Meski tentu saja survey BPS tidak memasukkannya dalam kategori penduduk miskin.
Dirgahayu Anak Indonesia, meski tak sempat nikmati waktu. Dipaksa pecahkan karang, lemah jarimu terkepal!
* Penulis saat ini sedang menempuh studi di Universitas Negeri Jakarta, sekaligus Anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Jabodetabek.
** Siapa saja dipersilahkan mengutip, menggandakan, menyebarluaskan sebagian atau seluruh materi yang termuat dalam portal ini selama untuk kajian dan mendukung gerakan rakyat. Untuk keperluan komersial pengguna harus mendapatkan ijin tertulis dari pengelola portal Prakarsa Rakyat. Setiap pengutipan, penggandaan dan penyebarluasan sebagian atau seluruh materi harus mencantumkan sumber (portal Prakarsa Rakyat atau www.prakarsa-rakyat.org).
Labels: bulletin sadar
0 Comments:
d-i-s-c-l-a-i-m-e-r
games tools
- agent waste
- asstroidz
- billyard
- binatang kembar
- blok 2
- bounce
- bullet snale 3
- cavern klamrisk
- chicken invaders roty
- dynomite deluxe
- feeding frenzy 2
- freeciv 2.1.9
- hell chess
- insaniquarium
- luxor
- monopoly
- moto
- pandaland
- picross mania
- pizza frenzy
- sponge bob collapse
- standing point the final stronghold
- the power
- zuma deluxe
temen gue
- adsense for feeds
- anang's blog
- angkatan sembilan belas
- babu ngeblog
- blog oranje
- blogger templates bycaz
- btemplates
- catatan dunia ira
- daleclick templates
- densu-nod
- desakuArt production
- dua mata
- facebook sunnah
- foto tanpa genre
- free blogger template layout
- free musicz mp3
- free templates
- hujan musik indonesia
- imam marsus
- indo bloger
- indo lawas
- indo metal box
- islam substantif
- karim samman
- kidz music community
- klasik rock indonesia
- lumajang music community
- media putra
- mr. ozay's blog
- music 4 sharing
- nona cantiq
- peduli buruh migran
- pers bebas, pintu demokrasi
- rindu pulang
- sanggar alif kaligrafi
- sanggar mata air
- soft 4 u
- template unik
- tunas trans solusindo
- tutorial jitu
- uc1n blog's
- underground indonesia
- unduh musik
- upex rock
- wonogiri voucher
bookmarks gue
- angel fire
- anymaking
- blog lines
- blog template 4u
- blogspot template
- blogspot templetes
- cbm card
- club brillian (id: cgd935029)
- currency converter
- cyber fret
- dhanny dhuzell site's
- dynamic tools drive
- editing foto online
- ez wp themes
- free templates online
- free warebb
- gpro tab
- gudang lagu
- guitar about
- guitar chords/scales
- guitarists
- hot frets
- html-kit-favicon
- indo mp3
- indonesia mp3
- indrakila band
- inilah indie
- isnaini blogger templates
- lumajang music
- mozilla themes
- mozilla themes
- mp3 indonesia
- musician
- musisi
- nolkoma band
- pax
- pp. daarul rahman jakarta
- rubby band
- sekolah rakyat indonesia
- smart telecom
- speed test
- speed test smart
- stafa band
- tab crawler
- tagihan pln jatim
- translator online (babelfish)
- translator online (toggle text)
- universitas terbuka
- warung mp3
- warung musik
- web2 feel
- youtube
kidz music community, desakuArt production, crew forsil songolas, sahabat forsil songolas, sekolah rakyat merdeka, perguruan rakyat merdeka, sekretariat anak merdeka indonesia, sanggar alif kaligrafi, sanggar mata air, exsongolas management, ponpes daarul rahman jakarta, ponpes an-nuqayah sumenep, boom cell cellulare, tunas trans solusindo, semeru scooter club '06 klakah, komunitas indie lumajang, solidaritas buruh migran indonesia - jawa timur, peduli buruh migran, prakarsa rakyat, bulletin sadar, praxis, dll.
(mohon maaf jika ada yang belum disebutkan)
terima kasih atas kunjungan anda, kritik saran yang membangun adalah kunci keberhasilan kami.
deditsabit@smara
thanks for the template design to skinCorner | grunged girl image from dapinoGraphics



